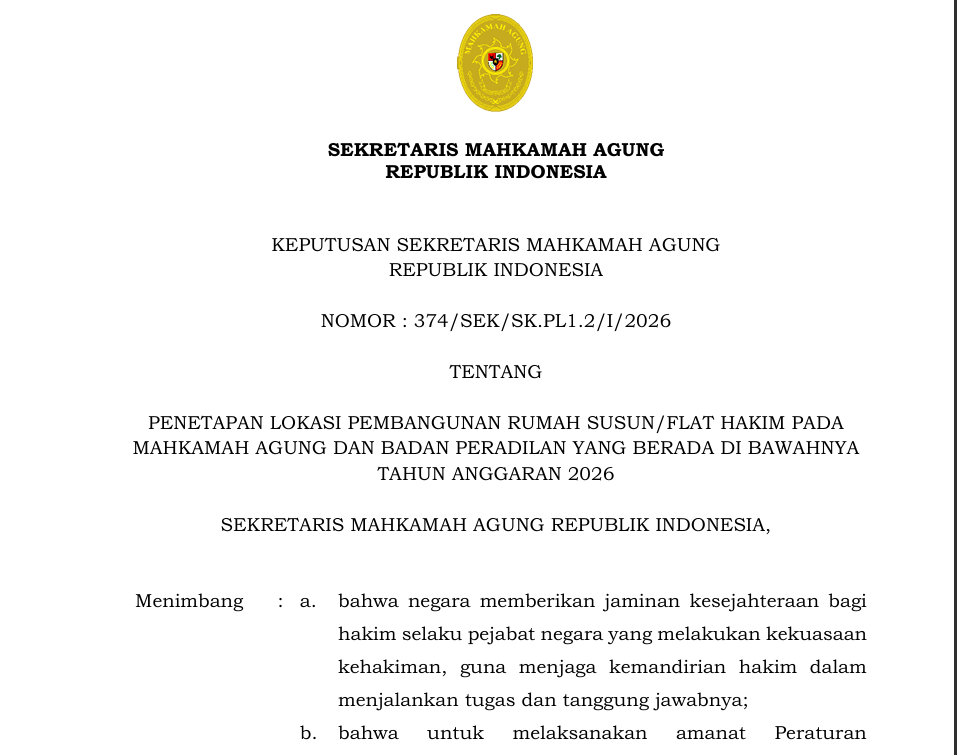Krisis
Ekologis dan Keterbatasan Instrumen Hukum Administratif
Krisis
ekologis di Indonesia berkembang menjadi fenomena struktural yang tidak lagi
dapat dipahami sebagai rangkaian insiden lingkungan yang terpisah. Kerusakan
Hutan Tesso Nilo, yang oleh laporan konservasi WWF digambarkan sebagai salah
satu titik keanekaragaman hayati terpenting di Asia Tenggara, mengilustrasikan
bagaimana fragmentasi habitat, ekspansi perkebunan, dan pembalakan sistematis
menghancurkan integritas ekosistem yang mestinya dilindungi.
Demikian
pula banjir besar yang melanda Sumatra pada akhir 2025 menegaskan hubungan
langsung antara perubahan tutupan lahan, hilangnya daerah resapan, dan
meningkatnya intensitas bencana. Laporan dari berbagai lembaga riset
menunjukkan bahwa kerusakan ekologis tersebut memperburuk akumulasi risiko
hidrometeorologi yang terjadi secara berulang.
Baca Juga: Environmental Ethic Sebagai Pilar Keadilan Ekologis
Fenomena
ini menyingkap satu persoalan mendasar, instrumen perlindungan lingkungan kita
terlalu bergantung pada politik hukum pemerintah. Sejak awal pembentukannya,
rezim perlindungan lingkungan Indonesia dibangun dengan logika
administratif—perizinan, sanksi administratif, dokumen AMDAL, dan standar
teknis.
Struktur
seperti ini tampak rasional dalam pengaturan penggunaan ruang dan aktivitas
industri, tetapi menjadi rapuh ketika arah kebijakan pemerintah bergeser.
Ketika prioritas ekonomi berada di atas perlindungan ekologi, maka izin yang
seharusnya menjadi filter justru berubah menjadi legitimasi kerusakan.
Keterbatasan
ini sejalan dengan kritik Hans Jonas dalam The Imperative of Responsibility
(1984). Jonas menegaskan bahwa dunia modern, dengan skala dan dampak teknologi
yang tak dapat dipulihkan, menuntut tanggung jawab moral yang melampaui
kalkulasi administratif.
Tanggung
jawab itu menuntut kita memandang tindakan pada dampak jangka panjangnya termasuk
dampak ekologis yang mungkin baru terlihat puluhan tahun kemudian. Dalam konteks
inilah, kelemahan struktur hukum lingkungan nasional tampak jelas, dibangun
untuk mengatur kegiatan, bukan untuk mencegah kehancuran sistem kehidupan.
Hal
ini diperjelas lagi oleh konsep planetary boundaries dari Rockström
(2009) dan Steffen (2015), yang menunjukkan bahwa bumi memiliki batas-batas
ekologis yang apabila dilampaui, akan mengancam stabilitas sistem kehidupan
global. Ketika kerusakan ekologi berlangsung pada skala yang telah melewati
kapasitas regulasi administratif, maka pendekatan hukum yang terlalu bergantung
pada pemerintah menjadi tidak memadai. Dengan demikian, masalah ekologis
Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi soal desain struktur hukum
yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai turunan dari kebijakan ekonomi,
bukan sebagai mandat moral negara.
Ecocide
dan Tanggung Jawab Moral Peradilan
Wacana
Ecocide muncul secara global bukan karena dunia tiba-tiba ingin
memperluas kriminalisasi, tetapi karena kerusakan ekologis telah mencapai
tingkat yang tidak dapat dikendalikan oleh instrumen administratif semata.
Panel
Ahli yang dibentuk oleh Stop Ecocide Foundation (2021) mengusulkan
definisi Ecocide sebagai tindakan melawan hukum atau sewenang-wenang
yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa tindakan tersebut berpotensi menyebabkan
kerusakan ekologis yang parah, meluas, atau jangka panjang.
Akademisi
hukum internasional seperti Philippe Sands (2020) menegaskan bahwa dunia
membutuhkan kategori moral baru dalam hukum pidana internasional untuk
merespons krisis lingkungan yang semakin dalam.
Wacana
Ecocide memberi pesan penting, hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan
jangka pendek pemerintah. Bila kerusakan lingkungan dibiarkan tunduk pada
prioritas politik atau ekonomi, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga
keberlanjutan.
Kondisi
ini relevan bagi Indonesia, di mana perlindungan lingkungan masih sangat
bergantung pada arah kebijakan eksekutif. Ketika izin dan standar administratif
menjadi instrumen utama, maka kerusakan sistemik seperti Tesso Nilo dan banjir
Sumatera mudah luput dari mekanisme pertanggungjawaban hukum.
Dalam
konteks ini, peradilan memikul peran yang jauh lebih besar daripada sekadar
menerapkan undang-undang. Hakim memiliki posisi epistemik yang unik, merekalah
yang menentukan bagaimana realitas ekologis dipahami secara hukum. Apakah
kerusakan ekologi hanya dibaca sebagai pelanggaran izin, atau sebagai ancaman
keberlanjutan hidup bersama? Perbedaan cara baca ini menentukan apakah hukum
akan melanggengkan kerusakan atau menghentikannya.
Gagasan
keadilan antar generasi yang dikemukakan Edith Brown Weiss (1989) relevan di
sini. Weiss menunjukkan bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban untuk
menjaga kapasitas ekologis bumi bagi generasi berikutnya.
Dalam
perkara lingkungan, hakim bukan hanya menyelesaikan sengketa antara pihak
berperkara, tetapi memutus arah ekologis masa depan bangsa. Ketika putusan
pengadilan mengabaikan dampak jangka panjang, pengadilan berpotensi ikut
mewariskan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.
Dalam
A Perfect Moral Storm (2011), Stephen Gardiner menjelaskan bahwa krisis
iklim adalah krisis moral karena institusi kita gagal bertindak meskipun
mengetahui risiko besar yang sudah terjadi. Peradilan Indonesia dapat terjebak
dalam krisis moral serupa apabila hanya berfokus pada legalitas administratif
tanpa membaca struktur ekologis yang lebih luas. Dalam konteks inilah, wacana Ecocide
berfungsi sebagai cermin, menuntut peradilan untuk meninjau ulang cara memahami
keadilan dalam era krisis lingkungan global.
Penutup:
Saatnya Peradilan Memikul Mandat Moral Ekologis
Instrumen
administratif yang menjadi fondasi hukum lingkungan Indonesia telah terbukti
tidak cukup menghadapi kerusakan ekologis yang bersifat sistemik.
Ketergantungan pada arah politik pemerintah menjadikan lingkungan hidup sebagai
variabel yang mudah dikompromikan ketika pembangunan ekonomi dijadikan
prioritas utama. Sementara itu, kerusakan ekologis terus berlangsung pada skala
yang mengancam keselamatan generasi mendatang.
Dalam
situasi ini, peradilan tidak boleh memposisikan diri sebagai penafsir pasif
dari kebijakan administratif. Peradilan harus memikul mandat moral untuk
memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat yang melegitimasi kehancuran
ekologis. Wacana Ecocide memberi arah etis bagi peradilan yang
mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi
ancaman terhadap keberlanjutan hidup bangsa.
Maka
pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan mengadopsi Ecocide
sebagai kategori pidana. Pertanyaannya adalah: apakah peradilan Indonesia
memiliki keberanian moral untuk membaca hukum dengan sensibilitas ekologis,
untuk menempatkan keberlanjutan sebagai inti keadilan, dan untuk bertindak
sebagai penjaga peradaban ekologis di tengah krisis global?
Daftar
Pustaka
Gardiner,
S. (2011). A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change.
Oxford University Press.
Jonas,
H. (1984). The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the
Technological Age. University of Chicago Press.
Leopold,
A. (1949). A Sand County Almanac. Oxford University Press.
Rockström,
J. et al. (2009). “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for
Humanity.” Ecology and Society, 14(2).
Steffen,
W. et al. (2015). “Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a
Changing Planet.” Science, 347.
Stop Ecocide
Foundation (2021). Independent Expert Panel: Legal Definition of Ecocide.
Baca Juga: Revisi RUU KUHAP di Ruang Bedah Moral: Keadilan atau Prosedural?
Weiss,
E. B. (1989). In Fairness to Future Generations. United Nations
University Press.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI