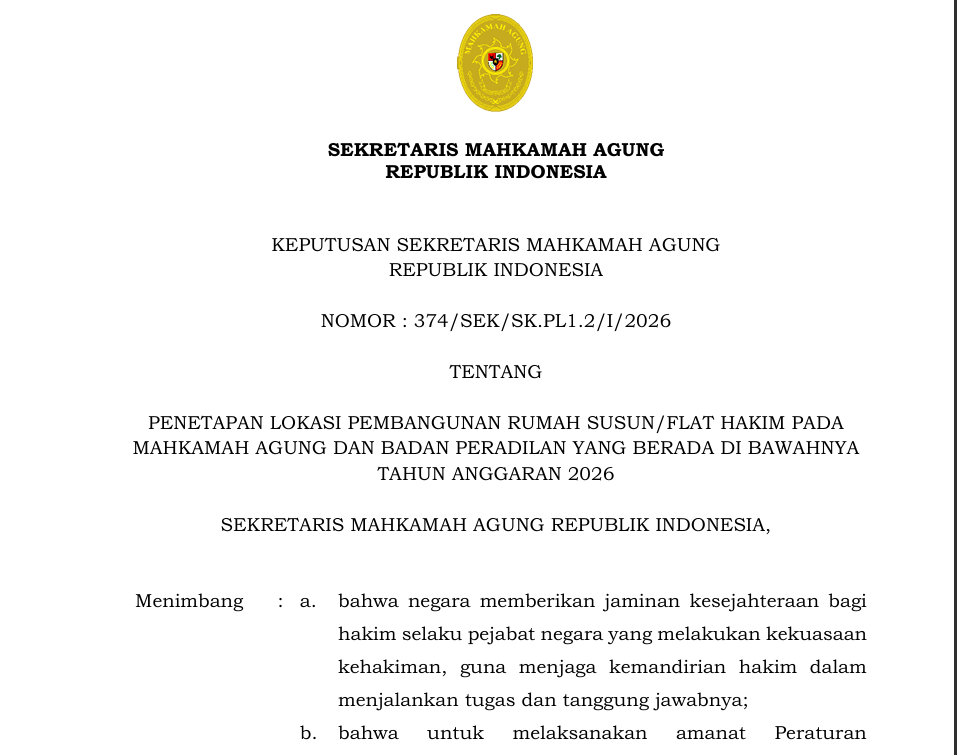Selama
bertahun-tahun, banyak putusan pidana lahir dari kebiasaan yang nyaris tak
disadari. Ketika suatu pasal memuat ancaman minimum khusus, proses berpikir
sering kali bergerak lebih cepat daripada proses menimbang. Angka menjadi titik
berangkat, bukan hasil akhir.
Kebiasaan
ini tidak hanya hidup di ruang sidang, tetapi juga dalam cara aparat penegak
hukum memahami berat ringannya suatu kejahatan. Dalam perkara narkotika
contohnya, terutama yang bersumber dari Pasal 112 dan Pasal 114, pidana kerap
dijatuhkan dengan keyakinan bahwa undang-undang memang menghendaki hukuman
berat, sehingga pertanyaan tentang peran konkret terdakwa dan tingkat
kesalahannya terasa sekunder.
Kondisi
tersebut melahirkan efek penyamarataan. Perbedaan peran antara bandar, perantara,
kurir kecil, hingga penyalahguna yang terjerat pasal kepemilikan sering kali
tidak terpotret secara utuh. Minimum khusus menutup ruang nuansa.
Baca Juga: Revisi RUU KUHAP di Ruang Bedah Moral: Keadilan atau Prosedural?
Dalam
situasi seperti ini, angka pidana berfungsi sebagai pengganti penilaian, bukan
sebagai hasil dari penilaian itu sendiri. Pemidanaan bergerak mendekati
rutinitas administratif, padahal hakikatnya merupakan proses bernalar yang
sarat tanggung jawab etik.
Kini
situasinya berubah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
menghapus ancaman minimum khusus bagi sebagian besar undang-undang di luar
KUHP.
Perubahan
ini tampak teknis, tetapi sesungguhnya mengguncang kebiasaan lama yang selama
ini kita terima hampir tanpa dipertanyakan. Ketika angka minimum tidak lagi
tersedia, pertanyaan yang tak terelakkan muncul. Jika bukan minimum khusus, apa
yang seharusnya memandu aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan
pidana. Di titik inilah pemidanaan kembali menuntut keberanian berpikir, bukan
sekadar kepatuhan pada rumusan pasal.
Pesan
normatif penghapusan minimum khusus
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah lanskap tersebut dengan
cara yang senyap namun tegas. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini
menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP,
dengan pengecualian terbatas pada tindak pidana berat terhadap hak asasi
manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Pilihan pengecualian ini
menunjukkan adanya diferensiasi normatif yang serius tentang jenis kejahatan
apa yang benar-benar dipandang luar biasa.
Pesan
yang dapat dibaca dari pengaturan ini adalah tidak semua kejahatan yang selama
ini diperlakukan keras memang layak ditempatkan dalam kategori luar biasa.
Dalam
konteks narkotika, penghapusan minimum khusus mengandung pengakuan bahwa
pendekatan pemidanaan yang seragam dan kaku tidak selalu menghasilkan keadilan
maupun efektivitas. Kritik terhadap kecenderungan overcriminalization dan
overpunishment telah lama menunjukkan bahwa hukuman berat yang
dipaksakan secara struktural sering gagal membedakan tingkat kesalahan dan
bahaya nyata dari suatu perbuatan (Husak, 2008).
Arah
tersebut menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan Pasal 54 KUHP Nasional.
Ketentuan ini mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang melekat
pada pelaku dan perbuatannya, mulai dari bentuk kesalahan, motif, sikap batin,
hingga dampak pidana terhadap masa depan pelaku. Dengan demikian, sistem hukum
pidana nasional sedang diarahkan kembali pada pemidanaan yang berbasis
penilaian, bukan sekadar kepatuhan pada konstruksi ancaman.
Penghapusan
minimum khusus bukan sinyal untuk melemahkan respons pidana, melainkan upaya
mengembalikan rasionalitas pemidanaan. Negara tidak sedang menaruh seluruh
beban penilaian pada pembentuk undang-undang, tetapi mengembalikannya kepada
aparat penegak hukum di ruang peradilan, dengan hakim sebagai penentu akhirnya.
Pada titik ini, perubahan norma menuntut perubahan cara berpikir. Jika
pemidanaan tetap dijatuhkan seolah minimum khusus masih mengikat, maka
reformasi berhenti sebagai teks hukum belaka.
Perubahan
rezim pemidanaan ini juga menuntut kehati-hatian agar diskresi yang luas tidak
berubah menjadi inkonsistensi. Tanpa minimum khusus, risiko baru muncul dalam
bentuk disparitas pemidanaan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Di
sinilah pentingnya membedakan antara diskresi yang bernalar dan kebebasan yang
tak terukur. Diskresi bukan ruang untuk intuisi semata, melainkan ruang untuk argumentasi
yang dapat diuji.
Hakim
perlu mulai membiasakan diri menyusun pertimbangan pemidanaan secara lebih
eksplisit dan terstruktur. Bukan dalam bentuk formula kaku, tetapi melalui
penjelasan jujur tentang mengapa suatu pidana dianggap layak. Penjelasan mengenai
peran terdakwa, tingkat kontrol terhadap peristiwa, serta hubungan antara
perbuatan dan dampak sosialnya menjadi semakin penting, sejalan dengan gagasan
individualisasi pidana dalam teori pemidanaan modern (Ashworth, 2015).
Dalam
konteks narkotika contohnya, pendekatan ini akan mendorong pemisahan yang lebih
tegas antara pelaku yang menggerakkan pasar dan pelaku yang berada di lapis
terbawah. Pemidanaan tidak lagi ditentukan oleh beratnya ancaman pasal,
melainkan oleh kualitas kesalahan. Dengan cara ini, penghapusan minimum khusus
justru memperkuat legitimasi putusan. Putusan tidak hanya sah secara normatif,
tetapi juga masuk akal bagi publik dan bagi terdakwa yang dijatuhi pidana.
Dari
angka ke pertimbangan
Penghapusan
minimum khusus membawa konsekuensi yang tidak ringan bagi semua yang terlibat
dalam sistem peradilan pidana. Khususnya pada hakim. Tidak ada lagi angka yang
dapat dijadikan tameng psikologis. Setiap pidana harus lahir dari pertimbangan
yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Dalam perkara narkotika, hakim
dituntut membaca secara lebih jernih posisi terdakwa dalam keseluruhan
peristiwa, bukan sekadar kecocokan unsur delik.
Pemidanaan
dalam kerangka ini kembali menjadi seni bernalar. Tujuan pemidanaan tidak lagi
dipahami secara abstrak, melainkan diuji secara konkret. Apakah pidana tertentu
proporsional dengan kesalahan. Apakah mencegah kejahatan atau justru
memproduksi ketidakadilan baru. Prinsip proportionality dalam teori
pemidanaan modern menegaskan bahwa keadilan pidana tidak terletak pada beratnya
hukuman, melainkan pada keseimbangan antara perbuatan dan respons negara (von
Hirsch, 1976).
Ruang
diskresi yang lebih luas juga menuntut kedewasaan. Kita tidak sedang diminta
untuk menjadi lunak, melainkan untuk menjadi jujur dalam menimbang. Pidana
berat tetap sah dan diperlukan bagi pelaku yang memiliki peran sentral dan niat
jahat yang jelas. Namun pidana yang lebih ringan juga sah ketika fakta
menunjukkan tingkat kesalahan yang berbeda. Keberanian intelektual diperlukan
untuk keluar dari kebiasaan lama yang menyamakan kerasnya pidana dengan
keadilan.
Pada
akhirnya, meskipun perubahan ini menyentuh seluruh aparat penegak hukum,
tanggung jawab pemidanaan tetap berakhir di ruang musyawarah hakim. Di sanalah
cara berpikir kita diuji secara paling konkret. Ketika angka ditarik mundur,
hakim dipanggil untuk melangkah maju. Pemidanaan kembali diletakkan pada
tempatnya sebagai keputusan yudisial yang bernalar, manusiawi, dan bertanggung
jawab. (ldr)
Referensi
Andrew
Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, 6th ed., Cambridge University
Press, Cambridge, 2015
Douglas
Husak, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford
University Press, Oxford, 2008
Andrew
von Hirsch, Doing Justice: The Choice of Punishments, Hill and Wang, New
York, 1976
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Baca Juga: Hilangnya Ancaman Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI