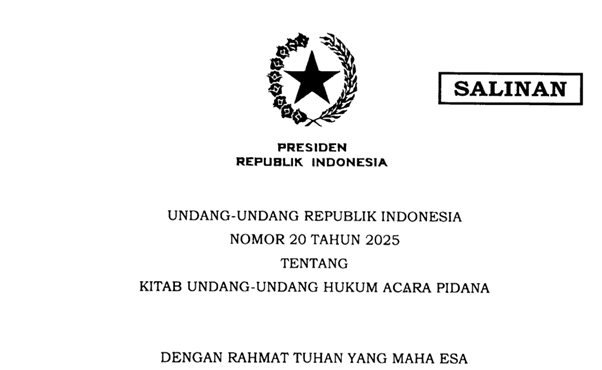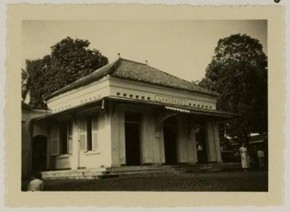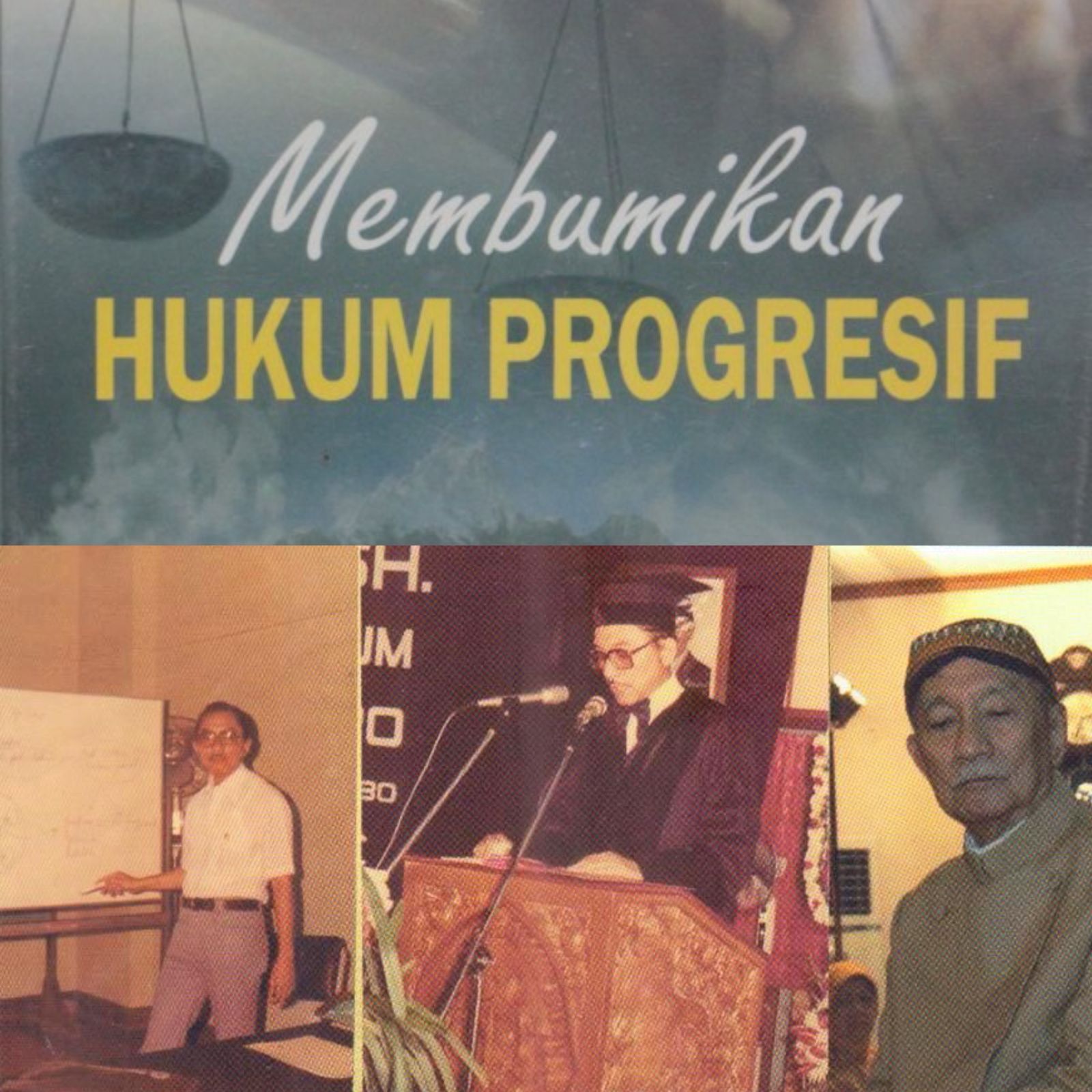Hukum progresif adalah
sebuah mazhab pemikiran yang menolak absolutisme teks normatif dan kepastian
formalistik, serta menekankan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri,
melainkan untuk manusia.
Inti filosofis dari hukum progresif adalah gagasan
bahwa hukum harus selalu berpihak pada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan
harus bergerak maju melampaui batas-batas undang-undang yang kaku, bahkan jika
harus "mendobrak" tatanan yang ada.
Dalam upaya pencarian keadilan substantif ini, hukum
progresif secara fundamental berbagi akar dan resonansi filosofis yang mendalam
dengan pemikiran-pemikiran Timur, khususnya konsep-konsep harmoni, keseimbangan
kosmos, dan moralitas non-dualistik.
Baca Juga: Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia
Melepaskan
Diri dari Formalisme Barat
Hukum progresif muncul sebagai kritik tajam
terhadap hegemoni positivisme hukum yang dibawa oleh tradisi Barat, dimana
hukum dipandang identik dengan undang-undang (tertulis) dan keabsahannya hanya
diukur dari prosedur pembentukannya.
Positivisme seringkali mengorbankan keadilan riil
demi kepastian formal, menghasilkan putusan yang berdimensi kepastian namun
dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Satjipto Rahardjo (2006) menyerukan
kembali pada spirit humanisme hukum, bahwa hukum adalah proses memanusiakan
manusia.
Pada titik inilah hukum progresif mulai
bersinggungan dengan pandangan filsafat timur. Filsafat hukum barat cenderung
bersifat dualistik: subjek-objek, benar-salah, hitam-putih, legal-ilegal.
Sebaliknya, filsafat timur, seperti yang tercermin dalam ajaran Taoisme,
Konfusianisme, dan ajaran Jawa seperti Sangkan Paraning Dumadi,
menekankan pada integrasi, keseimbangan (Yin dan Yang), dan jalan tengah
(Majjhimāpaṭipadā dalam Buddhisme).
Keseimbangan
Sebagai Tujuan Hukum
Inti dari
berbagai mazhab filsafat timur adalah konsep harmoni (seperti Tao dalam
Taoisme atau Rta dalam Hinduisme), yaitu keteraturan alam semesta yang
menuntut manusia untuk hidup selaras. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk
menciptakan konflik atau ketidakseimbangan, melainkan alat untuk
mengembalikannya.
Dalam
konteks hukum progresif, "mendobrak hukum" bukan berarti ugal-ugalan,
melainkan upaya radikal untuk mencari kembali keseimbangan sosial yang
terganggu (Rahardjo, Satjipto., 2007). Ketika hukum formal (positif) justru
menciptakan ketidakadilan, Hakim progresif didorong untuk menggunakan hati
nuraninya sebagai sebuah sumber kearifan yang melampaui undang-undang untuk menciptakan
putusan yang berlandaskan hati nurani.
Hati
nurani ini, dalam pandangan filsafat timur, adalah cerminan dari hukum kosmis
atau hukum alam yang sejati, yang selalu menuntut kebaikan dan keseimbangan.
Hakim progresif, dengan demikian, tidak hanya bertindak sebagai corong
undang-undang (sebagaimana diktum positivisme), tetapi sebagai pemelihara
harmoni sosial.
Etika
sebagai Landasan Hukum
Konfusianisme,
yang selalu menekankan pada Ren (kemanusiaan, kebajikan) dan Li
(aturan, ritual yang benar), menyediakan landasan etis yang kuat bagi hukum progresif.
Dalam Konfusianisme, aturan formal (Li) harus selalu dilayani oleh
spirit kebajikan (Ren). Sebuah aturan tanpa kebajikan akan menjadi
tirani.
Hukum progresif
mengadopsi pandangan serupa: teks undang-undang adalah Li, namun rohnya
haruslah Ren, yaitu keadilan substantif yang memanusiakan. Hukum
progresif menolak pendekatan mekanis dimana seorang Hakim cukup mencocokkan
fakta dengan pasal.
Sebaliknya,
ia menuntut kearifan (wisdom) dan kepedulian (compassion) dalam
setiap putusan. Keputusan harus dipertimbangkan dampaknya terhadap seluruh
jalinan kehidupan—korban, pelaku, dan masyarakat. Hal tersebut merupakan
manifestasi dari etika tanggung jawab yang sangat resonan dengan ajaran filsafat
timur.
Non-Dualisme
Hukum dan Moralitas
Filsafat timur,
khususnya Buddhisme dan Taoisme, mengajarkan non-dualisme, yaitu pandangan
bahwa segala sesuatu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak (Shi,
Y. Z., 2018). Dalam konteks hukum progresif, prinsip ini diaplikasikan
untuk menolak pemisahan tajam antara hukum dan moralitas (sebagaimana diyakini
oleh positivisme).
Bagi hukum
progresif, hukum harus bermoral, dan putusan yang tidak bermoral adalah putusan
yang cacat secara filosofis, meskipun sah secara prosedural. Hakim progresif adalah
mereka yang berani mengambil risiko untuk menyuntikkan nilai-nilai keadilan dan
kemanusiaan ke dalam norma yang bisu.
Mereka
tidak hanya melihat perbuatan yang melanggar pasal (formalistik), tetapi juga
melihat ada penderitaan manusia di baliknya (moral-humanis). Hal tersebut adalah
perwujudan dari pandangan bahwa "hukum yang baik haruslah baik secara
substansi"–suatu pengakuan bahwa aspek batin dan etis tidak dapat
dipisahkan dari aspek lahiriah dan prosedural (Supomo., 1951).
Hukum
sebagai Pengabdian (Pelayan)
Sebuah
refleksi mendalam dari filsafat timur adalah peran kepemimpinan dan kekuasaan
sebagai pengabdian (seva). Para pemimpin (termasuk penegak hukum) adalah
pelayan rakyat, bukan tuan. Hukum progresif menganut filosofi ini secara
eksplisit: hukum adalah pelayan masyarakat dan kemanusiaan.
Dalam
praktik, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus keluar dari menara
gading kekuasaan mereka dan turun ke tengah masyarakat untuk memahami persoalan
riil.
Penegakan
hukum yang progresif bukan sekadar implementasi paksa norma, tetapi proses
dialektika tanpa henti dengan realitas sosial. Hal ini membutuhkan kerendahan
hati, sebuah kebajikan yang sangat dihormati dalam tradisi filsafat timur untuk
mengakui keterbatasan teks hukum dan mencari solusi inovatif yang sesuai dengan
kepribadian bangsa dan nilai-nilai kasih sayang.
Kontemplasi
dan Kearifan Lokal (Local Wisdom)
Hukum progresif
sangat menekankan pada kearifan lokal (local wisdom) dan nilai-nilai
yang hidup di masyarakat (living law). Secara filosofis, hal tersebut
adalah wujud pengakuan bahwa kebenaran dan keadilan tidak hanya bersumber dari
pusat kekuasaan negara atau teks undang-undang yang bersifat universal, tetapi
juga dari proses kontemplasi masyarakat dalam menghadapi masalah kehidupan (Waluyo,
Bambang., 2014).
Tradisi
filsafat timur penuh dengan kearifan lokal yang telah teruji waktu, yang
menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih restoratif dan
kekeluargaan, seperti musyawarah, gotong royong, atau praktik Ngelmu
Pring (filosofi bambu yang lentur namun kuat). Hukum progresif
mengintegrasikan kearifan ini untuk mengisi kekosongan atau kegagalan hukum
negara, dengan pandangan bahwa hukum yang efektif harus bersifat kontekstual
dan mengakar.
Penutup
Hukum progresif adalah jembatan yang menghubungkan
rasionalitas hukum modern dengan spiritualitas dan humanisme filsafat timur. Ia
adalah ajakan untuk meninggalkan "hukum yang dingin" (ius
constitutum) yang hanya peduli pada legalitas, menuju "hukum yang
berhati" (ius constituendum) yang dipandu oleh moralitas, kearifan,
dan hasrat untuk memulihkan harmoni.
Dengan menempatkan hati nurani,
kearifan, dan prinsip keseimbangan kosmik di atas teks, hukum progresif bukan
hanya revolusi dalam pemikiran hukum Indonesia, tetapi juga kontribusi unik
dalam dialog hukum global, yang menegaskan bahwa keadilan sejati terletak pada
kemampuan hukum untuk memanusiakan manusia, bukan memaksakan manusia masuk ke
dalam hukum normatif yang masinal dan statis. (aar/ldr)
Daftar
Referensi
Rahardjo, Satjipto. (2006). Mengenal
Hukum Progresif. Genta Publishing.
Rahardjo, Satjipto. (2007). Biarkan
Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Hukum. Kompas.
Shi, Y. Z. (2018). Taoism
and the Idea of Natural Law. Routledge.
Supomo. (1951). Sistem
Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Djambatan.
Baca Juga: Buka Pelatihan Filsafat, Kepala BSDK: Hakim Jangan Jadi Juru Pembaca Pasal
Waluyo, Bambang. (2014). Filsafat
Hukum dan Perkembangan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI