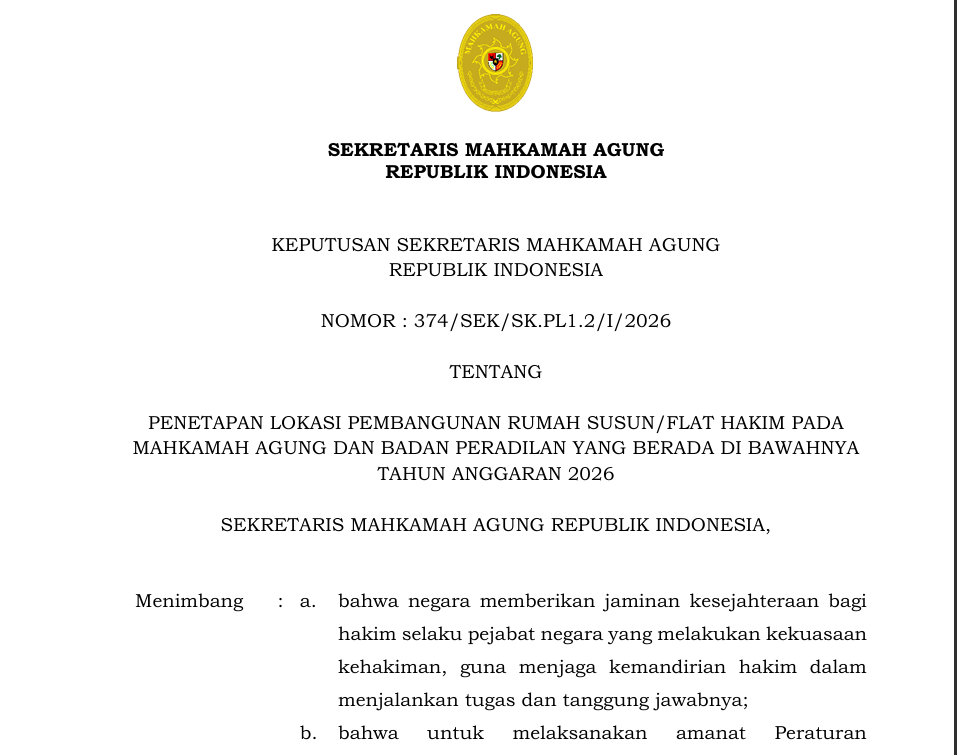Perceraian
di Indonesia tidak hanya persoalan emosional, tetapi juga proses hukum yang
sarat konsekuensi. Di balik setiap permohonan cerai, terdapat jalur normatif
yang mengikat para pihak baik mengenai putusnya perkawinan itu sendiri maupun
kewajiban nafkah yang timbul setelahnya. Menariknya, cara hukum memandang
hubungan antara nafkah dan keabsahan perceraian berbeda antara satu rezim
dengan rezim lainnya, dimana rezim hukum peradilan agama memiliki karakteristik
tertentu yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
REZIM
HUKUM PERADILAN AGAMA
Dalam
perkara cerai talak, suami mengajukan permohonan ke pengadilan dan mengikuti
proses pemeriksaan, mediasi, hingga putusan yang memberikan izin untuk
mengucapkan ikrar talak. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan
menetapkan hari sidang untuk melaksanakan ikrar talak. Pada tahap inilah
kewajiban suami sebagaimana diatur Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam muncul ke
permukaan: mut’ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, pelunasan mahar, serta biaya
hadhanah.[1]
Baca Juga: Menelisik Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian
Meskipun
secara konseptual kewajiban ini merupakan akibat hukum pasca perceraian, dalam
praktik majelis hakim kerap meminta agar suami menyelesaikan sebagian atau
seluruh kewajiban tersebut sebelum ikrar dilaksanakan. Pendekatan ini diperkuat
oleh SEMA No. 1 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa ikrar talak tetap dapat
dilaksanakan meskipun suami belum memenuhi kewajiban nafkah, sepanjang istri
tidak keberatan.[2] Jika istri menyatakan keberatan, sidang ikrar talak akan
ditunda.
Penundaan
ini membawa implikasi serius. Bila dalam waktu 6 (enam) bulan suami tidak hadir
untuk melaksanakan ikrar talak, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan
Agama izin mengucapkan talak gugur, dan perceraian tidak dapat diajukan kembali
dengan alasan yang sama.[3] Dengan demikian, kegagalan memenuhi nafkah bukan
secara langsung yang menggugurkan izin, tetapi keberatan istri dan
ketidakhadiran suami dalam tenggat tersebut.
REZIM
HUKUM PERDATA NASIONAL
Sistem
ini berbeda ketika kita mengalihkan pandangan ke kerangka hukum perdata
nasional. KUH Perdata sejak lama mengenal kewajiban nafkah pasca perceraian,
bahkan dalam Pasal 227 KUH Perdata pemberian nafkah berlaku sampai salah satu
mantan pasangan meninggal dunia.[4] Namun pemenuhan nafkah tidak pernah
mempengaruhi sah atau tidaknya perceraian. Bahkan Pasal 225 KUH Perdata memberi
ruang bagi hakim untuk menetapkan tunjangan hidup dengan membebankan pada harta
pihak lain apabila pihak yang berkewajiban tidak memiliki penghasilan yang
cukup.[5]
PENEGAKAN
NAFKAH MELALUI INSTRUMEN KEPERDATAAN DAN DISIPLIN
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 juga menyebutkan
bahwa suami dapat diwajibkan memberi nafkah kepada mantan istri atau anak.[6]
Namun, sebagaimana dalam KUH Perdata, tidak ada ketentuan bahwa perceraian
dapat menjadi batal atau tidak efektif bila nafkah tidak dipenuhi. Penegakan
hak dilakukan melalui jalur eksekusi, bukan melalui pembatalan proses
perceraian.
Khusus
untuk pegawai negeri sipil, kewajiban nafkah diperkuat dengan Pasal 16 PP No.
45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa PNS yang tidak memenuhi kewajiban
pemberian nafkah kepada mantan istri atau anak berdasarkan putusan pengadilan
dapat dikenai hukuman disiplin berat.[7] Namun sanksi ini pun tidak menyentuh
keabsahan status perceraian—yang dihukum adalah pelanggaran disiplin, bukan
putusnya perkawinan.
Sementara
itu, bagi warga negara non-Muslim, yang tunduk sepenuhnya pada hukum perdata
nasional, jaminan nafkah ditegakkan melalui instrumen keperdataan seperti sita
marital untuk menjamin pemenuhan hak finansial. Mekanisme ini berlandaskan
Pasal 190 KUH Perdata, Pasal 823 Rv, dan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9
Tahun 1975, yang memberi ruang bagi hakim untuk mengamankan hak nafkah melalui
pengaturan harta kekayaan.[8] Pendekatan ini sekali lagi menunjukkan bahwa
sistem perdata memisahkan tegas antara keabsahan perceraian dan penegakan hak
nafkah.
PENUTUP
Dalam
perspektif perbandingan, sistem hukum keluarga Islam dan sistem hukum perdata
nasional sebenarnya bekerja menuju tujuan yang sama, yakni melindungi pihak
yang rentan dalam putusnya perkawinan. Namun jalur yang ditempuh berbeda. Hukum
perdata nasional menekankan penegakan hak melalui mekanisme eksekusi, sedangkan
praktik peradilan agama mengintegrasikan perlindungan itu ke dalam prosedur
pelaksanaan talak. Pada akhirnya, perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan,
melainkan pluralitas pendekatan hukum yang sama-sama dirancang untuk mencegah
ketidakadilan dalam peristiwa perceraian.
DAFTAR
REFERENSI
[1]
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.
[2] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Agama.
[3] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun
2009, Pasal 70 ayat (6).
[4]
KUHPerdata, Pasal 227.
[5]
KUHPerdata, Pasal 225.
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 41; PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 24.
Baca Juga: Mencermati Nebis In Idem dalam Perkara Perceraian
[7] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS,
Pasal 16.
[8] KUHPerdata Pasal 190; Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Pasal 823; PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI