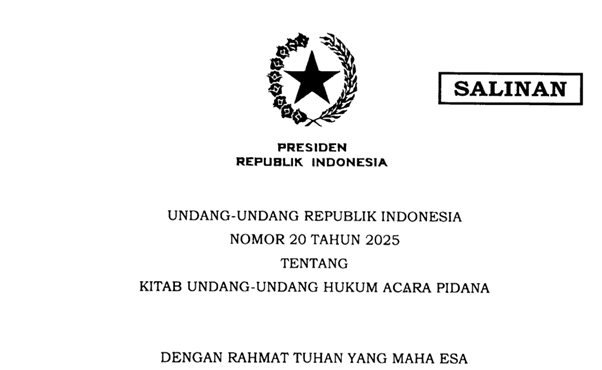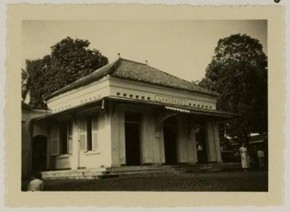Dalam ruang lingkup hukum,
keadilan seringkali dipandang sebagai konstruksi yang objektif, rasional, dan
harus bersifat universal, sebuah prinsip yang berdiri di atas emosi dan
sentimen individu, seperti kesetaraan di hadapan hukum (equality before the
law).
Namun,
bagi individu yang mengalami langsung dampak dari suatu peristiwa,
ketidakadilan memiliki definisi yang jauh lebih personal dan mendalam, yang
dapat dirangkai dalam satu pertanyaan dan jawaban “Kapan sesuatu dikatakan
tidak adil? Ketika sesuatu itu terasa sangat menyakitkan”.
Pernyataan
ini adalah resonansi kuat yang menyentuh inti terdalam dari penderitaan.
Pernyataan ini ingin memberikan argumen bahwa rasa sakit dan penderitaan
(bersifat subjektif) yang dialami oleh korban atau pihak yang dirugikan
bukanlah sekedar dampak dari ketidakadilan, melainkan indikator substantif yang
menuntut adanya intervensi filosofis dan hukum. Penulis menggunakan metafora
“rasa sakit” untuk menjembatani jurang antara keadilan yang objektif dan
pengalaman keadilan yang subjektif melalui lensa filsafat hukum.
Baca Juga: Pembantaran (Stuiting): Permasalahan dan Solusi Praktis
Filsafat
Klasik: Keadilan sebagai Keseimbangan yang Terganggu
Dalam
tradisi filsafat, keadilan selalu terkait dengan konsep keseimbangan dan
kesejahteraan. Filsuf Hukum terkenal, Aristoteles membagi keadilan menjadi
Keadilan Distributif dan Keadilan Korektif. “Rasa Sakit” sangat relevan dengan
keadilan korektif. Keadilan Korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan yang
terganggu akibat adanya kerugian atau pelanggaran.
Sebagai
contoh, jika A melakukan suatu perbuatan yang merugikan si B, maka keseimbangan
alamiah si B terganggu. Rasa sakit adalah manifestasi dari defisit keseimbangan
ini. Tugas hukum adalah mengembalikan status quo dengan memberikan
kompensasi atau hukuman yang sepadan, dengan tujuan untuk menghilangkan defisit
(rasa sakit) yang timbul dari kerugian tersebut.
Aliran
Utilitarianisme
Berdasarkan
sudut pandang Utilitarian, keadilan adalah Tindakan yang menghasilkan
kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (the
greatest happiness for the greatest number). Ketika suatu Tindakan
menyebabkan rasa sakit yang intens pada seseorang, hal itu mengurangi total
kebahagiaan (atau meningkatkan total penderitaan) dalam masyarakat. “Rasa
sakit” menjadi data empiris yang menunjukkan bahwa suatu Tindakan telah gagal
memberikan manfaat berupa kebahagiaan.
Tataran
Praktek: Antara Prosedur dan Substansi
Mazhab
positivisme hukum cenderung fokus pada keadilan prosedural. Selama hukum dibuat
dan diterapkan melalui prosedur yang sah, hasilnya dianggap sah, bahkan jika
terasa tidak adil secara moral bagi individu. Namun, disinilah titik
krusialnya.
Rasa
sakit adalah salah satu bukti bahwa hukum, meskipun telah diterapkan secara
benar secara prosedural, tetapi dapat gagal secara substantif. Rasa sakit
menjadi kritik tajam terhadap formalisme yang kaku, menuntut agar hukum tidak
hanya berjalan dengan benar, tetapi juga menghasilkan kebaikan. Rasa sakit
(penderitaan) dapat berfungsi sebagai sinyal alarm moral yang memaksa sistem
hukum untuk melihat melampaui aturan formal dan menerapkan prinsip keadilan
substantif.
Baca Juga: Hukum Progresif dan Konstelasi Filsafat Timur: Menemukan Keadilan Substantif dalam Harmoni Kosmos
Dalam
praktek hukum, rasa sakit ini diterjemahkan menjadi kategori yang dapat dinilai
dan diakui secara hukum sebagai kerugian immaterial, yang dapat “dibayar”
melalui 2 (dua) sarana, yaitu:
- Ganti
Rugi Moral, seperti dalam kasus perdata, yang mana rasa sakit psikologis,
emosional, dan penderitaan diakui sebagai kerugian yang harus diganti. Keadilan
muncul ketika sistem hukum memvalidasi dan memberikan kompensasi atas
penderitaan yang dialami;
- Keadilan
Restoratif, yang berfokus pada kebutuhan korban, bukan hanya pada hukuman
pelaku. tujuan utamanya adalah pemulihan dan perbaikan kerugian. Dalam konteks
ini, rasa sakit korban menjadi titik fokus. keadilan dianggap tercapai ketika
kebutuhan pemulihan korban terpenuhi dan penderitaannya diakui oleh pelaku,
bahkan oleh masyarakat.
Akhir
kata, meskipun hukum harus beroperasi secara prosedural dan rasional, ia tidak
boleh kehilangan sensitivitasnya terhadap pengalaman manusia. Rasa sakit
bukanlah emosi yang harus diabaikan, melainkan dapat menjadi standar minimal
dari keadilan substantif. Jika suatu putusan atau Tindakan hukum, terlepas dari
keabsahan proseduralnya, meninggalkan luka dan rasa sakit yang mendalam,
Penulis melihat ia belum dapat mencapai misi tertingginya untuk menegakkan
keadilan.
Keadilan sejati terjadi ketika norma hukum yang objektif tidak hanya menghukum yang salah, tetapi juga mampu mengobati dan memulihkan rasa sakit dari yang dirugikan. Inilah panggilan bagi filsafat hukum, untuk terus berjuang agar hukum tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga adil dalam hati dan pengalaman manusia. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI