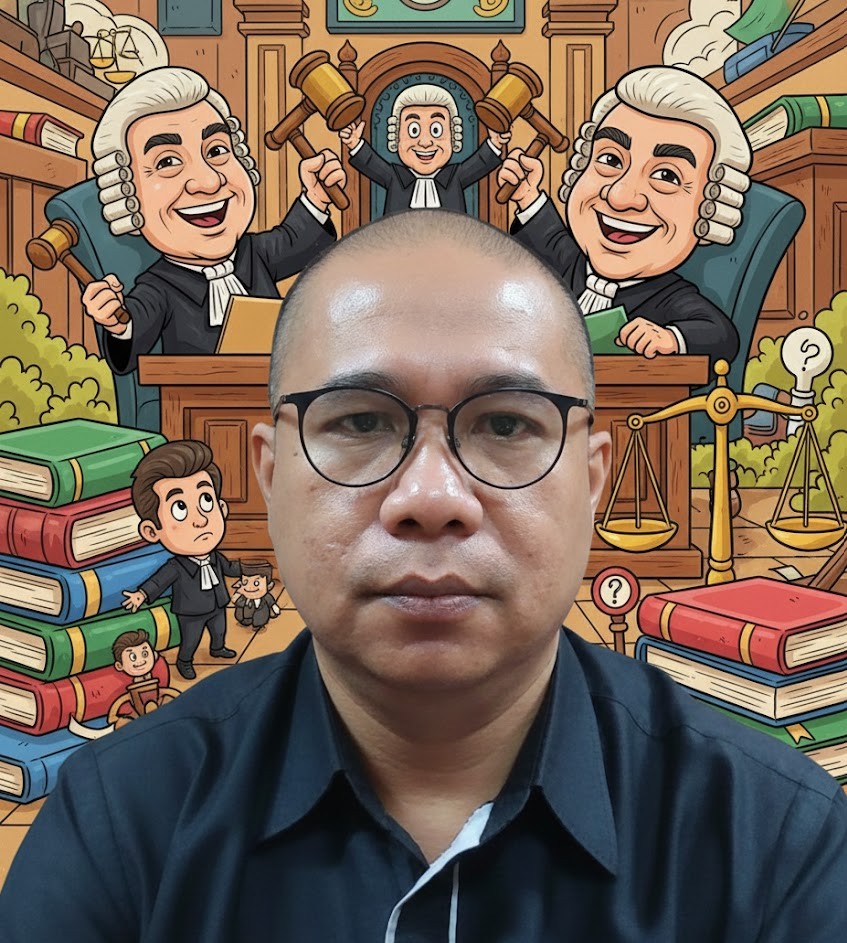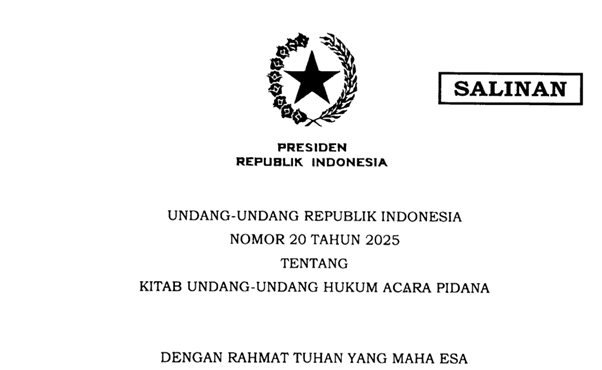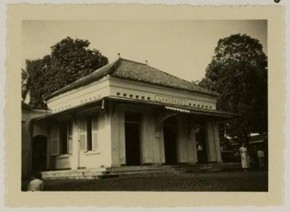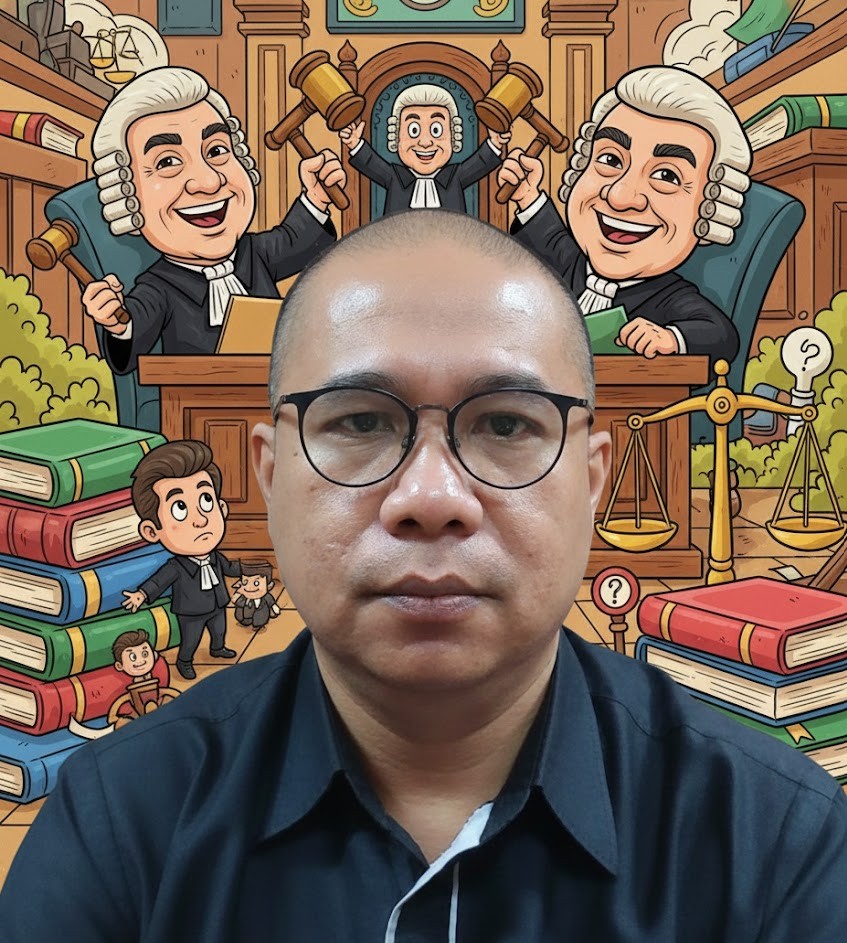Perdebatan yurisdiksi antara pengadilan negara dan arbitrase
internasional bukan sekadar masalah teknis, melainkan pertarungan ideologis
mempertahankan kedaulatan ekonomi.
Arbitrase kini bertransformasi menjadi rezim ekspansif,
melalui doktrin seperti Group of Companies, memaksakan yurisdiksi asing
dan menggerus hukum nasional. Ini adalah bentuk kolonisasi hukum, bukan sekadar
transplantasi norma.
Khususnya dalam sengketa Proyek Strategis Nasional,
intervensi arbitrase asing mengancam kepentingan publik dan melanggar Pasal 33
UUD 1945. Opini ini menggugat "mitos netralitas" arbitrase yang
berpotensi melegalkan kerugian negara melalui forum tertutup tanpa
akuntabilitas publik.
Doktrin "pro-bisnis" asing tidak boleh menjadi
kuda Troya yang melemahkan sistem hukum nasional. Ketertiban umum dan ekonomi
konstitusi harus ditempatkan sebagai norma tertinggi untuk menolak penaklukan
kedaulatan negara yang berlindung di balik topeng otonomi privat.
Fondasi arbitrase adalah konsensus mutlak.
Namun, doktrin Group of Companies mendestruksi postulat ini dengan
memaksakan yurisdiksi kepada entitas non-penandatangan berbasis "realitas
ekonomi tunggal". Secara dogmatik, konstruksi ini cacat karena secara
diametral melanggar asas privity of contract (Pasal 1315 dan 1340 KUH
Perdata) serta prinsip separate legal personality, menciptakan
"konsensus fiktif" yang menabrak syarat imperatif persetujuan
tertulis dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.
Dalam perspektif kritis, doktrin ini bukan
sekadar deviasi prosedural, melainkan manifestasi "imperialisme
yurisdiksi" yang dirancang elit transnasional demi komodifikasi keadilan.
Penerapannya merupakan bentuk penyelundupan hukum yang mengebiri kedaulatan yudisial
negara dan merampas hak konstitusional entitas nasional.
Secara
praksis, doktrin ini diterapkan secara asimetris dan oportunistik: agresif
menjerat aset strategis lokal, namun impoten menuntut pertanggungjawaban induk
perusahaan asing. Oleh karena itu, doktrin ini sejatinya adalah instrumen
neokolonialisme hukum yang meruntuhkan integritas tatanan hukum nasional.
Doktrin separabilitas, yang mempostulatkan
otonomi klausula arbitrase, menghadapi keruntuhan dogmatik saat berbenturan
dengan meta-norma fraus omnia corrumpit (kecurangan membatalkan
segalanya). Dalam sengketa infrastruktur strategis yang terkontaminasi fraud
sistemik atau korupsi, klausula arbitrase sejatinya adalah "buah dari pohon
beracun" yang cacat mutlak. Memaksakan keberlakuannya melanggar syarat
kausa halal (Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata), sehingga perjanjian tersebut
batal demi hukum.
Argumentasi Kompetenz-Kompetenz gugur di
hadapan defisit wewenang investigatif tribunal privat dan potensi konflik kepentingan
ekonomi arbitrator.
Menyerahkan ajudikasi perbuatan corrupt pada
forum arbitrase sama dengan melegitimasi pencucian uang hasil kejahatan. Oleh
karena itu, pengadilan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan
piercing the veil of separability.
Klausula arbitrase harus dinyatakan inoperable karena kesepakatan prosedural
tidak dapat dipisahkan dari itikad buruk substansial yang melahirkannya.
Intervensi yudisial ini adalah afirmasi supremasi keadilan substantif untuk
mencegah penyalahgunaan forum arbitrase sebagai benteng impunitas bagi
kejahatan korporasi.
Diskursus arbitrabilitas sengketa Proyek
Strategis Nasional tidak dapat dilepaskan dari mandat konstitusional Pasal 33
UUD 1945. Sebagai welfare state, Indonesia menempatkan penguasaan aset
vital di tangan negara, sehingga sengketa terkait infrastruktur strategis
bukanlah isu komersial murni, melainkan persoalan ketertiban umum (public
policy) yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
Menyerahkan sengketa bermuatan fraud, perbuatan corrupt atau
praktik monopoli kepada tribunal arbitrase asing adalah tindakan
inkonstitusional. Arbitrator privat tidak memiliki legitimasi demokratis maupun
mandat untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Lebih fundamental lagi, ranah
hukum publik yang memaksa, seperti hukum persaingan usaha, adalah domain
eksklusif peradilan negara yang bersifat non-arbitrable.
Oleh karena itu, paradigma "Ekonomi
Konstitusi" harus ditegakkan sebagai batasan mutlak (limitasi) bagi
otonomi privat. Pengadilan wajib mengintervensi dan menolak yurisdiksi
arbitrase ketika mekanisme tersebut berpotensi menggerus kedaulatan negara dan
melegitimasi kerugian publik. Ini adalah demarkasi yurisdiksi yang tak dapat
ditawar demi supremasi keadilan sosial.
Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum dan
teori kritis, dominasi arbitrase dalam sengketa strategis merupakan manifestasi
berbahaya dari "privatisasi keadilan". Sistem ini mendestruksi sifat
publik dari hukum yang seharusnya transparan dan akuntabel di pengadilan negara,
menggantikannya dengan mekanisme tertutup yang elitis.
Dalam konteks sengketa yang melibatkan aset
negara dan hajat hidup orang banyak, kerahasiaan arbitrase menciptakan
"defisit demokrasi" yang akut. Keputusan vital yang berdampak
langsung pada beban publik, seperti kenaikan tarif listrik atau pembengkakan
utang negara, diambil oleh arbitrator swasta yang tidak memiliki legitimasi
demokratis, hampa dari kontrol sosial.
Kerahasiaan ini bukan sekadar fitur prosedural,
melainkan bentuk "kekerasan epistemik" yang merampas hak publik untuk
mengetahui. Ia berpotensi menjadi selimut impunitas yang menutupi jejak
korupsi, mark-up, dan inefisiensi proyek dari jangkauan penegak hukum
dan audit negara.
Lebih jauh, fenomena ini melahirkan fragmentasi
hukum atau apa yang disebut Gunther Teubner sebagai "Global Bukowina", di mana dispersi sengketa ke berbagai forum
menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi pihak bermodal kuat
untuk melakukan forum shopping.
Mengacu pada postulat Jurgen Habermas,
legitimasi hukum hanya dapat lahir dari diskursus rasional di ruang publik.
Privatisasi sengketa publik melalui arbitrase memutus rantai legitimasi ini dan
mengkomodifikasi hukum. Oleh karena itu, mengembalikan sengketa strategis ke pengadilan
nasional adalah imperatif sosiologis dan konstitusional untuk merebut kembali
ruang publik hukum. Pengadilan negara adalah satu-satunya forum yang menjamin
bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat secara transparan
oleh rakyat.
Analisis terhadap interaksi dialektis antara
doktrin Group of Companies, prinsip
separabilitas, dan isu fraud
menyingkap sebuah krisis kedaulatan yang akut dalam lanskap hukum Indonesia.
Hegemoni arbitrase transnasional, yang kerap
didewakan tanpa kritik sebagai "standar emas", sejatinya menyimpan
potensi destruktif yang serius terhadap tatanan hukum nasional. Oleh karena
itu, Pengadilan Indonesia harus segera mengakhiri era "kepatuhan
buta" terhadap konstruksi hukum asing dan menegakkan demarkasi yurisdiksi
yang bermartabat melalui tiga pilar aksiomatis.
Pertama, repudiasi doktrin group of companies. Doktrin ini
wajib ditolak secara tegas karena bertentangan secara fundamental dengan asas privity
of contract (personalitas) dalam KUH Perdata. Memaksakan yurisdiksi
arbitrase kepada pihak non-penandatangan hanya berdasarkan afiliasi korporasi
adalah bentuk "imperialisme yurisdiksi". Hal ini menciptakan
konsensus fiktif yang merampas hak konstitusional subjek hukum untuk memilih
forum peradilan secara sadar dan bebas, serta melanggar kedaulatan otonomi
entitas korporasi yang terpisah.
Kedua, supremasi fraus omnia corrumpit atas separabilitas.
Doktrin separabilitas tidak boleh menjadi safe haven bagi white
collar crime. Berdasarkan meta norma bahwa "kecurangan membatalkan
segalanya", apabila sebuah perjanjian lahir dari korup sistemik atau konspirasi
jahat, maka cacat tersebut merusak validitas klausula arbitrase di dalamnya.
Dalam kondisi ini, pengadilan negara wajib mengambil alih kompetensi.
Formalisme prosedural arbitrase tidak boleh dibiarkan mengalahkan keadilan
substantif atau melegitimasi hasil kejahatan.
Ketiga, status non-arbitrable bagi sengketa strategis.
Berdasarkan mandat ekonomi konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), sengketa yang
melibatkan Proyek Strategis Nasional dan aset vital yang menguasai hajat hidup
orang banyak adalah ranah ketertiban umum yang bersifat non-arbitrable. Penegakan
hukum publik yang memaksa (mandatory public law), seperti hukum
persaingan usaha dan pemberantasan korupsi, adalah domain eksklusif yurisdiksi
negara yang haram diprivatisasi ke dalam tribunal tertutup.
Pada akhirnya, reklaim yurisdiksi ini adalah
manifestasi mutlak kedaulatan negara. Hukum Indonesia tidak boleh sekadar
menjadi stempel legitimasi bagi kepentingan modal global, melainkan harus
kembali pada khittah-nya sebagai instrumen perlindungan rakyat yang mandiri.
Ini adalah seruan untuk membangun tatanan hukum yang berkeadilan, berwawasan
kebangsaan, dan berkonstitusi. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI