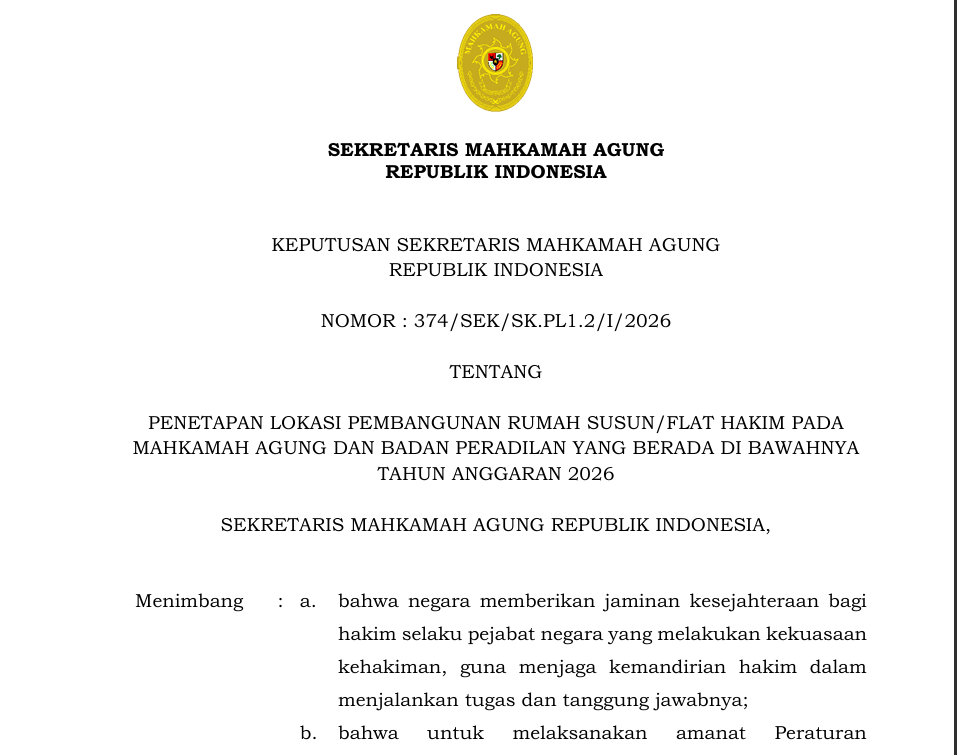Dalam sistem
peradilan pidana Indonesia, hakim menghadapi dilema yang kompleks antara
menghormati kewenangan penuntut umum sebagai dominus litis dan kewajiban mencari kebenaran materiil
secara objektif. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip kepastian hukum
dan keadilan substantif.
KUHAP mengatur ketentuan bahwa putusan hakim harus
didasarkan pada surat dakwaan dan fakta yang terbukti, namun dalam praktik,
fakta kerap menunjukkan adanya tindak pidana di luar dakwaan penuntut umum,
sehingga menimbulkan dilema apakah hakim harus menerapkan judicial restraint atau judicial
activism dalam mengadili dan menjatuhkan putusan.
Judicial restraint adalah pendekatan yudisial yang
menekankan pembatasan peran hakim dalam menginterpretasi hukum. Hakim yang
menganut prinsip ini berpegang pada interpretasi tekstual hukum, taat pada stare decisis, dan menghormati pemisahan
kekuasaan terhadap proses legislatif dan eksekutif yang mengeluarkan produk
peraturan perundangundangan.
Baca Juga: PN Sungai Penuh Vonis Penjara 13 Orang Perusak Kotak Suara
Sebaliknya, judicial
activism mengadopsi interpretasi hukum yang dinamis dan kontekstual,
memungkinkan hakim untuk berperan aktif memperbaiki ketidakadilan substantif
dan melindungi hak asasi manusia. Hakim yang ber-judicial activism memiliki keberanian untuk mengubah preseden
apabila diperlukan dan mencari kebenaran materiil secara menyeluruh selama
persidangan, walau dihadapkan pada risiko ketidakpastian hukum.
KUHAP Pasal 182 ayat (4) menegaskan putusan hakim harus didasarkan pada
surat dakwaan dan fakta yang terbukti, yang menjadi "kerangka normatif"
utama untuk judicial restraint.
Namun, Pasal 183 KUHAP yang mengatur pembuktian dengan minimal dua alat bukti memberi ruang bagi
hakim untuk secara aktif menilai akurasi bukti.
Pasal 191 KUHAP, yang mengatur bebasnya terdakwa jika
dakwaan tidak terbukti, mempertegas perlindungan terdakwa. Sementara Pasal 197
ayat (2) KUHAP menyatakan putusan di luar dakwaan adalah batal
demi hukum, membatasi ruang bagi hakim untuk aktif mengubah putusan yang tidak
berdasar pada dakwaan penuntut umum. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 memberi keleluasaan terkendali bagi hakim
untuk menjatuhkan putusan dengan pasal berbeda khususnya dalam perkara
narkotika, menggambarkan adanya pembukaan untuk judicial activism secara terbatas karena memiliki payung hukum.
Permasalahan kemudian muncul terhadap perkara-perkara yang dilimpahkan ke
pengadilan oleh kejaksaan, ternyata ketika diperiksa di persidangan ditemukan
fakta-fakta yang tidak dimuat dalam dakwaan penuntut umum. Penuntut Umum pasti
memiliki konsistensi untuk mempertahankan surat dakwaan beserta dengan
substansinya, akan tetapi keadaan berbanding terbalik, misalnya saksi-saksi
atau terdakwa yang membantah keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam
berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan.
Meskipun penulis tidak akan membahas lebih dalam mengenai mekanisme ketika
ada hal demikian terjadi dari sudut pandang saksi dan terdakwa. Namun yang
menjadi fokus penulis adalah bahwa situasi tersebut nyata terjadi dan bukan
skenario atau delusional penulis semata.
Praktik pengadilan menunjukkan beberapa dilema yang signifikan. Pertama,
ketika dakwaan penuntut umum tidak terbukti baik sebagian atau seluruhnya,
namun fakta persidangan menunjukkan perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan atau
tindak pidana lain yang tidak didakwakan, hakim menghadapi pilihan antara
membebaskan terdakwa demi kepastian hukum (restraint)
atau memutus berdasarkan fakta baru demi keadilan substantif (activism).
Kedua, adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tindak pidana yang
didakwakan dan yang terbukti, menantang hakim untuk mengambil keputusan yang
adil namun juga “legal”.
Ketiga, tekanan pada hakim agar
menghormati penuntut umum sekaligus mempertahankan independensinya.
Keempat, dalam kasus terdakwa tanpa pendampingan hukum yang optimal, hakim
perlu menentukan sampai sejauh mana perannya aktif memberikan akses keadilan
yang efektif tanpa melampaui batas secara normatif.
Konfrontasi sering terjadi antara penuntut umum dengan penasihat
hukum/Terdakwa atau saksi-saksi yang keterangannya tidak sesuai dengan
ekspektasi dari penuntut umum. Kita mengetahui betul bahwa tugas dan tanggung
jawab penuntut umum tentunya adalah membuktikan suatu peristiwa pidana terjadi
dan dilakukan oleh orang yang sedang duduk sebagai terdakwa di persidangan.
Situasi seperti ini tentu membuat hakim yang memeriksa perkara
bertanya-tanya, apakah terdakwa atau saksi-saksi yang tidak jujur, atau
penuntut umum yang tidak mau mengakui kelalaiannya dalam proses penuntutan dan
perumusan surat dakwaan.
Bahkan penulis ingin bertanya kepada para pembaca sekalian, sebagai hakim
sudah berapa kali dalam persidangan meminta penuntut umum untuk renvoi surat
dakwaan? Baik meliputi kesalahan penulisan (clerical error) atau sampai kesalahan yang fatal
berkaitan dengan syarat sahnya surat dakwaan.
Mengapa hakim cenderung memaafkan kelalaian penuntut umum terkait surat
dakwaan? Bukankan itu mendegradasi hak-hak terdakwa, mengingat KUHAP dilahirkan
dengan berasaskan pada perlindungan hak-hak terdakwa karena belum terbukti
melakukan tindak pidana, sebagaimana asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Pada akhirnya,
keadaan yang tidak ideal demikian menuntut hakim untuk bekerja lebih keras
dalam menggali dan mencari kebenaran. Mengesampingkan kelalaian dan kekurangan
pada dakwaan yang disusun penuntut umum tidak boleh sama sekali mengurangi
hak-hak yang dimiliki oleh Terdakwa maupun korban atau pihak lain yang
berkepentingan. Namun hal ini dapat menjadi diskursus lebih lanjut, sampai
kapan hakim harus selalu bersikap demikian? Hakim tetap harus menghormati
pemisahan kekuasaan, sehingga dalam melakukan judicial restraint atau judicial activism tetap dilakukan secara terbatas dan
bertanggung jawab, transparan, dan profesional. (ldr)
Referensi:
Richard A Posner, The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint, California Law Review
100.3, 2012.
Jerold Waltman, Principled Judicial Restraint: A Case against Activism. New York:
St. Martin’s Press, 2015.
Subhash Kumar, Judicial Activism vs. Judicial Restraint: Balancing the Role of the
Courts in a Democratic Society, Indian Journal of Law, Vol. 2, Issue 2,
Mar-Apr 2024.
Dominico Sony Nugraha dan Itok Dwi
Kurniawan, Pertimbangan Hakim Dalam
Memutus Tindak Pidana Narkotika Pada Dakwaan Alternatif Penuntut Umum,
Jurnal Verstek, Volume 12, Issue 2, 2024.
Raudah Muliana, Zulfan Zulfan, dan
Herinawati Herinawati, Tinjauan Yuridis
Putusan Hakim Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana
Narkotika (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt), Jurnal Ilmiah
Mahasiswa (JIM-FH), Volume VII, Nomor 2, April 2024.
Jihan Sukmawati Daratu dan Abdul Ficar
Hadjar, Putusan Tindak Pidana Narkotika
Yang Diputus Diluar Dari Dakwaan Penuntut Umum, Jurnal Reformasi Hukum
Trisakti, Vol. 6, No. 1, 2024.
Yunita Savira Budiarti, Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan
Diluar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K /Pid.Sus/2018), Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 3,
September-Desember 2021.
Ulfiyah Hasan dan Alfitra Alfitra, Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan
Kepastian Hukum; Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015,
Vol. 1, No. 3, 2019.
Baca Juga: 13 Terdakwa terkait Perusakan dan Pembakaran Kotak Suara di Sungai Penuh Jalani Sidang Perdana
Wienda Kresnantyo, Kewenangan Hakim Mengoreksi Dominus Litis Penuntut Umum,
https://dandapala.com/opini/detail/kewenangan-hakimmengoreksi-dominus-litis-penuntut-umum,
tanggal 29 Maret 2025, diakses tanggal 26 November 2025.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI