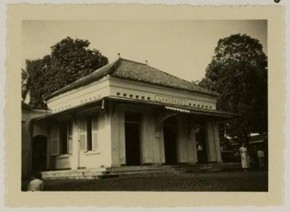Semenjak bertugas di Pengadilan Negeri Amlapura dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga bulan, Penulis kerap menjumpai perkara yang mengandung paradoks hukum dan budaya: pasangan yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu (pawiwahan) saat masih di bawah umur, kini datang sebagai orang dewasa, memohon “Penetapan Dispensasi Kawin”.
Padahal, mereka bukan hendak menikah, melainkan ingin memperoleh
legalitas negara atas ikatan yang sudah sah secara agama dan adat.
Permohonan ini menempatkan Hakim dalam suatu dilema: mengabulkan dispensasi kawin berarti menggunakan instrumen pencegahan perkawinan terhadap anak di bawah umur untuk memutihkan masa lalu, sementara menolak bisa merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Baca Juga: Fenomena Dispensasi Kawin Pasca Perkawinan Terlaksana Secara Adat dan Agama di Bali
Ironisnya, data perkara dari Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar adalah
penyumbang terbesar kedua perkara dispensasi kawin di Indonesia setelah Pengadilan
Tinggi Manado.
Ketidaksesuaian Konseptual
Dispensasi Kawin Pasca-Dewasa
Secara yuridis, dispensasi kawin adalah izin untuk menikah bagi mereka yang belum cukup umur. Ketika pasangan yang sudah dewasa mengajukan dispensasi kawin, instrumen ini kehilangan relevansi dan fungsi. Ia berubah menjadi alat pemutihan administratif, bukan pencegahan perkawinan anak. Hal ini mengikis marwah hukum dispensasi kawin dan menciptakan preseden yang membingungkan.
Terlebih lagi, permohonan semacam ini sering diajukan bukan oleh
orang tua dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, melainkan oleh pasangan itu
sendiri, yang secara hukum sudah cakap dan tidak lagi berada dalam pengampuan
orang tua. Bahkan jika orang tua yang mengajukan, permohonan tersebut tetap
tidak relevan karena subjek hukum yang dimohonkan sudah dewasa dan telah
menjalani kehidupan rumah tangga.
Permasalahan lain yang muncul adalah, sejauh yang Penulis ketahui, dalam pelaksanaannya, agama Hindu yang tumbuh dan hidup di Provinsi Bali tidak mengenal konsep “kawin ulang.” Pawiwahan adalah ritual sakral yang bersifat final dan mengikat seumur hidup.
Meminta pasangan untuk mengulang pawiwahan demi
administrasi negara akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian terhadap
kesakralan adat, menciptakan beban ekonomi, dan bertentangan dengan prinsip
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Tri Upasaksi: Pilar Filosofis Perkawinan
Hindu Bali
Sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam acara “Kopi Bali” yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025, Penulis berpendapat seorang Hakim yang menangani perkara serupa dapat mempertimbangkan konsepsi Tri Upasaksi dalam penetapannya.
Sederhananya, Tri Upasaksi merupakan tiga syarat yang menjadi penentu
sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Bali, yang terdiri dari Dewa
Saksi, Manusa Saksi, dan Bhuta Saksi. Apabila dijabarkan, maka
perwujudan tri Upasaksi tersebut adalah:
- Dewa Saksi (Tuhan/Agama): Perkawinan telah sah di
hadapan Sang Hyang Widhi Wasa melalui upacara yadnya.
- Manusa Saksi (Manusia/Adat): Perkawinan disaksikan
oleh sulinggih (pemuka agama), keluarga, dan banjar adat.
- Bhuta Saksi
(Alam/Lingkungan):
Pasangan telah hidup bersama, membangun rumah tangga, dan memiliki
keturunan.
Ketika ketiga hal
ini telah terpenuhi, maka secara substansi, ikatan perkawinan telah sah dan
sempurna menurut adat dan agama. Meskipun usia pasangan saat pawiwahan belum
memenuhi syarat administratif negara, kenyataan bahwa mereka kini telah dewasa
dan cakap hukum membuka ruang bagi negara untuk mengakui dan mencatat
perkawinan tersebut secara resmi, tanpa harus mengulang proses sakral yang
telah tuntas. Menurut Penulis, inilah titik temu antara kearifan lokal dan
sistem hukum nasional.
Pencatatan Perkawinan
Terlambat sebagai solusi yang kontekstual
Penulis berpandangan bahwa instrumen hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan perkara semacam ini adalah Pencatatan Perkawinan Terlambat, bukan Dispensasi Kawin.
Berkaitan dengan pencatatan perkawinan terlambat tersebut,
terdapat beberapa instrumen hukum yang mengakomodir, antara lain:
- Pasal 2 ayat (1) dan (2)
UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan.
- Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Perkawinan): Dispensasi hanya diberikan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum. (bertolak belakang dengan diberikannya dispensasi ketika sudah dewasa).
- Pasal 34, 35, dan 36 UU No. 23 Tahun 2006: Pencatatan perkawinan terlambat dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
Dengan mengalihkan permohonan dispensasi kawin ke
pencatatan terlambat, Hakim dapat menjaga fungsi asli dispensasi kawin sebagai
pencegah perkawinan anak. Dispensasi kawin tidak lagi menjadi instrumen
pemutihan, melainkan tetap fokus pada perlindungan anak sebelum usia dewasa.
Solusi ini juga memberikan
kepastian hukum bagi anak dalam hal administratif dan hak sipil lainnya. Semua
ini tercapai tanpa harus memaksa orang tua melakukan proses kawin ulang yang hampir
tidak dikenal dan tidak pernah terdengar dan tidak pernah diketahui sejauh ini
oleh Penulis dalam tradisi Hindu Bali.
Keadilan yang Berakar pada
Kearifan Lokal
Penulis percaya bahwa hukum tidak boleh berjalan sendiri,
melainkan harus beriringan dengan adat budaya yang tidak melanggar ketentuan. Konteksnya
dengan permasalahan dispensasi kawin dan pencatatan perkawinan terlambat
adalah, ketika Tri Upasaksi telah terpenuhi dan pasangan telah dewasa,
maka pencatatan perkawinan terlambat menjadi sebuah bentuk keadilan mampu menghormati
hukum nasional tanpa mengabaikan kearifan lokal. Dengan pendekatan ini, Hakim
tidak hanya meluruskan administrasi, tetapi juga menjaga martabat hukum dan
adat.
Baca Juga: Memaknai Status “Kawin Belum Tercatat” pada Dokumen Kependudukan
Bali bukan
sekadar daerah dengan banyak perkara Dispensasi Kawin; Bali adalah tempat di
mana hukum dan budaya saling bertemu, saling memengaruhi, dan mencari jalan
tengah yang adil. Dalam setiap perkara, Hakim dituntut untuk tidak hanya
menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai adat yang hidup di
masyarakat. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI