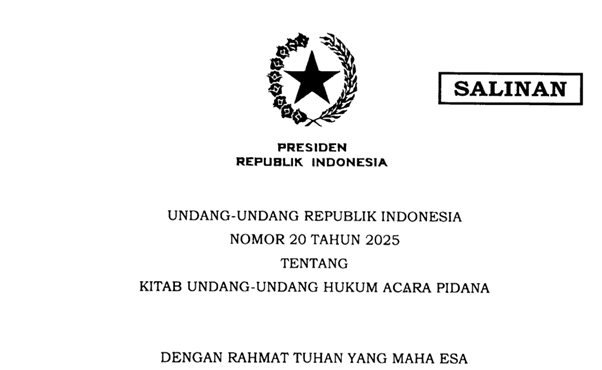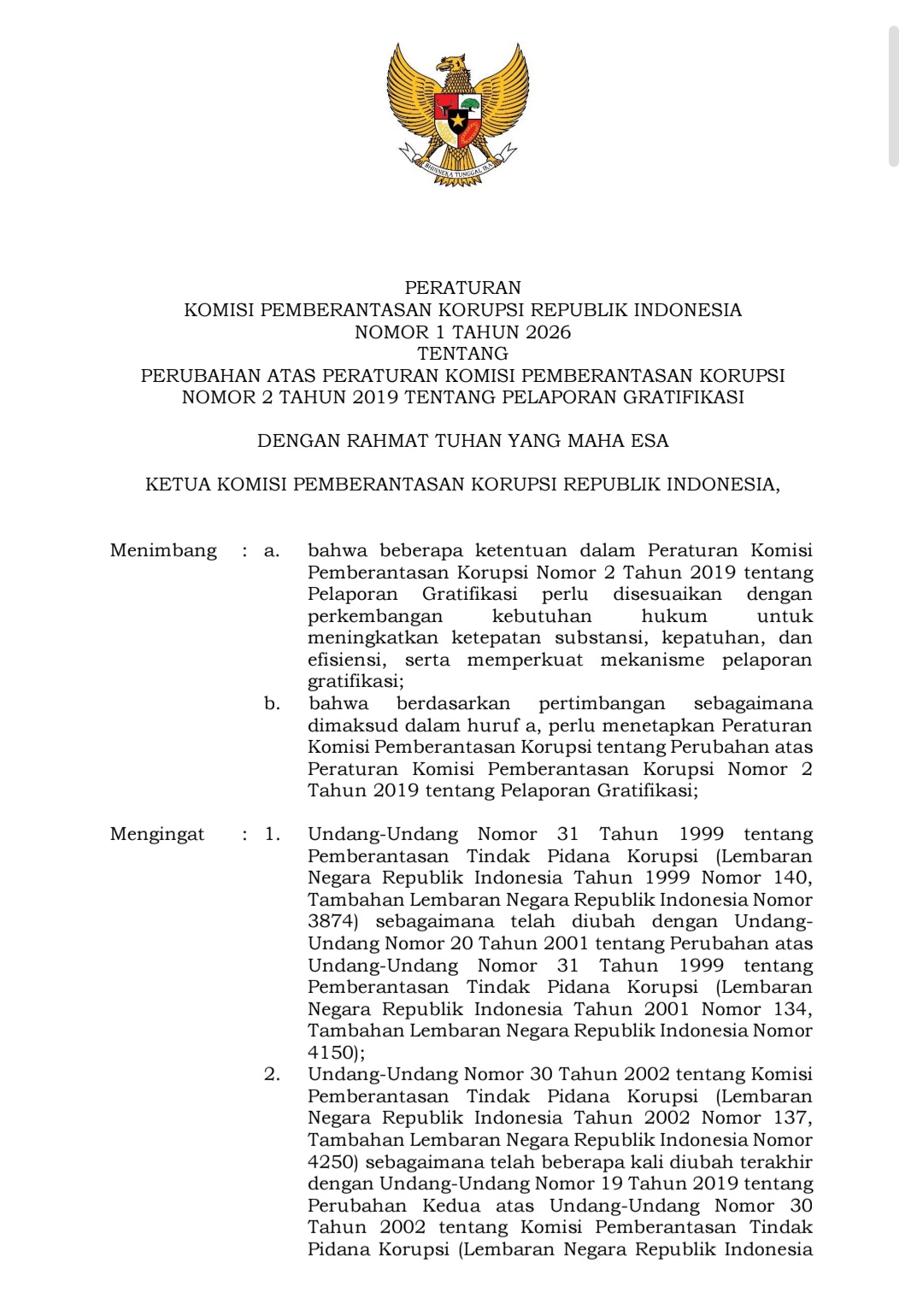Ketika aturan sudah menutup celah, mengapa
gratifikasi masih berulang? Setiap kali publik mendengar kabar hakim terseret
perkara gratifikasi, responsnya pasti akan selalu sama, marah, kecewa, lalu
bertanya mengapa ini berulang? Padahal, dari sisi tata kelola, perangkat
normatif untuk menjaga integritas peradilan semakin lengkap.
Standar etik, mekanisme pengawasan, sistem
pelaporan, hingga pembatasan interaksi dengan pihak berperkara terus
diperketat. Celah prosedural ditambal satu demi satu, namun kebocoran tetap
terjadi. Fenomena ini menegaskan satu hal yang kerap luput dalam diskursus
reformasi birokrasi, korupsi kecil yang disebut “tanda terima kasih” bukan
sekadar masalah aturan, melainkan masalah mentalitas dan kehendak
batin.
Di titik tertentu, persoalan gratifikasi tidak lagi
bertumpu pada lemahnya regulasi, tetapi pada rapuhnya kontrol diri ketika
kesempatan datang, dan ketika godaan bertemu pembenaran. “Aturan bisa menutup
celah, tapi hanya hati yang bisa menutup niat.”
Baca Juga: Melihat Alur Mudah Pelaporan Gratifikasi
Gratifikasi dalam konteks etik hakim adalah racun
yang paling berbahaya justru karena ia sering tampil tanpa wajah kriminal yang
kasar. Ia bisa hadir sebagai bingkisan, fasilitas, jamuan, bantuan “biaya”,
atau layanan yang dibungkus sopan santun. Di masyarakat, budaya balas budi
kerap dijadikan alasan: “sekadar penghormatan”, “tidak ada permintaan apa-apa”,
“cuma bentuk terima kasih”.
Namun dalam dunia peradilan, semua “hadiah” yang
beririsan dengan jabatan dan perkara tidak pernah benar-benar netral. Sekalipun
tidak mengubah putusan secara langsung, gratifikasi merusak dua hal sekaligus:
independensi hakim dan kepercayaan publik.
Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga
harus tampak ditegakkan. Sekali hakim menerima, yang rusak bukan hanya
satu perkara yang runtuh adalah wibawa lembaga. “Keadilan tidak selalu
runtuh karena putusan yang salah, sering kali ia runtuh karena hadiah yang
‘katanya’ kecil.”
Penulis memiliki pengalaman pernah mengikuti profil
assesment yang memang didesain untuk rekruitmen hakim tinggi badan pengawasan,
saat itu penulis diminta untuk membuat makalah untuk dipresentasikan.
Pertanyaannya saat itu adalah "sudah berulang
terjadi Hakim dan Aparatur Peradilan melakukan pelanggaran etik, apa langkah
saudara untuk membenahi hal ini agar tidak terulang lagi?" Saat itu penulis
berpendapat, sudah banyak sekali aturan / kebijakan yang dibuat oleh pimpinan
Mahkamah Agung untuk menutup pintu bahkan celah bagi terjadinya pelanggaran, namun
semua itu belum sepenuhnya berhasil.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembenahan internal
sudah bergerak ke arah compliance yang makin ketat. Secara umum,
arsitekturnya mencakup penguatan kode etik dan pedoman perilaku, pembatasan
relasi yang berpotensi konflik kepentingan, penegasan larangan menerima
hadiah/fasilitas, peningkatan fungsi pengawasan (internal maupun eksternal),
serta digitalisasi layanan untuk mengurangi kontak transaksional.
Di banyak satuan kerja, pesan pimpinan juga jelas,
integritas adalah “harga mati”, dan pelanggaran etik tidak boleh diperlakukan
sebagai kesalahan administratif yang bisa dimaafkan dengan mutasi. Kebijakan
internal yang menutup ruang kompromi terus didorong, termasuk pembinaan,
inspeksi, penguatan kontrol berjenjang, dan mendorong pelaporan bila ada
indikasi pelanggaran.
Masalahnya, pada level tertentu regulasi bekerja
efektif untuk mencegah pelanggaran yang bersumber dari ketidaktahuan atau
ketidakjelasan prosedur. Tetapi untuk pelanggaran yang bersumber dari
kesengajaan, aturan hanya berfungsi sebagai pagar. Pagar bisa dilompati oleh
orang yang sudah memutuskan untuk melompat.
Semakin tinggi pagar aturan, semakin jelas bahwa
pelanggaran terjadi bukan karena tidak tahu, melainkan karena tetap mau. Pola
berulang biasanya lahir dari kombinasi tiga hal:
1. Pertama, normalisasi. Ketika
lingkungan sosial (bahkan di luar pengadilan) menganggap pemberian sebagai hal
lumrah, hakim bisa mulai memandangnya sebagai “risiko kecil” yang bisa
dikelola.
2. Kedua, pembenaran psikologis. Di
sinilah bahasa menjadi alat paling licin: “sekadar menerima”, “bukan suap”,
“tidak mempengaruhi”, “ini budaya”, “saya juga punya kebutuhan”, “yang lain
juga begitu”. Pembenaran semacam ini bekerja seperti anestesi moral mengurangi
rasa bersalah, menurunkan kewaspadaan, dan memperbesar toleransi pada
pelanggaran berikutnya.
3. Ketiga, peluang. Peluang bukan hanya
soal sistem, tetapi soal momentum. Bahkan dengan sistem yang ketat, selalu ada
situasi perjumpaan, relasi, atau jejaring yang bisa menjadi kanal. Bila
integritas personal tidak kokoh, peluang sekecil apa pun menjadi pintu masuk.
Di titik ini, pendekatan pembenahan harus melampaui
prosedur. Yang dibutuhkan adalah pergeseran dari sekadar compliance-based
integrity menjadi character-based integrity.
Disini, penulis berpendapat perlunya pendekatan mental–spiritual,
Agama sebagai “Firewall” Batin. Pendekatan mental dari sisi agama bukan berarti
memindahkan urusan etik ke ranah simbolik atau seremonial. Justru sebaliknya,
agama memberi fondasi paling dalam self-governance, yakni pengawasan
diri ketika tidak ada kamera, tidak ada atasan, dan tidak ada laporan.
Dalam ajaran agama apapun, inti pesannya sama,
jabatan adalah amanah, harta yang tidak halal mengundang kehancuran, dan
keadilan adalah tanggung jawab moral yang dipertanggungjawabkan bukan hanya di
dunia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Jika nilai ini hidup, ia berfungsi sebagai
“firewall” batin yang tidak bisa digantikan oleh SOP.
Maka pembinaan integritas hakim perlu memperkuat
dimensi mental-spiritual secara sistematis: bukan sekadar ceramah, tetapi
internalisasi nilai, latihan refleksi etik, penguatan kepekaan hati nurani, dan
pembiasaan “menghitung konsekuensi” secara moral. Dalam konteks ini, agama
berperan sebagai perangkat pengendali diri paling efektif, karena ia berbicara
pada ruang terdalam yang tidak tersentuh audit. Karena pengawasan terbaik bukan
yang berdiri di luar diri, melainkan yang hidup di dalam diri.
Reformasi etik tidak bisa berdiri pada satu kaki.
Menutup celah eksternal tetap wajib memperkecil ruang pertemuan yang rawan,
membangun sistem transparansi, memastikan pelaporan berjalan, dan menjatuhkan
sanksi yang konsisten. Tetapi bersamaan dengan itu, benteng internal harus
dibangun karakter, rasa cukup (qana’ah), takut akan pertanggungjawaban
moral, dan kebanggaan menjaga marwah profesi.
Hakim bukan sekadar pejabat, ia personifikasi
negara ketika menjatuhkan putusan. Karena itu, pelanggaran etik oleh hakim
bukan hanya soal individu, tetapi soal legitimasi negara di mata warga. Pada
akhirnya, ketika aturan sudah banyak dan kebijakan pimpinan sudah berlapis,
pertanyaannya bergeser bukan lagi “apa aturan yang kurang?”, melainkan “apa
yang kurang di dalam diri kita, sehingga aturan tidak lagi menahan?”. Sistem
bisa mempersempit kesempatan, tetapi hanya iman dan karakter yang bisa
menghapus niat.
Hakim adalah primus inter pares yang pertama
di antara yang setara, bukan karena previllege, melainkan karena beban
keilmuan dan beban nurani yang melekat pada jabatannya. Pada dirinya tersemat
asas ius curia novit dirinya dianggap mengetahui hukum.
Konsekuensinya tegas, hakim tidak berhak belindung
di balik dalih “tidak tahu”, apalagi ketika norma etik dan larangan gratifikasi
telah ditulis terang, disosialisasikan berulang, dan diperkuat oleh kebijakan
kelembagaan.
Karena itu, ketika pelanggaran tetap terjadi,
publik wajar menolaknya sebagai sekadar kekhilafan. Ini bukan salah baca, bukan
kelalaian administratif, bukan “terpeleset” oleh situasi. Ini adalah keputusan,
sebuah kesengajaan untuk menyeberangi garis yang sudah jelas, mengabaikan pagar
yang sudah kokoh, dan pada akhirnya mengkhianati marwah luhur profesi. Pada
titik itu, pelanggaran etik bukan lagi sekadar pelanggaran aturan, melainkan
pembunuhan karakter terhadap amanah jabatan.
Lebih dari itu, pelanggaran seorang hakim tidak
pernah berhenti pada dirinya sendiri. Di ruang peradilan, integritas bekerja
seperti reputasi kolektif, ia dibangun bertahun-tahun, tetapi dapat runtuh oleh
satu tindakan.
Cukup satu yang menerima, maka ribuan lainnya
menanggung akibatnya. Kepercayaan publik terkikis, putusan-putusan yang lahir
dari hakim yang bersih ikut dicurigai, dan wibawa pengadilan tergerus di mata
pencari keadilan. Yang hancur bukan hanya nama individu, yang retak adalah
legitimasi lembaga.
Dalam lanskap seperti itu, urgensinya jelas,
disiplin etik tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas kepatuhan. Ia adalah
pondasi eksistensial peradilan. Hakim boleh berbeda pendapat dalam pertimbangan
hukum, tetapi tidak boleh berbeda komitmen dalam integritas. Sebab ketika
integritas dinegosiasikan, pengadilan tidak lagi berdiri sebagai rumah keadilan
ia berubah menjadi ruang transaksi.
Melalui tulisan ini, penulis ingin mengusulkan satu
penekanan yang selama ini kerap berada di pinggir agenda reformasi etik
pencegahan pelanggaran tidak cukup dibangun hanya dengan pagar aturan dan
ancaman sanksi, tetapi harus menyentuh wilayah yang paling menentukan yakni mentalitas
dan ketahanan batin.
Karena itu, pembinaan integritas hakim perlu
ditopang oleh pendekatan mental berbasis agama yang bersifat serius,
operasional, dan terukur, bukan seremonial, bukan sekadar formalitas, melainkan
proses internalisasi nilai amanah, rasa cukup, takut akan pertanggungjawaban
moral, serta disiplin menolak segala bentuk pemberian.
Agar efektif, pembinaan semacam ini semestinya
dilakukan berkala setidaknya setiap enam bulan sekali dengan desain kurikulum
yang konsisten, berjenjang, dan berbasis kasus nyata (case-based).
Enam bulan adalah ritme yang cukup dekat untuk
menjaga “kesadaran etik” tetap hidup, sekaligus cukup longgar untuk
memungkinkan evaluasi perubahan perilaku dan iklim integritas di satuan kerja.
Pembinaan berkala juga memberi pesan kelembagaan yang tegas, bahwa integritas
bukan program musiman, melainkan napas profesi.
Namun, penulis juga menegaskan pendekatan mental
bukan pengganti penindakan. Sanksi pidana dan sanksi etik tetap harus berjalan
cepat dan konsisten sebagai efek jera. Justru karena pelanggaran gratifikasi
sering terjadi dalam bentuk yang terselubung dan dirasionalisasi, pencegahan
dan penindakan harus berjalan sebagai dua kaki, pencegahan membangun benteng
dari dalam; penindakan menegakkan batas dari luar.
Dalam kerangka itu, penulis mendorong agar
pembinaan tidak dikerjakan sendirian oleh lembaga, melainkan menggandeng
kampus, universitas, akademisi, dan para guru besar lintas disiplin hukum,
etika, psikologi, kriminologi, teologi, hingga tata kelola publik.
Kolaborasi ini penting untuk dua hal, pertama,
memperkaya materi pembinaan dengan perspektif ilmiah dan praktik terbaik,
kedua, menciptakan “komunitas epistemik” yang membantu lembaga menjaga standar
etik secara berkelanjutan, tidak bergantung pada figur, tetapi pada sistem
pengetahuan dan budaya.
Lebih lanjut, penulis mengusulkan agar konsekuensi
atas gratifikasi tidak berhenti pada ranah pidana dan etik semata, melainkan
juga menyentuh dimensi reputasi akademik sebagai bentuk akuntabilitas moral
yang lebih luas.
Penulis mendorong gagasan agar hakim yang terbukti
melakukan gratifikasi didorong untuk kehilangan legitimasi simbolik yang selama
ini melekat pada gelar akademiknya, sehingga gelar itu tidak lagi dapat
digunakan sebagai “modal sosial” untuk memperoleh pekerjaan atau posisi di masa
depan.
Tentu, usulan ini harus ditempatkan secara
hati-hati, pencabutan gelar bukan perkara administratif sederhana dan harus
tunduk pada dasar hukum, kewenangan institusi pendidikan, serta mekanisme due
process yang adil dan akuntabel. Tetapi gagasan intinya jelas, ketika jabatan
kehakiman dikhianati melalui gratifikasi, yang dipertaruhkan bukan hanya
jabatan, melainkan kehormatan pengetahuan dan kredibilitas akademik itu
sendiri.
Pada akhirnya, penulis ingin menegaskan bahwa
pencegahan pelanggaran etik harus naik kelas, dari sekadar kepatuhan prosedural
menuju pembentukan karakter. Aturan sudah tegas. Kebijakan sudah berlapis. Maka
pekerjaan paling berat sekaligus paling menentukan adalah memastikan agar di
dalam diri hakim, ada pagar yang tidak bisa dilompati iman, rasa malu, dan
kesetiaan pada marwah profesi. Pembinaan mental berbasis agama yang berkala,
ditopang oleh komunitas akademik, dan diperkuat oleh konsekuensi sosial yang
nyata, adalah ikhtiar untuk membangun pagar itu dari dalam. (ldr)
Baca Juga: KPK Perbarui Aturan Pelaporan Gratifikasi, Nilai Batas Wajar Naik!
Referensi:
- Bazerman,
Max H., and Ann E. Tenbrunsel. Blind Spots: Why We Fail to Do What’s
Right and What to Do about It. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2011.
- Buscaglia,
Edgardo. An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary.
Washington, 1999.
- Transparency
International, Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial
Systems
- MA
RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010–2035.
- KEPPH
(SKB MA–KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009)
- KPK,
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI