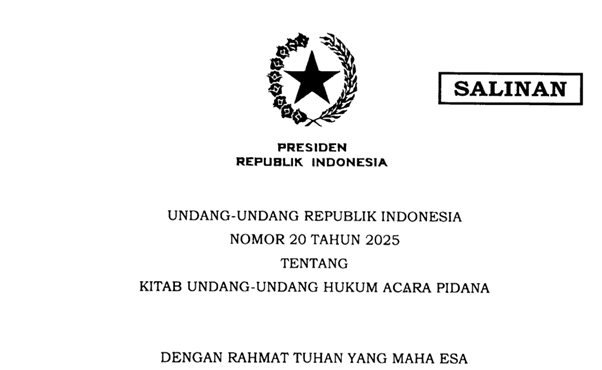UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa pesan yang
tegas, yakni negara boleh mencari kebenaran, tetapi cara mencarinya harus sah,
rasional, dan dapat diaudit. Dalam praktik sebelumnya, pelanggaran prosedur
sering dipahami sebagai kesalahan administrasi atau disiplin yang tidak
otomatis menggugurkan nilai pembuktian.
Hakim kerap menimbang
kebenaran materiil secara dominan, sementara isu legalitas perolehan bukti
berada di pinggir. KUHAP baru memindahkan keseimbangan itu, yakni kebenaran
tetap penting, tetapi kebenaran harus lahir dari proses yang tertib, bukan dari
rekayasa atau paksaan.
Perubahan paling tajam
tampak pada Pasal 235. Alat bukti tidak cukup sekadar “ada”, melainkan harus
memiliki legitimasi asal usul. Alat bukti wajib dapat dibuktikan autentikasinya
dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Hakim berwenang menilai autentikasi
serta sah atau tidaknya perolehan alat bukti, dan ketika hakim menyatakan bukti
tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, bukti tersebut tidak
dapat digunakan serta tidak memiliki kekuatan pembuktian. Rumusan ini penting
karena mengikat hakim dan sekaligus memaksa para pihak menguji asal usul bukti
secara terang.
Baca Juga: Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia
Kerangka tersebut
berkaitan erat dengan konsep “upaya paksa” yang didefinisikan luas, mencakup
penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, hingga larangan keluar wilayah
Indonesia.
Definisi luas ini
penting secara politik hukum karena pembentuk undang-undang mengakui bahwa
intervensi negara atas kebebasan, privasi, dan harta bukan perkara kecil. Konsekuensinya
sederhana, yakni setiap intervensi harus memiliki dasar hukum, alasan faktual,
dan batasan yang dapat dinilai oleh hakim.
Namun, definisi luas
tidak berarti perlakuan proseduralnya seragam. Penggeledahan dapat dijadikan
contoh. KUHAP baru memungkinkan penggeledahan terhadap rumah atau bangunan,
pakaian, badan, alat transportasi, bahkan informasi elektronik dan dokumen
elektronik.
Sebelum penggeledahan,
penyidik pada prinsipnya mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan
negeri, disertai uraian lokasi serta dasar atau fakta yang dipercaya tentang
adanya barang bukti terkait tindak pidana. Struktur ini menegaskan prinsip
“terukur”, yakni izin menentukan cakupan, dan cakupan membatasi cara kerja
penyidik agar tidak berubah menjadi penggeledahan “menjaring apa saja”.
Pengawasan yudisial
makin kuat melalui praperadilan. Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan
memutus sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Di tingkat definisi,
praperadilan dipahami sebagai kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus keberatan atas tindakan penyidik atau penuntut umum menurut cara yang
diatur undang-undang. Yang paling menentukan adalah konsekuensi pembuktiannya,
yakni bila putusan praperadilan menetapkan penggeledahan, penyitaan,
penyadapan, atau pemeriksaan surat tidak sah, maka barang bukti yang diperoleh
dari tindakan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Konsekuensi
ini memberi “gigi” pada kontrol prosedural, karena langsung menyentuh nyawa
perkara.
Pada titik tersebut,
gagasan exclusionary rule mendapatkan padanan operasional di Indonesia.
Tidak krusial apakah istilahnya dipakai atau tidak, yang menentukan adalah
fungsinya, yakni pengadilan menolak menjadi tempat pemutihan penyalahgunaan
wewenang. Norma eksklusi juga bekerja sebagai mekanisme pencegahan. Ketika
aparat memahami bahwa bukti ilegal akan nihil di persidangan, insentif untuk
mengambil jalan pintas melemah, sementara perencanaan penyidikan yang patuh
prosedur berubah menjadi kebutuhan strategis. Bahasanya sederhana, yakni
prosedur bukan hiasan, melainkan syarat sah pembuktian.
Tantangan terbesar
muncul ketika pembuktian masuk ke ranah elektronik. Bukti elektronik dikenal volatile,
tersembunyi, dan mudah dimanipulasi, proses perolehannya pun sering invasif,
dari penyadapan sampai forensik perangkat seluler dan akses data komputasi
awan. Dalam praktik, penyitaan perangkat sering diikuti penelusuran isi tanpa
batas yang jelas, padahal perangkat menyimpan lanskap kehidupan pribadi yang
luas dan tidak selalu relevan dengan perkara. Karena itu, kepatuhan prosedur
dan protokol forensik menjadi kunci autentikasi. Rantai penjagaan harus jelas,
yakni siapa mengakses, kapan mengakses, dan apa yang berubah harus dapat
ditelusuri.
Di atas persoalan teknis
itu terdapat persoalan kausalitas, yaitu bukti turunan. Penyidikan kerap
menemukan bukti A melalui tindakan awal yang keliru, lalu dari bukti A lahir
bukti B, C, dan seterusnya. Doktrin “buah dari pohon beracun” menyediakan lensa
analitis untuk menguji apakah bukti turunan masih tercemar oleh ilegalitas
awal. Perbaikan penting bagi argumentasi adalah ketepatan klaim, yakni doktrin
tersebut bukan norma eksplisit yang dirinci KUHAP, melainkan metode penalaran
untuk menilai akibat pelanggaran, dengan Pasal 235 sebagai dasar normatifnya.
Dengan demikian, dialektika kausalitas memberi cara kerja untuk menerapkan
dasar itu secara adil.
Agar penilaian
kausalitas tidak berubah menjadi spekulasi, hakim perlu memaksa pembuktian
proses, bukan hanya hasil. Penuntut umum seharusnya memaparkan kronologi
penyidikan secara runtut, kapan tindakan dilakukan, siapa yang memberi
perintah, bukti permulaan apa yang sudah ada, langkah apa yang mengantar pada
bukti berikutnya, serta dokumen apa yang menunjukkan kepatuhan prosedur. Berita
acara, izin pengadilan, dan dokumentasi teknis forensik harus diperlakukan
sebagai bagian dari pembuktian legalitas. Tanpa itu, diskursus autentikasi
tidak berubah menjadi mantra teknis yang menutupi pelanggaran hak.
Di sisi manajemen
perkara, KUHAP baru mendorong kebiasaan baru di ruang sidang. Sengketa dapat
tidaknya alat bukti digunakan sebaiknya dikelola sejak awal, terutama terhadap
bukti yang menjadi tulang punggung dakwaan. Hakim dapat mengagendakan
pemeriksaan pendahuluan mengenai legalitas perolehan bukti krusial, sehingga
risiko sidang panjang yang runtuh di akhir dapat diminimalkan.
Pada bukti elektronik,
standar minimal yang patut diuji meliputi cakupan izin, relevansi tindakan
terhadap objek yang dicari, integritas media sitaan, metode imaging,
serta konsistensi rantai penjagaan. Pola ini membuat para pihak lebih fair,
yakni terdakwa mengetahui sejak dini bukti apa yang dapat dipakai, sedangkan
penuntut umum dapat mengoreksi kelemahan sebelum berlarut.
Ada satu konsekuensi
praktis yang sering terlewat, yaitu sengketa legalitas menuntut pembalikan fokus
pembuktian. Ketika terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan yang
beralasan, penuntut umum semestinya mampu menunjukkan dasar tindakan aparat,
termasuk surat perintah, izin pengadilan, dan catatan pelaksanaan. Ini sejalan
dengan gagasan pengawasan yudisial atas tindakan yang invasif, yang diposisikan
sebagai mekanisme checks and balances dalam konstruksi KUHAP baru.
Tanpa itu, proses mudah
dituding sewenang-wenang dan bukti diragukan serius. Dengan standar itu,
pemeriksaan tidak terjebak formalitas. Pemeriksaan memastikan bukti yang masuk
benar-benar bersih. Pada akhirnya, kepastian prosedur melindungi semua pihak,
termasuk korban, karena perkara tidak kandas di tingkat pembuktian.
Faktor penentu akhirnya
adalah konsistensi yudisial. Ada risiko standar ganda, yakni ketat pada perkara
ringan, namun permisif pada perkara yang dianggap besar dengan dalih
kepentingan umum atau keamanan. Jika inkonsistensi terjadi, fungsi pencegahan
eksklusi bukti akan tumpul dan aparat belajar bahwa pelanggaran prosedur dapat
dimaafkan untuk kasus tertentu.
Karena itu, keberanian
hakim menjadi kunci, yakni berani mengesampingkan bukti yang tidak sah, meski
putusannya tidak populer, demi menjaga martabat hukum acara sebagai pagar
pembatas kekuasaan.
Baca Juga: Kemana Perginya Keyakinan Hakim dalam KUHAP Baru?
Dengan demikian, KUHAP
2025 dapat dibaca sebagai arsitektur etika pembuktian. Pasal 235 memaksa
autentikasi dan legalitas. Konsep upaya paksa menandai batas intervensi negara.
Praperadilan memberi kontrol yang berdampak langsung pada kegunaan barang
bukti, dan analisis bukti turunan memperhalus cara hakim menilai akibat
pelanggaran prosedur. Di era digital, tuntutan literasi teknis meningkat,
tetapi arah dasarnya tetap sama, yakni kebenaran yang dicapai dengan cara
melawan hukum bukan kemenangan negara hukum, melainkan kegagalannya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI