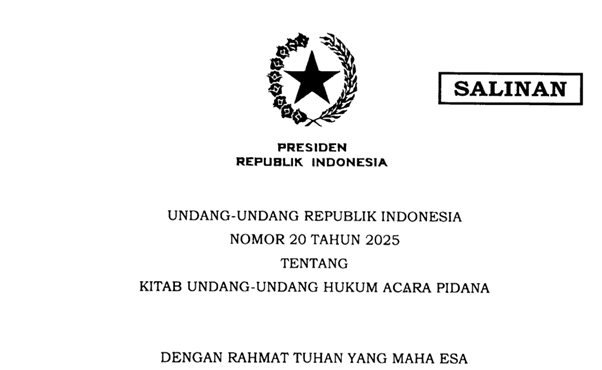Praperadilan
dalam KUHAP 2025 tampil sebagai mekanisme kontrol yudisial yang lebih tajam. Tidak
lagi semata menguji tindakan paksa yang bersifat "aktif", melainkan
mulai menyentuh kelalaian prosedural dan pengabaian kebutuhan kesehatan
tahanan. Pada titik ini lahir dilema keadilan prosedural, yakni ketika UU
membuka pintu perlindungan baru, segera muncul pertanyaan tentang siapa yang
berhak memakainya, bagaimana prosedurnya, dan apakah tersedia koreksi vertikal
melalui banding.
Fondasi pertama harus diletakkan pada pengakuan objek. KUHAP 2025 memasukkan "penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah" dan "penangguhan pembantaran penahanan" sebagai objek praperadilan.
Secara konseptual, ini menggeser fokus perlindungan dari unlawful acts menuju unlawful omission. Negara tidak hanya diminta menahan diri dari penangkapan atau penahanan yang cacat hukum, tetapi juga dituntut bertindak wajar agar seseorang tidak disandera oleh status hukum yang menggantung.
Baca Juga: Pembantaran (Stuiting): Permasalahan dan Solusi Praktis
Fenomena tersangka yang
bertahun-tahun "digantung" tanpa SP3 tetapi juga tanpa pelimpahan,
kini diposisikan sebagai problem legal yang dapat diuji cepat di hadapan hakim.
Demikian pula, keputusan menunda pembantaran bukan lagi diskresi mutlak,
melainkan tindakan yang dapat diuji karena menyentuh hak atas kesehatan
tahanan.
Namun problem sistematika segera muncul. Pasal 160 – 162, yang memetakan jenis permohonan praperadilan dan memberi petunjuk tentang legal standing, tidak menyebut secara eksplisit bagaimana permohonan untuk 2 objek baru itu diajukan, dan siapa yang berhak mengajukannya.
Kekosongan penyebutan ini
memancing 2 tafsir. Pertama menyatakan objek tersebut menjadi tidak operasional
karena tidak memiliki pasal teknis. Kedua mendorong argumentum a contrario,
yaitu karena Pasal 160 – 162 tidak mencantumkan e dan f, maka larangan banding
dalam Pasal 164 yang merujuk Pasal 160 sampai 162 dianggap tidak berlaku,
sehingga putusan praperadilan e dan f dapat dibanding.
Di sini analisis harus disiplin. Kewenangan praperadilan atas objek e dan f lahir dari Pasal 158 sebagai norma kompetensi, bukan dari Pasal 160 sampai 162. Artinya, ketiadaan aturan teknis tidak boleh dipakai untuk menutup akses, sebab menutup akses akan mengingkari norma kompetensi yang sudah tegas.
Dalam hukum acara, kekosongan prosedural lazim diisi lewat penafsiran sistematis dan analogi terbatas, yaitu prosedur yang sudah ada diterapkan sepanjang selaras dengan sifat objek dan tidak bertentangan dengan asas dasar. Secara natur hukum, penundaan perkara tanpa alasan sah dan penangguhan pembantaran bersinggungan langsung dengan kepentingan Tersangka, maka, secara mutatis mutandis, legal standing yang paling rasional mengikuti pola permohonan yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya. Dengan demikian, kebisuan pembentuk undang-undang dipahami sebagai kekosongan teknis yang diisi demi efektivitas hak.
Tetapi, kesimpulan "dapat mengajukan praperadilan" tidak otomatis berarti "dapat mengajukan banding". Justru pada titik upaya hukum, KUHAP 2025 menegakkan pagar legalitas prosedural yang paling keras, yaitu acara pidana dilaksanakan hanya menurut tata cara yang diatur undang-undang.
Konsekuensinya, upaya hukum
bukan ruang kreativitas interpretatif, melainkan kewenangan yang diciptakan
secara limitatif. Hal tersebut dipahami sebagai "hak Terdakwa atau
Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan", sehingga harus
berada dalam koridor yang ditentukan undang-undang. Dalam hukum publik, asas
yang bekerja bukan “semua boleh kecuali dilarang”, melainkan “hanya boleh
sejauh diberi kewenangan”. Karena itu, pertanyaan "karena tidak dilarang
maka boleh banding" harus dijawab dengan logika yang terbalik, yakni yang
boleh adalah yang diberi, sedangkan yang tidak diberi tidak dapat diciptakan
dengan penafsiran.
Isu banding harus ditarik kembali ke norma finalitas praperadilan, yakni Pasal 164. Pasal ini menyatakan bahwa putusan praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 – 162 tidak dapat dimintakan banding, lalu membuka 1 pintu saja, yaitu jika putusan praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta putusan akhir ke pengadilan tinggi.
Secara kebijakan, konstruksi ini menunjukkan bahwa
pembentuk undang-undang menginginkan praperadilan tetap menjadi forum cepat,
dengan finalitas sebagai harga bagi kecepatan, kecuali pada satu situasi yang
dipandang sangat krusial karena menyangkut "hidup-matinya" perkara
pidana.
Di sini, argumentum a contrario yang mencoba membuka banding untuk objek e dan f menjadi rapuh. Jika pembentuk UU memang bermaksud membuka banding bagi penundaan perkara atau pembantaran, logika pembatasan menuntut agar kedua objek itu dicantumkan secara eksplisit sebagai pengecualian, sebagaimana pengecualian untuk penghentian penyidikan atau penuntutan.
Fakta bahwa pengecualian hanya
diberikan pada 1 jenis putusan menunjukkan ratio legis yang sempit,
yaitu hanya sengketa yang memaksa perkara yang dihentikan untuk "dihidupkan
kembali" yang diberi kanal koreksi vertikal, karena konsekuensinya
menyentuh kepentingan publik dan korban secara langsung. Untuk objek lain,
termasuk e dan f, pembentuk UU memilih finalitas demi kepastian dan efisiensi.
Argumen teleologis memperkuat penutupan pintu banding. Objek huruf e adalah sengketa atas penundaan, membuka banding atas putusannya berpotensi melahirkan penundaan baru yang dilembagakan oleh proses upaya hukum, sehingga remedy memakan dirinya sendiri.
Proses yang dimaksudkan memutus penundaan berlarut akan berubah menjadi proses berlapis yang menambah delay, padahal esensi objek ini adalah memulihkan kepastian hukum secepat mungkin. Objek huruf f bahkan lebih sensitif, yang mana masalah kesehatan tahanan menjadikan waktu sebagai variabel "hidup-mati", bukan sekadar administrasi.
Apabila
banding dibuka tanpa desain tenggat ekstra cepat dan tanpa kejelasan mengenai
daya eksekusi putusan pada masa banding, maka perlindungan kesehatan dapat
berubah menjadi prosedur yang membiarkan kerusakan kesehatan terus berjalan
sambil menunggu putusan tingkat atas.
Hakim tunggal praperadilan memegang kekuasaan besar, dan kekeliruan penilaian dapat mengunci nasib tersangka, terutama pada pembantaran yang mensyaratkan penilaian medis. Namun KUHAP 2025 memilih mengelola risiko itu bukan melalui banding, melainkan melalui desain acara yang cepat dan akuntabel, yaitu hakim menetapkan hari sidang dalam waktu singkat, pemeriksaan dilakukan cepat dan putusan wajib dijatuhkan dalam tenggat, serta putusan harus memuat dasar dan alasan secara jelas.
Di samping itu, jika upaya paksa dinyatakan tidak sah, pemulihan harus
dilakukan dalam waktu singkat setelah putusan. Desain ini menuntut kualitas
argumentasi dan pembuktian di tingkat pertama, karena koreksi vertikal ditutup,
koreksi horizontal harus hadir melalui transparansi pertimbangan, kontrol etik,
dan pengawasan kelembagaan.
Di ranah strategi, jalan keluar yang realistis bukanlah memproduksi banding melalui tafsir, melainkan memanfaatkan kanal yang tersedia. Untuk pembantaran, permohonan harus bertumpu pada keterangan dokter yang relevan, risiko klinis yang terukur, dan rencana pengawasan yang meminimalkan kekhawatiran pelarian, sehingga hakim memiliki dasar objektif untuk menilai proporsionalitas.
Bila permohonan ditolak, keadaan kesehatan yang dinamis dapat melahirkan fakta baru yang substantif. Permohonan berikutnya, sepanjang berbasis keadaan baru, lebih tepat dipahami sebagai respons atas perubahan keadaan, bukan pengulangan formal.
Untuk penundaan perkara, fokus argumentasi harus memaku parameter "tanpa
alasan yang sah" dengan menunjukkan langkah penyidik yang stagnan,
absennya tindakan penyidikan yang wajar, atau alasan penundaan yang tidak
proporsional terhadap kompleksitas perkara. Selain itu, KUHAP 2025 juga
mengakui kemungkinan pemeriksaan praperadilan kembali pada tahap berbeda dengan
permintaan baru, yang menunjukkan bahwa sistem menyediakan koreksi berbasis
keadaan dan tahap, bukan koreksi vertikal melalui banding.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praperadilan atas objek Pasal 158 huruf e dan f tetap dapat diajukan. Kebisuan Pasal 160 sampai 162 adalah kekosongan teknis yang harus diisi melalui penafsiran sistematis agar perlindungan tidak menjadi slogan kosong. Banding atas putusan praperadilan untuk objek e dan f tidak dapat dibenarkan hanya karena tidak disebut. Upaya hukum bersifat limitatif dan KUHAP 2025 menutup banding kecuali pada pengecualian tunggal yang dinyatakan secara eksplisit. Dalam kerangka itu, adagium "tidak dilarang berarti boleh" tidak cocok untuk rezim upaya hukum. Yang menentukan bukan ketiadaan larangan, melainkan keberadaan pemberian kewenangan. (gp/ldr)
Baca Juga: Tranformasi Praperadilan dalam KUHAP
Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan/pendapat lembaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI