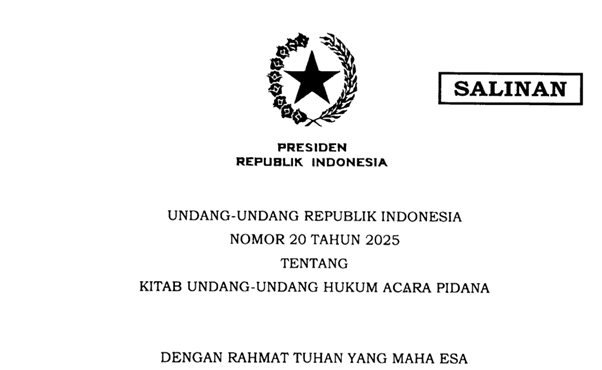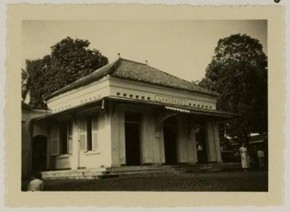Kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama
negara hukum yang demokratis. Konstitusi Indonesia secara tegas menjaminnya
melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Namun, jaminan konstitusional tersebut tidak berdiri
sendiri. Dalam praktik penegakan hukum pidana terutama pasca berlakunya Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, kebebasan berekspresi kerap
beririsan dengan kepentingan lain yang juga dilindungi hukum, seperti perlindungan
reputasi, ketertiban umum, dan keamanan negara. Di titik inilah peran hakim
menjadi sangat krusial.
Hakim tidak sekadar berfungsi sebagai “corong undang-undang”.
Dalam perkara yang berdimensi kebebasan berekspresi, hakim dituntut untuk
melakukan pembacaan hukum secara kontekstual, bukan semata-mata tekstual.
Artinya, hakim tidak cukup hanya berhenti pada rumusan pasal pidana atau pada
konten ekspresi, misalnya cuitan di media sosial (instagram, tiktok, facebook
dan lainnya) tetapi harus menggali konteks, tujuan, serta dampak nyata dari
ekspresi tersebut terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.
KUHP Nasional membawa semangat pembaruan hukum pidana yang
menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu pijakan penting. Berbagai
ketentuan terkait penghinaan, ujaran kebencian, maupun kejahatan terhadap
ketertiban umum dan keamanan negara dirumuskan dengan tujuan memberikan
kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan pemidanaan terhadap ekspresi
yang sah.
Baca Juga: Keseimbangan Perlindungan Nama Baik & Kebebasan Berekspresi dalam KUHP Baru
Namun, keberadaan norma pidana tersebut tidak otomatis
melegitimasi setiap pembatasan kebebasan berekspresi. Prinsip umum dalam hukum dan
HAM yang juga diakui dalam praktik peradilan menegaskan bahwa pembatasan
ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat yang ketat diatur oleh
undang-undang, bertujuan melindungi kepentingan yang sah, dan benar-benar
diperlukan serta proporsional dalam masyarakat demokratis.
Dalam konteks ini, hakim memegang peranan sentral sebagai
penjaga keseimbangan (balancing rights). Hakim harus mampu menilai apakah suatu
ekspresi benar-benar menimbulkan bahaya nyata (real and tangible harm), ataukah
sekadar kritik, opini, bahkan ekspresi keras yang masih berada dalam koridor
kebebasan berekspresi.
Perkembangan teknologi informasi membuat ekspresi di ruang
digital khususnya media sosial menjadi perhatian utama penegak hukum. Banyak
perkara pidana bermula dari unggahan singkat, komentar, atau cuitan. Namun,
pendekatan hukum yang hanya berfokus pada teks unggahan tanpa menilai konteks
sosial, politik, dan dampaknya berpotensi menjerumuskan penegakan hukum ke arah
represif dan otoriter.
Di sinilah hakim dituntut untuk melampaui pembacaan literal.
Apakah sebuah pernyataan dimaksudkan sebagai kritik kebijakan publik? Apakah ia
merupakan opini atau analisis berbasis kepentingan publik? Apakah pernyataan
tersebut benar-benar mendorong kekerasan, kebencian, atau gangguan nyata
terhadap ketertiban umum? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi
inti pertimbangan hakim.
Tanpa pengukuran dampak yang jelas dan rasional, pemidanaan
terhadap ekspresi berisiko mengikis ruang demokrasi. Indonesia adalah negara
hukum yang demokratis, bukan negara hukum otoriter. Dalam negara demokratis,
ekspresi yang tajam, keras, bahkan tidak menyenangkan terhadap kekuasaan tetap
harus dilindungi sepanjang tidak melanggar batasan yang sah.
Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam perkara yang
melibatkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Keduanya didakwa terkait
ekspresi kritik yang disampaikan dalam konteks advokasi dan kepentingan publik.
Dalam putusan pengadilan, majelis hakim tidak semata-mata menilai isi
pernyataan secara terpisah, melainkan membaca keseluruhan konteks: tujuan
penyampaian, posisi para pihak, serta relevansi ekspresi tersebut dengan
kepentingan publik.
Putusan yang membebaskan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar
kerap dipandang sebagai best practices
dalam mengadili perkara kebebasan berekspresi. Hakim dalam perkara tersebut
menunjukkan keberanian dan ketajaman analisis dengan menempatkan kebebasan
berekspresi sebagai hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi secara sangat
terbatas. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat publik dipahami
sebagai bagian esensial dari demokrasi, bukan sebagai serangan pidana yang
harus segera dibungkam.
Lebih dari itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum
pidana tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan dari
kritik. Pemidanaan terhadap ekspresi harus menjadi ultimum remedium, bukan
instrumen pertama yang digunakan negara.
Dalam perspektif KUHP Nasional, peran hakim menjadi semakin
strategis. Hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjaga
agar hukum pidana tidak menyimpang dari nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dengan
pendekatan kontekstual, hakim dapat memastikan bahwa batasan kebebasan berekspresi
diterapkan secara proporsional dan adil.
Pendekatan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kebebasan
berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun, batasan tersebut harus
jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa itu, pembatasan
hanya akan menjadi dalih untuk membungkam perbedaan pendapat.
Baca Juga: Delik Penghinaan Presiden, Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial
Memahami kebebasan berekspresi dalam mengadili perkara pidana
bukanlah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional bagi hakim. KUHP Nasional
memberikan kerangka normatif, tetapi kunci utamanya tetap terletak pada
keberanian dan kecermatan hakim dalam menafsirkan hukum secara kontekstual.
Dengan meneladani praktik baik seperti dalam perkara Fatia Maulidiyanti dan
Haris Azhar, peradilan pidana Indonesia dapat terus bergerak menuju wajah hukum
yang adil, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. (rw/snr/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI