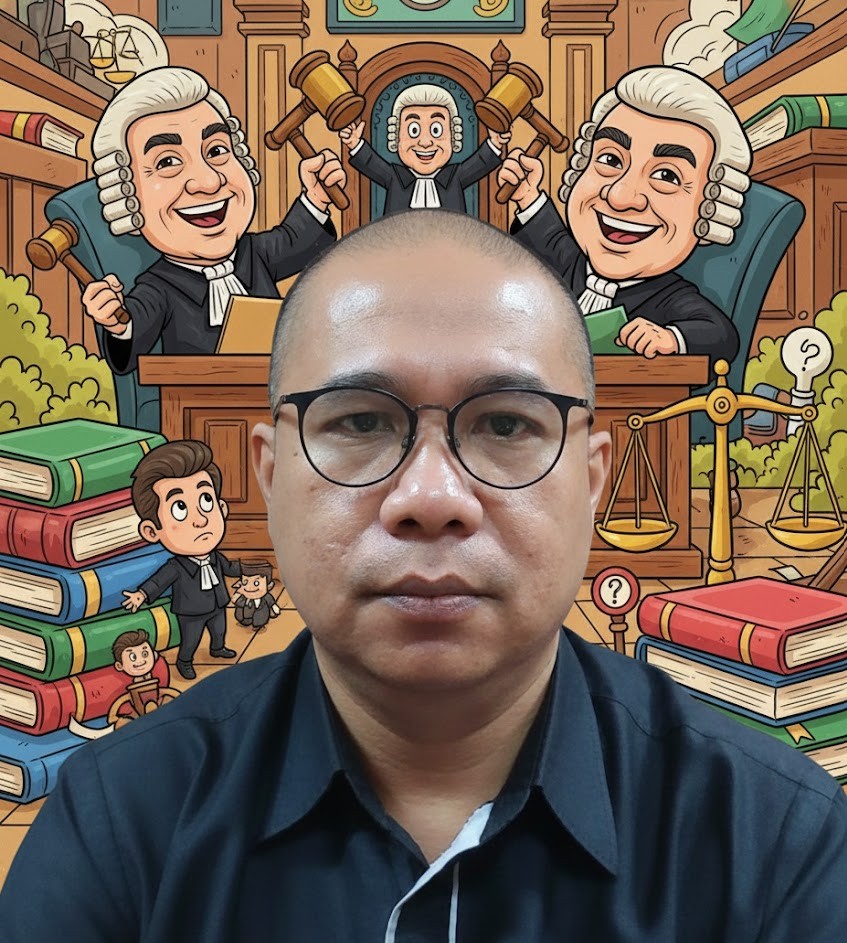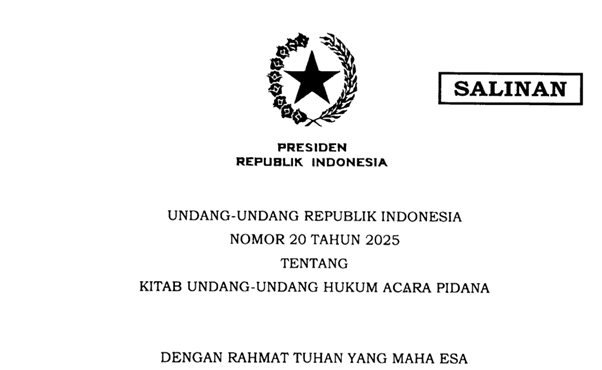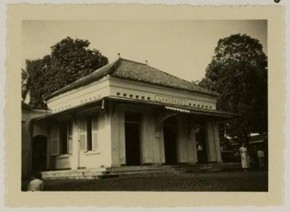Dalam dua seri sebelumnya, telah dibedah perbedaan filosofis pengakuan dan tata laksana operasional persidangan antara Pasal 78, Pasal 204 - 205, dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Baca Juga: Part 2. Plea Bergain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian
Kini, pembahasan
diarahkan pada titik hilir, yakni konsekuensi pemidanaan. Bagi terdakwa, jalur
prosedural pada akhirnya bermuara pada pertanyaan: pidana seperti apa yang
mungkin dijatuhkan, dan faktor prosedural apa yang secara normatif dapat
memengaruhi ruang gerak hakim.
UU
20/2025 tidak hanya membenahi “cara” mengadili, melainkan juga menyusun
struktur insentif yang memengaruhi prediktabilitas dan batas pidana dalam
situasi tertentu. Dengan kata lain, pemidanaan tidak lagi semata ditautkan pada
berat ringannya perbuatan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana perkara
diproses, sepanjang syarat-syarat yuridisnya dipenuhi.
Isu hukum
yang mengemuka ialah justifikasi normatif atas gradasi pemidanaan di antara 3 rezim
pengakuan tersebut. Pertanyaannya bukan semata mengapa 2 pelaku tindak pidana
serupa dapat berujung pada lama pidana yang berbeda, melainkan apakah perbedaan
itu dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan rasional.
Dalam
perspektif due process, terdakwa tetap memiliki hak menyangkal dan
menuntut pembuktian penuh. Namun, dalam perspektif kebijakan kriminal, negara
juga berwenang menyusun insentif agar perkara yang memenuhi kualifikasi
tertentu dapat diselesaikan lebih efisien tanpa menanggalkan perlindungan
hak-hak dasar. Tantangannya adalah menempatkan “insentif” sebagai instrumen
rasionalisasi penegakan hukum, bukan sebagai substitusi terhadap pembuktian
atau sebagai penentu tunggal pemidanaan.
Pertama, Pasal
78 menempatkan “Pengakuan Bersalah (plea bargain)” sebagai mekanisme
yang secara konseptual dikaitkan dengan imbalan keringanan hukuman. Secara
normatif, ruang lingkupnya dibatasi: hanya untuk pelaku yang baru pertama kali
melakukan tindak pidana; untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, dan/atau
bagi yang bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Pembatasan ini memperlihatkan
bahwa insentif pemidanaan pada Pasal 78 tidak dimaksudkan bersifat universal,
melainkan selektif, terutama untuk perkara yang relatif lebih ringan atau
memiliki dimensi pemulihan yang dapat segera ditunaikan oleh pelaku.
Logika
pemidanaan pada Pasal 78 bersifat konsensual terkendali. Jika pengakuan
bersalah disepakati, dibuat perjanjian tertulis antara Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan persetujuan hakim. Perjanjian tersebut memuat elemen minimum,
termasuk terdakwa mengetahui konsekuensi pengakuan berupa pengabaian hak diam
dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa, pengakuan dilakukan
secara sukarela, pasal yang didakwa dan ancaman yang akan dituntut sebelum
pengakuan dilakukan, serta hasil perundingan, termasuk alasan pengurangan masa hukuman.
Dengan
konstruksi demikian, “keringanan” bukanlah asumsi, melainkan bagian dari desain
yang wajib diargumentasikan dan didokumentasikan, sehingga dapat diuji secara
profesional, baik dari sisi kewajaran maupun kepatuhan terhadap batas-batas
normatif.
Kontrol
hakim menjadi kunci agar insentif tidak menggerus prinsip pembuktian. UU
20/2025 mewajibkan hakim menilai pengakuan dilakukan secara sukarela, tanpa
paksaan, dan dengan pemahaman penuh. Lebih jauh, putusan sesuai kesepakatan
baru dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa pengakuan
dilakukan sesuai ketentuan Pasal 78 dan didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
Dengan demikian, insentif pemidanaan pada Pasal 78 bekerja di dalam pagar ganda,
yakni pagar integritas proses (voluntariness dan informed consent)
serta pagar kecukupan bukti minimum. 2 pagar ini penting untuk mencegah
mekanisme pengakuan berubah menjadi pemidanaan yang semata bertumpu pada
pernyataan terdakwa, atau pada dinamika perundingan yang tidak transparan.
Kedua,
Pasal 204 - 205 membangun insentif pemidanaan melalui jalur khusus di ruang
sidang, yakni pengakuan terhadap dakwaan pada momen awal ajudikasi. Dalam
desain ini, insentif bukan berupa kesepakatan angka pidana, melainkan berupa
pemangkasan tahapan pembuktian setelah hakim memverifikasi kualitas pengakuan.
Pasal 205 secara eksplisit mengharuskan hakim memeriksa pengakuan terdakwa
dengan mempertimbangkan indikator proses sebelumnya, antara lain terdakwa telah
diperiksa pada tahap penyidikan, didampingi advokat selama pemeriksaan, pemeriksaan
dilakukan dengan cara dan waktu yang patut, terdakwa telah diberitahu dan dapat
menggunakan haknya, serta tidak ada tekanan, paksaan, atau penyiksaan dalam
memperoleh pengakuan tersebut. Ini menegaskan bahwa jalur khusus bukan “jalur
cepat” yang mengorbankan hak, melainkan jalur yang mensyaratkan kualitas
proses.
Dalam
konteks penjatuhan pidana, jalur Pasal 204 - 205 berkorelasi dengan acara
pemeriksaan singkat. Dalam rezim acara pemeriksaan singkat, UU 20/2025
menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling
lama 3 (tiga) tahun. Batas ini membentuk insentif struktural, yakni kooperasi
terdakwa di awal sidang dapat mengarahkan perkara ke rezim yang secara normatif
membatasi eksposur pidana penjara. Pada saat yang sama, hakim tetap memegang
diskresi untuk menilai proporsionalitas pidana di dalam batas tersebut, dengan
mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan. Dengan kata lain, penghargaan
terhadap kooperasi prosedural tetap ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang
bertanggung jawab dan tidak otomatis.
Ketiga,
Pasal 234 menunjukkan hubungan yang lebih eksplisit antara pengakuan, acara
pemeriksaan singkat, dan plafon pemidanaan pada situasi pengakuan saat dakwaan
dibacakan. Pasal ini mengatur bahwa, pada saat Penuntut Umum membacakan surat
dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah
melakukan tindak pidana dengan ancaman tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun,
Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
Pada fase ini, hakim wajib memberitahukan hak yang dilepaskan, memberitahukan
lamanya pidana yang mungkin dikenakan, menanyakan apakah pengakuan diberikan
secara sukarela, dan bahkan dapat menolak pengakuan jika ragu terhadap kebenarannya.
Lebih
penting lagi, Pasal 234 menetapkan batas eksplisit, yakni penjatuhan pidana
tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) dari maksimum pidana tindak pidana yang
didakwakan. Norma plafon ini mengandung pesan kebijakan yang jelas, yakni pengakuan
pada tahap dakwaan yang memenuhi syarat dapat menghasilkan konsekuensi
pemidanaan yang lebih terprediksi, tetapi tetap berada dalam kontrol hakim dan
tetap bergantung pada keyakinan hakim atas kebenaran pengakuan. Dengan
demikian, perbedaan output pemidanaan antarjalur tidak harus dipahami
sebagai deviasi dari asas persamaan di hadapan hukum, melainkan sebagai
diferensiasi yang dibenarkan oleh perbedaan perilaku prosedural yang relevan dan
perbedaan beban institusional yang ditanggung negara.
Jika
ketiga jalur disintesis, UU 20/2025 membangun spektrum insentif pemidanaan yang
bertingkat dan berbasis verifikasi. Pada Pasal 78, insentif lahir dari
kesepakatan yang memuat alasan pengurangan masa hukuman dan disaring melalui
kontrol hakim serta dukungan bukti minimum. Pada Pasal 204 - 205, insentif
lahir dari transisi ke acara singkat setelah uji integritas pengakuan, dengan
implikasi plafon pidana penjara dalam rezim acara singkat. Pada Pasal 234,
insentif dirumuskan sebagai plafon 2/3 maksimum bagi perkara tertentu yang
memenuhi syarat, disertai kewajiban hakim untuk menjelaskan hak yang dilepaskan
dan memastikan voluntariness. Keseluruhan desain ini menunjukkan bahwa
“insentif” bukanlah pengganti pembuktian, melainkan instrumen tata kelola
perkara yang mensyaratkan akuntabilitas proses.
Sebagai penutup, keberhasilan desain tersebut bergantung pada disiplin argumentatif para penegak hukum. Penuntut Umum perlu merumuskan alasan pengurangan dalam perjanjian Pasal 78 secara terukur dan dapat diuji, sekaligus memastikan adanya bukti yang memadai agar hakim dapat membangun keyakinan secara sah. Hakim perlu konsisten menempatkan voluntariness, pemahaman terdakwa, dan pengujian rasionalitas pidana sebagai prasyarat yang tidak dapat dikompromikan. Advokat, pada gilirannya, perlu memastikan pilihan jalur didasarkan pada informasi yang memadai, termasuk risiko dan manfaat normatif tiap rezim. Dengan penerapan yang cermat, arsitektur pemidanaan UU 20/2025 dapat berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian, dan kemanfaatan. (gp/ldr)
Baca Juga: Part 1. Plea Bargain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian
tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat lembaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI