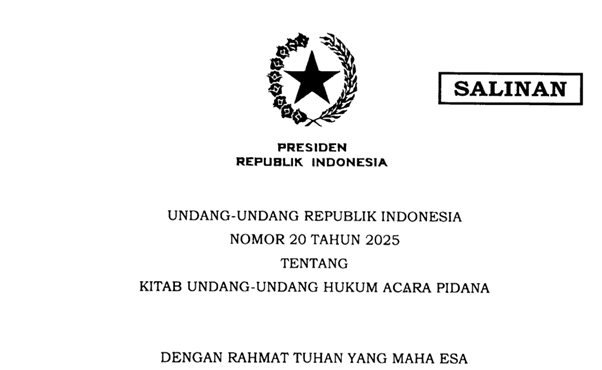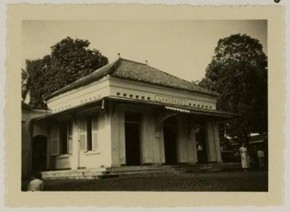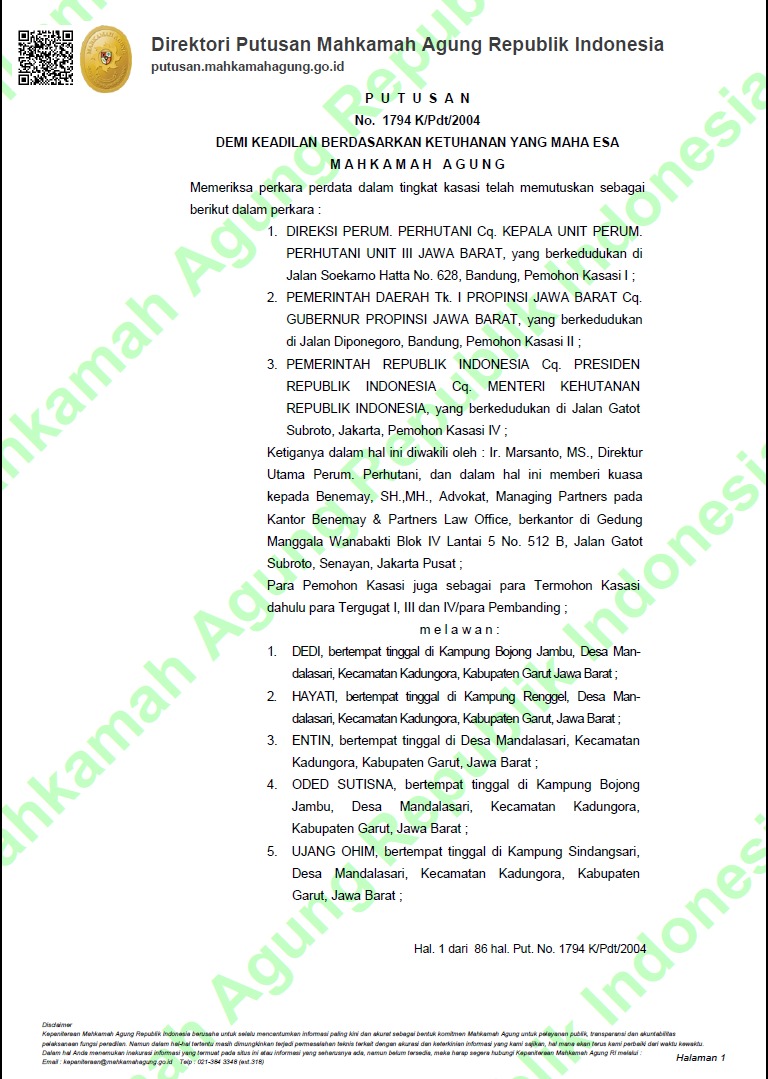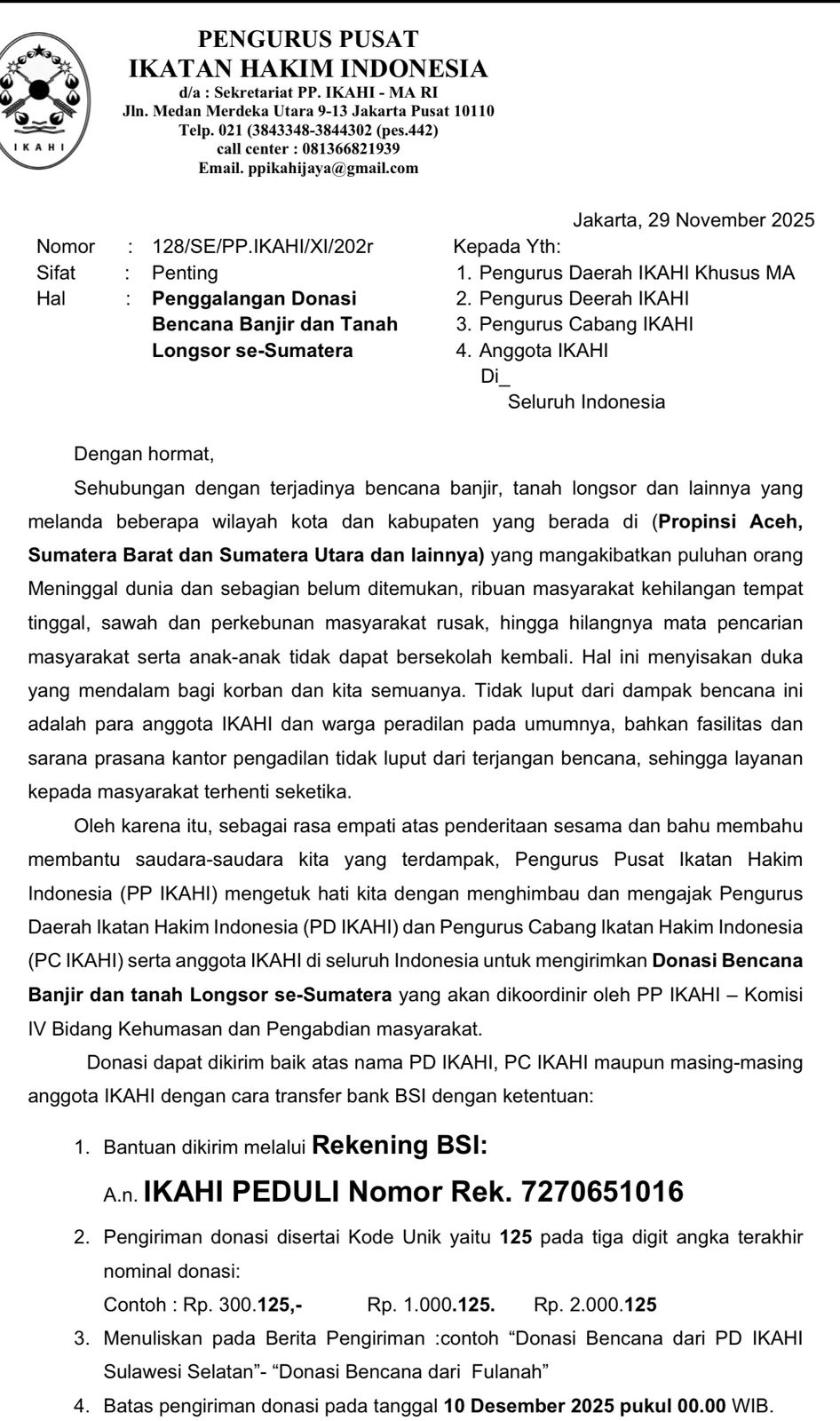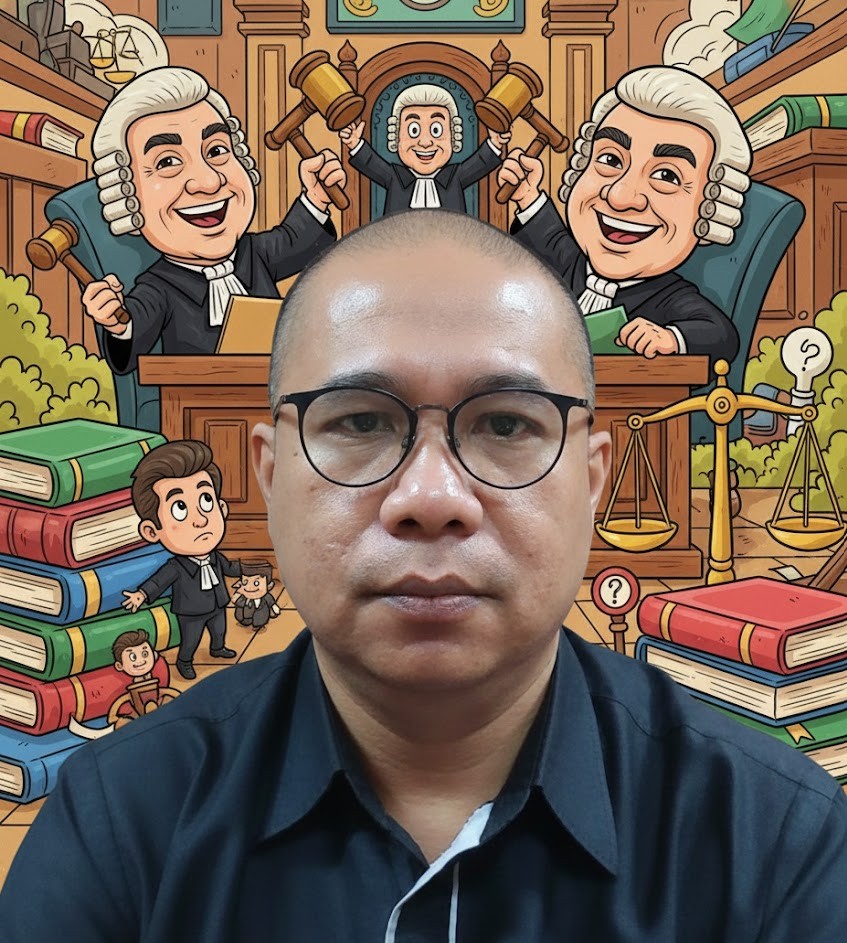Tragedi banjir dan tanah
longsor yang menimpa Pulau Sumatera, di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan
Sumatera Barat memakan korban jiwa yang tidak sedikit dan meluluh lantakkan
rumah, sawah, ladang dan harta benda lainnya dengan nilai kerugian tak
terhingga.
Paling tidak terdapat 34
Kabupaten dan Kota di tiga Provinsi tersebut yang terkena dampak signifikan.
Aktivitas perdagangan dan perkantoran lumpuh. Kota-kota dan desa-desa menjadi
terisolir, karena jembatan-jembatan dan jalan-jalan yang menuju ke sana
terputus.
Ketiadaan aliran listrik ‘black out’ yang menyebabkan sulitnya untuk
berkomunikasi dengan orang di sana. Banyak orang kelaparan, balita kekurangan
makanan dan susu karena terbatasnya persediaan. Bahkan dikabarkan di salah satu
kota sudah terjadi penjarahan di toko-toko yang menjual makanan.
Baca Juga: Ketua PN Simpang Tiga Redelong, Aceh: Operasional Kantor Lumpuh Total!
Tidak dapat disangkal
penyebab utama terjadinya bencana ini diakibatkan karena kerakusan manusia ‘greedy men” yang melakukan eksploitasi tidak
terkendali di daerah Bukit Barisan. Baik dilakukan secara sah dengan memegang
izin-izin atau konsesi-konsesi maupun dilakukan secara illegal.
Hutan-hutan dan belantara
bukit barisan yang berfungsi sebagai ‘giant sponge” dibabat dan dikonversi menjadi lahan tambang dan perkebunan dengan
dalih membuka lapangan kerja, menambah pendapat Negara, mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi sampai kepada dalih ‘komoditi ekstraktif’ dan sawit dapat
digunakan sebagai bargaining position
ke bangsa-bangsa lain.
Bukti nyata dari ini semua
secara kasat mata dapat terlihat dari kayu-kayu gelondongan dari daerah hulu,
daerah bukit barisan terbawa arus sungai yang kemudian terdampar di daerah-daerah
hilir. Di daerah Sumatera Barat, kayu gelondongannya sudah menutupi
pesisir-pesisir pantai. Bahkan bangkai Anak Gajah Sumatera yang merupakan hewan
endemik dan icon ‘Bukit
Barisan’ ikut hanyut bersama-sama kayu gelondongan di daerah Pidie Jaya,
Aceh.
Banjir dan longsor memang
sering terjadi di daerah Sumatera, akan tetapi persebaran dan kadarnya tidak
semasif saat ini. Kata seorang rekan Hakim yang bertugas di daerah Aceh bahwa
dirinya dan keluarga pernah mengalami kejadian serupa pada tahun 2006 di Kuala
Simpang, namun tidak separah sekarang.
Terlepas apakah tragedi ini
terdapat korelasi dengan kebijakan ‘weak sustainability’ yang terdapat di Undang-undang Cipta Tenaga Kerja, sudah semestinya
otoritas melakukan langkah-langkah efektif supaya kejadian serupa tidak
terulang di kemudian hari.
Apabila otoritas belum mampu
menerapkan kebijakan ‘deep ecology’ yang secara radikal menghentikan dan mencabut penerbitan izin-izin
kegiatan dan usaha yang mengeksploitasi alam.
Setidaknya otoritas dapat
menerapkan kebijakan ‘strong sustainability’ dalam penerbitan izin-izin kegiatan dan usaha di daerah pegunungan yang
merupakan daerah hulu tempat resapan dan sumber air.
Strong sustainability ini tidak dapat ditawar-tawar lagi alias merupakan conditio sine quanon agar perizinan dapat
diterbitkan. Bila perlu diterapkan kepada setiap perizinan yang berdampak
secara langsung terhadap lingkungan hidup. Selain itu izin-izin yang berdampak
langsung terhadap lingkungan hidup mesti dievaluasi. Apakah tetap dilanjutkan
dengan atau tanpa memberikan syarat-syarat tambahan, atau mencabutnya dengan
pertimbangan izin-izin yang diberikan tersebut berpotensi merusak lingkungan
hidup.
Tentu saja mengubah arah kebijakan dari
semula ‘weak sustainability’ menjadi ‘strong sustainability’ dan mengevaluasi izin-izin tersebut membawa konsekuensi yang tidak
ringan. Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang izinnya
batal diterbitkan atau dihentikan menjadi terhenti, penyerapan tenaga kerja
berkurang, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pada akhirnya dapat
menimbulkan permasalahan sosial baru.
Belum lagi otoritas mesti
mengkompensasi kerugian dari pemegang izin-izin tersebut, atau bahkan
berhadap-hadapan dengan pemilik izin-izin tersebut yang bisa saja dimiliki atau
dibekingi oleh actor-actor yang
menjadi bagian dari otoritas itu sendiri.
Dalam pilihan sulit ini
otoritas mau tidak mau harus mengambil pilihan yang memihak kepada
keberlangsungan lingkungan hidup (pro natura). Bukan saja karena dampak dari perubahan kebijakan tersebut masih jauh
lebih ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan dari banjir dan
longsor seperti sekarang ini, tetapi dengan memastikan keberlangsungan
lingkungan hidup maka otoritas juga telah menjamin kehidupan dan penghidupan
masyarakatnya.
Hal lain yang perlu dilakukan
oleh otoritas adalah melakukan langkah represif dalam menindak
aktifitas-aktifitas yang merusak lingkungan hidup. Salah satu langkah represif
yang mendesak untuk dilakukan adalah sesegera mungkin melakukan penyelidikan
terhadap dugaan kejahatan lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya banjir
dan tanah longsor.
Dengan segala perangkat, sarana
dan fasilitas yang dimiliki, otoritas dapat dengan mudah untuk menelusuri dan
menemukan aktifitas-aktifitas ilegal yang merusak lingkungan hidup. Otoritas
cukup memerintahkan perangkat-perangkat penegak hukum yang dimilikinya untuk
melakukan penindakan.
Sengketa-sengketa dikarenakan perubahan arah
kebijakan dan penindakan tersebut pada akhirnya akan diputuskan di Pengadilan.
Pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak terima aktifitasnya terhenti karena
izinnya akan membawa persoalan tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara, dan
pelaku kejahatan lingkungan hidup akan diadili di Peradilan Umum dan Militer.
Hakim-hakim yang mengadili perkara tersebut
memainkan peranan penting untuk menentukan keberlangsungan lingkungan hidup.
Apakah akan menjadi penjaga lingkungan hidup ‘the guardian of
environment’ dengan menerapkan nilai-nilai keadilan
lingkungan ‘green justice’,
ataukah bertoleransi terhadap eksploitasi. Itu semua ditentukan oleh ketukan
palu Hakim.
Pada akhirnya masa depan keberlangsungan
lingkungan hidup dan keselamatan rakyat ditentukan oleh pemegang-pemegang
otoritas. Dalih-dalih pertumbuhan ekonomi dan mengejar ketertinggalan dari
bangsa-bangsa lain kerapkali digunakan sebagai pembenaran oleh pemegang
otoritas untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan.
Usaha-usaha perlindungan lingkungan hidup
dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai penghambat pembangunan. Berdiri di
posisi anthropocentris yang
menganggap lingkungan hidup diperuntukkan untuk melayani kebutuhan manusia,
ataukah berdiri di posisi ecocentris dengan
hidup harmonis dan berdampingan bersama alam merupakan pilihan masing-masing.
Kiranya penting bagi kita untuk merenungkan secara mendalam perkataan Gandhi
yang berkata “earth provides enough to satisfy every
man’s need, but not even one man’s greed”. (al/ldr/seg)
Penulis Dr. Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H adalah Hakim PN Muara Enim
Baca Juga: Eksistensi Alat Bukti Bekas Hak Milik Adat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI