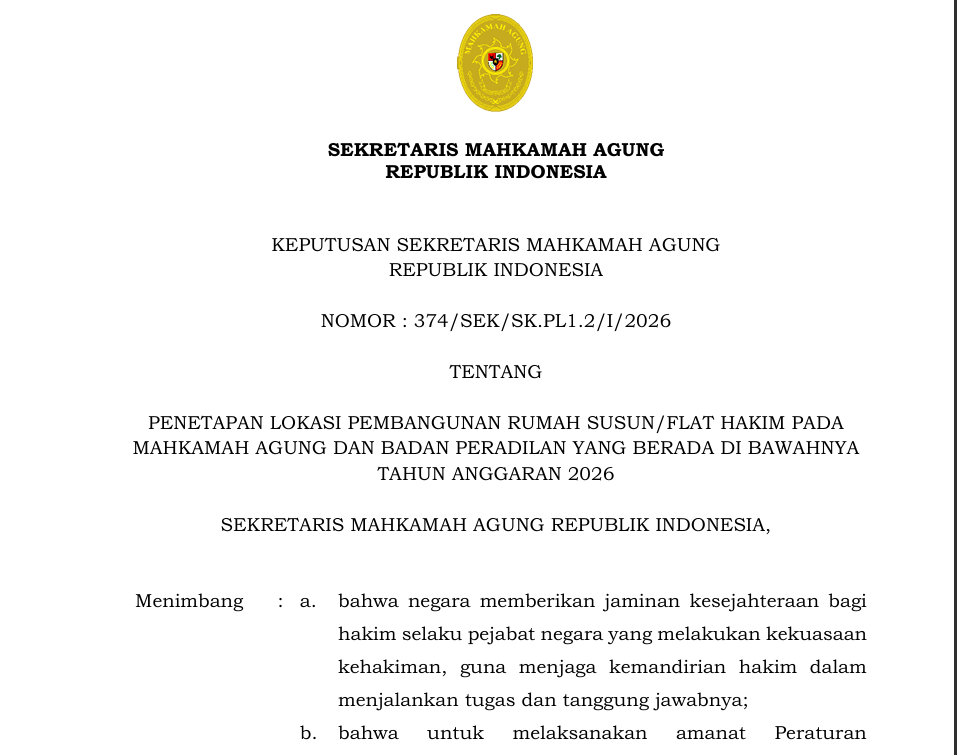Kontemplasi mengenai etika selalu menjadi “primus interpares” dalam pembahasan sebuah profesi. Setiap profesi pasti melekatkan etika dalam pondasi, bangunan dan puncak eksistensinya. Etika melalui turunannya kode etik, akhirnya menjadi penentu apakah sebuah profesi pantas disebut “Keadaan” atau ‘Kemuliaan”.
Etika menjadi salah satu cabang filsafat terpenting selain logika, yang menduduki tempat terhormat, bukan hanya dalam khazanah ilmu pengetahuan tapi juga setiap segmentasi kehidupan. Etika adalah prinsip dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat (Silalahi, Dkk., 2022).
Menyadari pentingnya pemahaman terhadap konsep etika, Badan Peradilan Umum MA RI tanggal 7 Oktober 2024 lalu, menggagas Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai) untuk melakukan diskusi lebih dalam tentang tema ini, meskipun perlu digaris bawahi, Perisai adalah kegiatan berkelanjutan sebagai wadah membuka ruang diskusi dan argumentasi di tengah semakin minimnya literasi. Etika, dipilih sebagai topik perdana karena keutamaannya.
Baca Juga: Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat: Ancaman atau Perlindungan terhadap Profesi Advokat?
Salah satu etika profesi yang selalu menarik atensi adalah pembahasan tentang etika profesi hakim. Tema ini sangat fundamental bukan hanya sebagai pembahasan utama dalam cabang pemikiran filsafat etika profesi tapi juga karena profesi hakim merupakan profesi utama dalam dunia penegakan hukum.
Menariknya, anomali situasi terjadi ketika diskusi perdana “Perisai” dibuka. Hari itu dua tepian peristiwa yang mungkin saja terpisah secara geografis, justru terkait secara etik. Peristiwa pertama, seperti disebutkan di awal tulisan ini adalah salah satu tema diskusi yang diangkat sebagai tema “Perisai” tentang kode etik hakim yang melibatkan seluruh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum secara daring.
Peristiwa kedua, dihari yang sama, sekumpulan hakim yang menamakan diri gerakan solidaritas hakim Indonesia justru sedang “berjuang” merefleksikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan mendatangi gedung DPR RI,. wakil tuhan mendatangi para wakil rakyat, adalah fenomena filsafat paling layak dipikirkan abad ini.
Ada beberapa tuntutan yang dikemukakan, tapi intinya lebih dari 12 (dua belas tahun) negara abai dalam memperhatikan nasib para wakil tuhan. Negara sedang mempertontonkan “cidera janji” terhadap salah satu pilar yudikatif yang menopang negara hukum.
Hakim turun ke jalan. Demikian diksi yang dipilih salah satu media. Maka bermunculanlah komentar kalap sebagian netizen. Diantaranya mempertanyakan etika para hakim yang justru seolah “mengemis” kesejahteraan kepada para wakil rakyat. Satire itu muncul, mengapa para wakil tuhan meminta itu kepada wakil rakyat? etika tanpa logika, katanya.
Tapi ada juga yang bijak dalam berkomentar. Kata mereka, memang pantas seorang hakim memperoleh hak sebagai pejabat negara atau sebagai wakil tuhan asalkan mereka pun siap menerima konsekuensi maksimal bila hakim menyimpang dari koridor etika yang telah digariskan. Wajar pejabat negara diperlakukan selayaknya pejabat negara dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang telah digariskan aturan.
Dalam dua tepian peristiwa ini, lagi-lagi kata “etika” digaungkan. Meski memiliki definisi, faktanya dalam ruang publik, etika adalah labirin yang menimbulkan kebingungan dan kegelisahan. Etika adalah kata yang begitu mudah diucapkan tapi begitu rumit ketika bersinggungan dengan kenyataan.
Dalam ruang terbatas, persepsi yang muncul dalam kedua peristiwa ini sebenarnya sangat berkaitan. Diskusi atau argumentasi terhadap etika yang digagas Perisai langsung menemukan contoh nyata dilapangan ketika etika berbenturan bukan dengan logika tapi justru dengan negara.
Hakim harus punya etika. Etika diatur dalam kode etik, maka setiap hakim harus tunduk dan patuh terhadap kode etik itu. Apakah hakim yang “turun ke jalan” yang tidak sidang, bersikap layaknya demonstran, melanggar etika ?. Belum tentu.
Etika tertinggi dianut oleh penguasa (baca : negara) untuk memastikan seluruh alat penggerak kekuasaan juga berjalan dalam koridor etika pula. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai “Tuhan” bukan lagi alat penyelenggara negara.
Ketika negara lalai memperhatikan eksistensi hakim termasuk kesejahteraan mereka dan hak haknya, itu satu hal. Tapi hal lain yang luput dari pemikiran adalah kelalaian ini berpotensi menyulut pelanggaran etika dari hakim itu sendiri. Godaan, ancaman kekerasan, pengabaian hak, hanya untuk menyebut sedikit diantaranya membuat hakim sangat mungkin melakukan pelanggaran kode etik dalam profesinya. Tapi perlu dicatat, sedikit banyak, hal ini bisa muncul dari “ketidak-hadiran Tuhan” dalam memperhatikan nasib mereka. Lagipula, ketika wakil rakyat menerima para wakil tuhan, para wakil rakyat ini bertindak atas semboyan ‘Vox populi Vox Dei”.
Maka peristiwa hakim turun ke jalan hanyalah preferensi moral yang diterjemahkan dalam pertanyaan dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan “Tuhan”. Metamorfosis penegak keadilan menjadi pencari keadilan adalah masalah lain. Tapi sekali lagi, inilah semiotika ketidak-adilan.
Semiotika adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna dalam sebuah tanda. Menurut Susanne Langer, menilai simbol atau tanda merupakan sesuatu yang penting kehidupan binatang diperantarai oleh perasaan (feeling) tetapi perasaan manusia diperantarai oleh sejumlah konsep, simbol dan bahasa (Morison, 2013).
Meski harus diakui, sangat ironis melekatkan pertanda ini kepada para hakim yang di tangan mereka keadilan ditegakkan, di pundak mereka kebenaran terakhir dipertaruhkan, dan di dalam hati dan pikiran mereka lah konstitusi dijaga dan diwariskan.
Semiotika ketidak-adilan ini menjadi begitu brutal karena beberapa hal, pertama, melibatkan “Tuhan” dan wakilnya sebagai fragmen kegagalan bernegara, kedua, keseimbangan tiga pilar penyelenggara negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan ketiga, terbelahnya riuh persepsi publik dalam menyikapi fenomena ini.
Satu hal yang pasti, etika meskipun sifatnya ideal tapi akan selalu ada dalam ruang realitas. Etika yang dijabarkan dalam kode etik, apapun profesinya adalah konjungsi timbal balik antara nilai dan penganutnya. Mustahil berharap etika akan dipenuhi, apabila nilai yang diharapkan untuk mematuhi etika itu malah diabaikan. Bila Anda berharap hakim sepenuhnya patuh pada etika sebagai pejabat negara, tapi disisi lain hak dan kewajibannya tidak sepenuhnya juga dipenuhi, maka di titik itu anda melakukan pengabaian terhadap gambaran etika itu sendiri.
Hakim meskipun disimbolkan sebagai wakil tuhan tetaplah manusia biasa. Bukan sekadar tempat salah dan dosa tapi tempat segala godaan diuji coba. Saat tulisan ini dibuat penawar letih tuntutan hakim telah dipenuhi. Tapi itu hanya penawar sementara sedangkan masalah sesungguhnya lebih dari itu.
Sekali lagi masalah hakim di Indonesia adalah semiotika ketidak-adilan. Tanda-tanda ini akan terus ada bila negara sebagai pengayom dan penegak konstitusi gagal atau lalai dalam menjaga konstitusi.
Memang benar bahwa sampai kapan pun, dalam dunia manapun, ketidakadilan akan selalu ada tak jarang pula ketidak-adilan ini menjadi gambaran paripurna yang meruntuhkan suatu rezim. Tapi, tak ada yang lebih mengkhawatirkan bila palu yang menjadi pemukul ketidakadilan justru “break” sejenak karena sang pemegang palu sedang menuntut keadilan.
Baca Juga: Akuntansi Forensik, Jurus Baru Pemberantasan Korupsi
Semiotika ini berbahaya dan tak boleh lagi terulang di masa depan. Bila negeri ini ingin tetap kukuh sebagai negara hukum, maka sepantasnya hukum dan hakim harus seiring sejalan.
John F. Kennedy pernah berujar, jangan tanyakan apa yang dilakukan negara untukmu, tapi tanyakan apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu. Biarkan hakim “berbuat” untuk negaranya, tapi pastikan “negara” juga hadir dalam proses dialektika itu. Ini semata bukan karena negara kita adalah negara hukum, tapi karena hukum, pada akhirnya, adalah “negara” itu sendiri. (FAC, LDR)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI