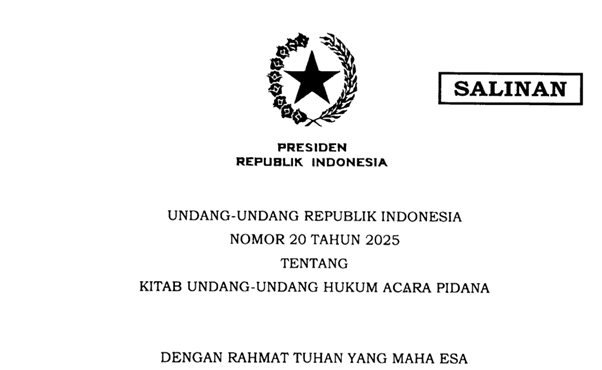Sudah sejak puluhan tahun lalu, hukum acara pidana Indonesia
membiasakan hakim membuat pertimbangan putusan pemidanaan yang disusun secara
“ringkas”. Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana merumuskan kewajiban memuat pertimbangan ringkas mengenai
fakta, keadaan, dan alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
Rumusan ini membentuk kebiasaan institusional, selama fakta dan alat bukti
disebutkan, putusan dianggap sahih secara prosedural.
KUHAP baru mengubah penekanan tersebut. Pasal 250 ayat
(1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menuntut pertimbangan yang
disusun secara jelas dan lengkap mengenai fakta, keadaan, serta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Perubahan ini
bukan sekadar kosmetik redaksional. Perubahan ini menandai pergeseran cara
hukum memahami fungsi putusan pidana dari ringkasan proses menuju
justifikasi rasional yang dapat dipahami dan diuji.
Pertanyaan kuncinya kemudian muncul: apakah perubahan
norma ini hanya menambah beban administratif, atau justru menggeser standar
legitimasi putusan pidana?
Baca Juga: Intelijen, Algoritma dan Bayang-Bayang di Balik Layar Digital
Dari Putusan sebagai Ringkasan ke Putusan sebagai Alasan
Dalam KUHAP lama, “ringkas” berfungsi sebagai toleransi
normatif. Pertimbangan putusan cukup menunjukkan bahwa fakta dan alat bukti
telah dipertimbangkan. Hubungan logis antara keduanya sering kali tidak
dijabarkan secara eksplisit. Logika yang bekerja adalah logika proses,
kebenaran dianggap telah diuji di persidangan, sementara putusan berfungsi
sebagai penutup formal.
Pendekatan ini berbeda dengan tuntutan “jelas dan
lengkap” dalam KUHAP baru. Kejelasan menuntut keterpahaman bagi pembaca
putusan, sedangkan kelengkapan menuntut penjelasan yang memadai tentang
bagaimana fakta dan alat bukti memenuhi unsur delik. Putusan tidak lagi sekadar
menyatakan hasil, tetapi harus memperlihatkan alur penalaran yang
menghubungkan premis faktual dengan kesimpulan hukum.
Dalam teori hukum, pergeseran ini sejalan dengan gagasan
bahwa legitimasi hukum lahir dari alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
bukan dari otoritas semata. Lon L. Fuller, misalnya, menempatkan rasionalitas
dan keterjelasan sebagai syarat moral internal hukum (Lon L. Fuller, The
Morality of Law, 1964). Dalam kerangka ini, putusan pidana yang “jelas dan
lengkap” bukan tuntutan estetika, melainkan tuntutan etis.
Dengan demikian, KUHAP baru secara implisit menaikkan
standar putusan pidana. Putusan harus menunjukkan bukan hanya apa yang
diyakini, tetapi bagaimana keyakinan tersebut dibentuk melalui pembuktian.
Benturan dengan Budaya Putusan Ringkas
Perubahan norma ini berhadapan langsung dengan budaya
“putusan ringkas” yang telah lama mengakar. Budaya tersebut lahir dari
kebutuhan efisiensi, beban perkara, dan tradisi administratif yang menempatkan
sistematika di atas argumentasi. Putusan pendek dianggap cepat, praktis, dan
aman secara prosedural.
Namun, tuntutan “jelas dan lengkap” mengganggu kenyamanan
tersebut. Efisiensi prosedural kini harus berdampingan dengan akuntabilitas
rasional. Putusan yang terlalu ringkas berisiko tidak lagi memenuhi standar
normatif baru, sementara putusan yang panjang tetapi tidak argumentatif tetap
gagal memenuhi tujuan hukum acara pidana.
Di sini terdapat jebakan yang perlu dihindari, menyamakan
“jelas dan lengkap” dengan “panjang”. Kelengkapan bukan soal jumlah halaman,
melainkan soal kecukupan alasan. Putusan yang singkat masih mungkin memenuhi
standar baru, sepanjang hubungan antara fakta, alat bukti, dan unsur delik
dijelaskan secara transparan. Sebaliknya, putusan yang panjang dapat tetap
bermasalah apabila hanya bersifat deskriptif tanpa struktur inferensial.
Implikasi praktisnya juga terasa dalam mekanisme upaya
hukum. Banding dan kasasi tidak lagi cukup menguji kesesuaian amar dengan
dakwaan, tetapi semakin menguji kualitas penalaran. Dalam konteks ini, putusan
tingkat pertama menjadi fondasi utama bagi kontrol yudisial di tingkat lebih
tinggi (bandingkan dengan peran reason-giving dalam putusan menurut
Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, 1989).
Tantangan Kelembagaan dan Template Putusan
Perubahan norma ini membawa konsekuensi kelembagaan yang
signifikan, khususnya bagi Pengadilan. Selama ini, template putusan berfungsi
sebagai panduan sistematika dan keseragaman administratif. KUHAP baru menuntut
lebih dari itu. Template tidak lagi cukup sebagai kerangka formal, tetapi perlu
menjadi alat bantu penalaran.
Template yang hanya menyediakan bagian “fakta”, “alat
bukti”, dan “pertimbangan” tanpa struktur hubungan logis berisiko melanggengkan
budaya lama dalam bungkus baru. Tuntutan “jelas dan lengkap” memerlukan
template yang mendorong keterkaitan eksplisit antara alat bukti tertentu dengan
unsur delik tertentu, serta alasan penolakan terhadap alternatif penafsiran
yang mungkin.
Dalam perspektif kelembagaan, pembaruan template bukan
sekadar soal teknis. Pembaruan ini menyentuh fungsi Mahkamah Agung sebagai
penjaga kualitas penalaran peradilan. Tanpa pembaruan template, terdapat risiko
bahwa norma KUHAP baru hanya dipenuhi secara formal, sementara budaya penalaran
substantif tidak berubah.
Di sisi lain, template yang dirancang dengan baik dapat
berfungsi pedagogis. Template semacam itu membantu membangun kebiasaan berpikir
yang lebih sistematis dan transparan, tanpa harus mengorbankan independensi
hakim dalam menilai perkara.
Penutup
Pertanyaan “putusan pidana tak bisa lagi ringkas?” bukan
pertanyaan tentang panjang tulisan, melainkan tentang standar legitimasi
kekuasaan kehakiman. KUHAP baru menandai pergeseran dari peradilan yang
cukup diyakini menuju peradilan yang harus dapat dijelaskan. Pergeseran ini
menuntut perubahan budaya, bukan sekadar perubahan redaksi pasal.
Apabila tuntutan “jelas dan lengkap” dibaca sebagai beban
administratif, perubahan ini akan berakhir pada putusan yang lebih panjang
tanpa menjadi lebih adil. Namun, apabila tuntutan tersebut dibaca sebagai
kewajiban etis untuk memperlihatkan penalaran, putusan pidana berpeluang
menjadi instrumen akuntabilitas yang sesungguhnya.
Baca Juga: Judgment Summary: Jembatan antara Peradilan dan Publik
Dalam kerangka itu, putusan pidana memang tidak bisa lagi
“ringkas”. Yang dipertaruhkan bukan efisiensi semata, melainkan kepercayaan
terhadap rasionalitas peradilan pidana itu sendiri. (NP/LDR/SNR)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI