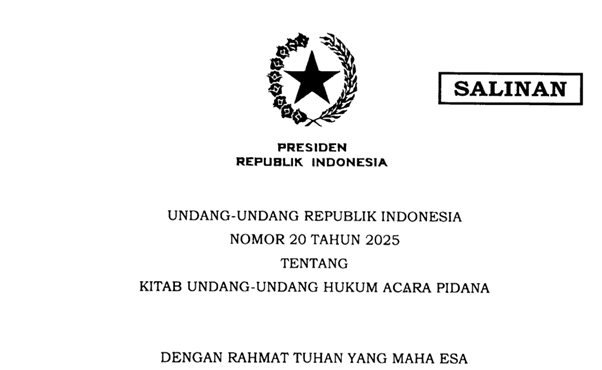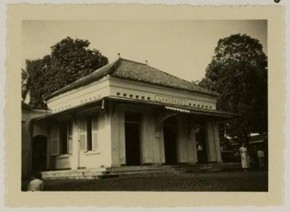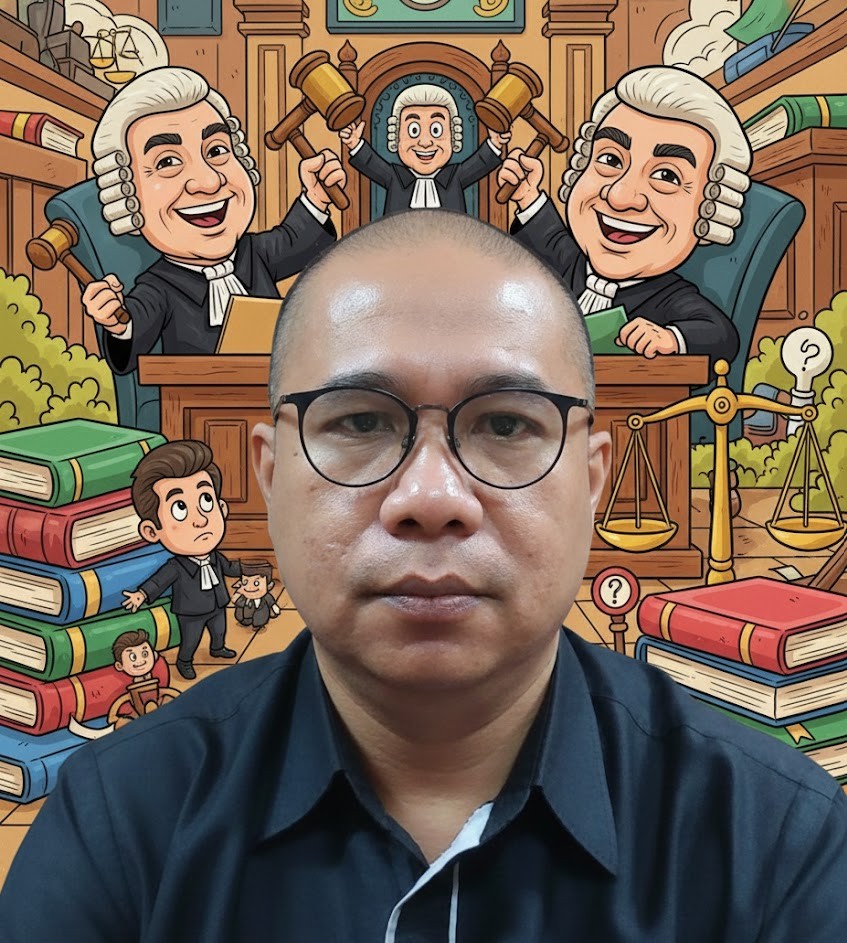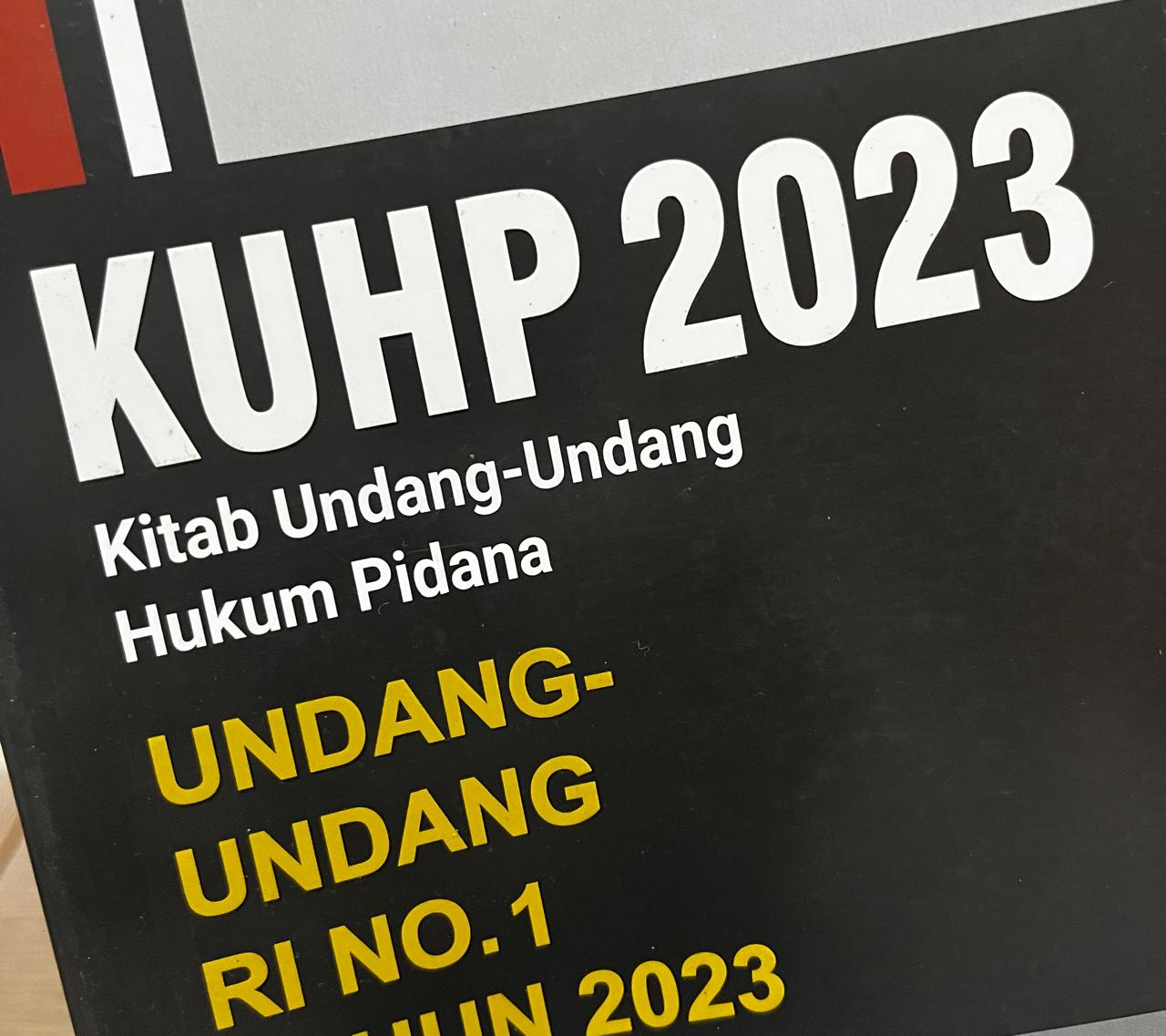Reformasi
hukum pidana Indonesia melalui
pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
Nasional) dan perkembangan hukum formilnya menandai paradigma baru bagi sistem
peradilan pidana Indonesia.
Salah satu manifestasi paling progresif adalah
pengadopsian secara tegas sistem dua jalur (double track system). Sistem
ini tidak lagi hanya mengandalkan sanksi pidana (straf) yang bersifat
retributif, tetapi juga memperkenalkan sanksi tindakan (maatregel) yang
bersifat rehabilitatif.
Secara teoretis, sanksi pidana berorientasi pada
penderitaan istimewa (bijzonder leed) sebagai respons atas kesalahan
masa lalu pelaku (daader-strafrecht). Sebaliknya, sanksi tindakan
berorientasi pada masa depan (doelmatigheid), yakni upaya perlindungan
masyarakat dan perawatan bagi pelaku agar dapat berintegrasi kembali secara
sosial.
Baca Juga: Menelisik Eksistensi Sanksi Tindakan dalam KUHP Nasional
Pengaturan sanksi tindakan merupakan terobosan progresif
yang memperkuat posisi Hakim sebagai penjaga keadilan individual. Dalam sistem
lama, Hakim terbatas pada penentuan berat-ringan pidana (strafmaat), sementara jenis pidana (strafsoort) telah ditentukan secara imperatif oleh undang-undang.
Kini, melalui sanksi tindakan, Hakim diberi diskresi luas
untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi pelaku, seperti rehabilitasi narkotika
atau pembinaan mental, tanpa terikat ketat pada rumusan pidana pokok. Ini
selaras dengan prinsip individualisasi pemidanaan dalam teori modern, yang
menekankan penilaian kasus per kasus untuk memaksimalkan efektivitas hukum.
Namun, di balik semangat pembaruan ini, terdapat ganjalan
yuridis berupa ketidaksinkronan formulasi norma antara hukum materiil (KUHP)
dan hukum formil (KUHAP) yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid)
dalam praktiknya di meja hijau.
Ketidaksinkronan ini tidak hanya terjadi pada aspek cara
pengenaan, tetapi juga pada eksistensi sanksi itu sendiri sebagai sanksi
mandiri.
Hukum Materiil (Pasal 103 KUHP Nasional) menyatakan
tindakan "dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok".
Secara tekstual, KUHP Nasional tidak membuka ruang bagi penerapan sanksi
tindakan secara tunggal. Pembentuk undang-undang mendesain tindakan sebagai
komplementer yang melekat pada pidana pokok. Artinya, tanpa adanya pidana pokok
yang dijatuhkan, sanksi tindakan kehilangan landasan hukum materiilnya untuk
berdiri sendiri.
Hukum Formil (Pasal 244 KUHAP Baru): Menyatakan terdakwa "dikenai
sanksi berupa pidana atau tindakan". Formulasi ini memposisikan sanksi
tindakan sebagai alternatif eksklusif dari pidana, sehingga tidak memungkinkan
penerapan gabungan. Penggunaan konjungsi "atau" di sini secara
eksplisit memberikan ruang bagi Hakim untuk menjatuhkan tindakan secara tunggal
sebagai alternatif dari pidana. Ini bertentangan dengan semangat KUHP Baru, di
mana sanksi tindakan dirancang sebagai pelengkap, bukan pengganti mutlak.
Perbedaan ini menimbulkan komplikasi serius bagi Hakim di
ranah praktik peradilan. Jika Hakim mengikuti KUHAP dan menjatuhkan sanksi
tindakan secara tunggal (tanpa pidana pokok), maka secara materiil Hakim
berisiko melanggar Asas Legalitas (nulla poena sine lege). Mengapa
demikian? Karena dalam hukum pidana, jenis dan cara pengenaan sanksi harus
ditentukan secara limitatif oleh hukum materiil.
Apabila KUHP (sebagai sumber hukum materiil) hanya
mengakui tindakan sebagai sanksi yang "menyertai" pidana pokok, maka
tindakan tunggal adalah sanksi yang "tidak dikenal" oleh hukum
materiil tersebut, kecuali untuk subjek hukum tertentu seperti penyandang
disabilitas mental atau anak yang ditentukan khusus. Bagi pelaku dewasa pada
umumnya, menjatuhkan tindakan secara tunggal berdasarkan Pasal 244 ayat (1)
KUHAP justru akan bertabrakan dengan batasan Pasal 103 KUHP.
Dalam doktrin hukum, berlaku asas substantive law
defines the rights and duties, while procedural law provides the machinery for
enforcing them. Hukum acara (formil) seharusnya menjadi "pelayan"
bagi hukum materiil. Hukum acara seharusnya berfungsi sebagai sarana
menjalankan hukum materiil (adjectief recht).
Secara logika hukum, jika hukum materiil memperbolehkan
kumulasi (pidana + tindakan), maka hukum formil tidak boleh menutup pintu
tersebut dengan formulasi alternatif. Dalam kasus ini, hukum formil (KUHAP)
justru "menciptakan" kemungkinan pemidanaan yang lebih luas (yakni
tindakan tunggal) yang tidak diakomodasi oleh hukum materiilnya (KUHP).
Ketidaksinkronan ini membawa dampak pada dua hal yaitu
Ketidakpastian Hukum dan Ancaman Diskresi yang Liar. Terdakwa tidak mendapat
gambaran pasti apakah dirinya bisa lolos dari pidana penjara hanya dengan
sanksi tindakan (rehabilitasi/perawatan). Pada sisi lain, Hakim dipaksa
melakukan pilihan sulit yaitu menuruti teks KUHAP namun melanggar doktrin
sanksi materiil, atau mengikuti teks KUHP namun dianggap mengabaikan
fleksibilitas yang diberikan KUHAP.
Solusi Yuridis dan Posisi Hakim
Untuk menjawab persoalan ini, Hakim harus kembali pada
prinsip bahwa sanksi adalah substansi hukum materiil. Dalam konteks pemidanaan,
hukum materiil adalah "hulu" yang menentukan apa sanksinya,
sedangkan hukum formil adalah "hilir" mengenai bagaimana cara
menjatuhkannya. Jika KUHAP memberikan pilihan (alternatif) yang tidak
disediakan oleh KUHP, maka Hakim harus memprioritaskan KUHP demi menjaga Asas
Legalitas. Sanksi yang tidak diakui hukum materiil adalah sanksi yang tidak sah
(nulla poena sine lege).
Karena KUHP telah menggariskan bahwa tindakan adalah
instrumen yang "dikenakan bersama-sama" dengan pidana pokok, maka
idealnya, formulasi "atau" dalam KUHAP harus dimaknai secara
restriktif.
Hakim sebaiknya tetap berpedoman pada Pasal 103 ayat (1)
KUHP Nasional yaitu menjatuhkan sanksi tindakan sebagai penguat pidana pokok,
bukan sebagai pengganti total, kecuali pada kasus-kasus di mana hukum materiil
sendiri memberikan pengecualian (seperti alasan pemaaf karena gangguan jiwa).
Menjatuhkan tindakan secara tunggal kepada pelaku yang terbukti bersalah tanpa
adanya landasan dalam KUHP materiil adalah tindakan yang rapuh secara yuridis.
Disharmoni antara pola kumulatif dalam KUHP dan pola
alternatif tunggal dalam KUHAP adalah "cacat logika" legislasi yang
meletakkan Hakim pada posisi dilematis. Perlu ada upaya harmonisasi segera agar
hukum formil tidak bergerak liar melampaui batas-batas yang telah dipagari oleh
hukum materiil. Keadilan tidak hanya harus dicapai, tetapi harus dicapai melalui
prosedur dan jenis sanksi yang sah menurut hukum materiil yang berlaku.
Baca Juga: Mengenal Jenis Sanksi Hukum di Jawa Abad ke-18, dari Cambuk hingga Dibuang
Keadilan restoratif dan rehabilitatif adalah masa depan,
namun ia tidak boleh dibangun di atas fondasi yuridis yang retak. Sebelum KUHAP
disinkronkan secara legislatif, Hakim adalah benteng terakhir yang harus
memastikan bahwa progresivitas tetap berjalan dalam koridor legalitas yang
ketat. Tanpa itu, diskresi bukan lagi alat mencapai keadilan, melainkan pintu
menuju ketidakpastian. (Np/Ldr/Snr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI