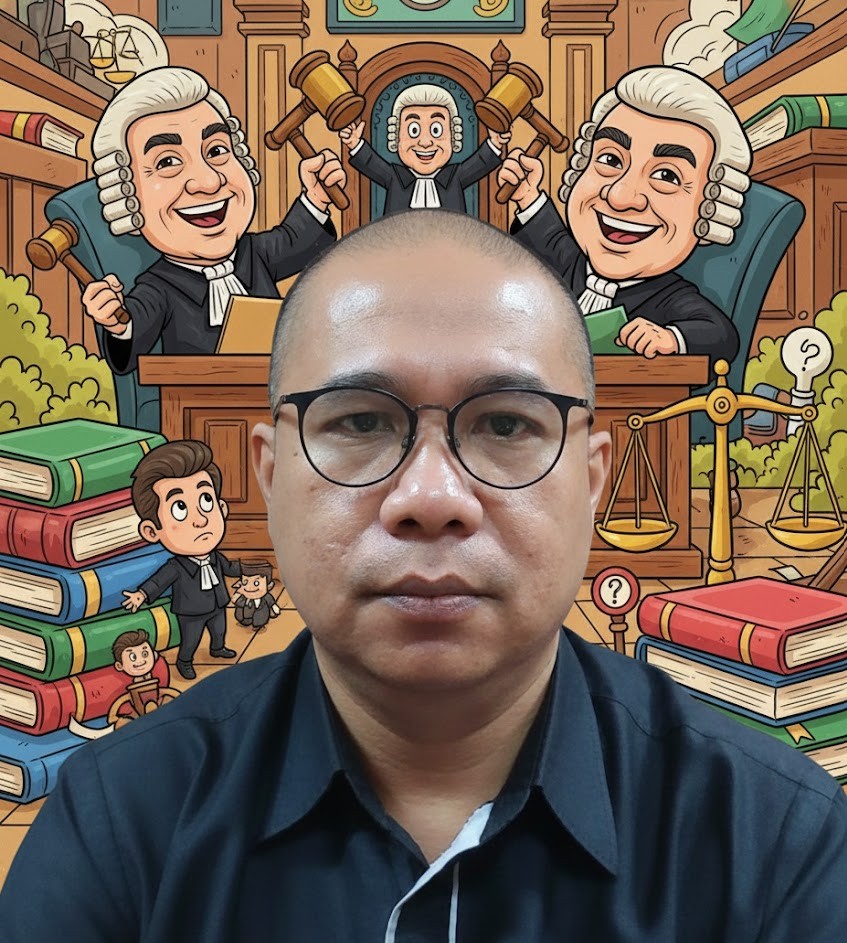Pengesahan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP 2025) menandai transformasi fundamental hukum Indonesia menuju paradigma adversarial yang humanis. Inovasi utamanya, Pasal 78 mengenai mekanisme pengakuan bersalah, hadir untuk mengatasi stagnasi perkara secara pragmatis. Namun, terdapat residu normatif pada kewenangan absolut Hakim Tunggal yang memikul beban ganda sebagai fasilitator sekaligus adjudikator substansial.
Konstruksi ini rentan memicu bias kognitif yang mencederai asas due process of law, terutama jika pengakuan ditolak. Sebagai solusi konstruktif, diperlukan harmonisasi interpretasi Pasal 271 dan 272 KUHAP 2025 guna memitigasi risiko psikologi yudisial tersebut serta menjamin tegaknya keadilan substansial demi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa.
Secara tekstual, Pasal 78 KUHAP 2025 mendesain sebuah fast track bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Desain ini memberikan mandat eksklusif kepada Hakim Tunggal untuk memeriksa validitas pengakuan tersebut dalam sebuah sidang pendahuluan (preliminary hearing).
Baca Juga: Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan?
Hakim tidak sekadar berfungsi sebagai "stempel administratif", namun dibebani kewajiban moral dan hukum untuk melakukan uji sukarela dan memastikan kebenaran materiil berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Sampai di sini, konstruksi hukum tampak ideal sebagai wujud efisiensi peradilan.
Namun, titik nadir keadilan muncul ketika menempatkan norma ini dalam skenario kegagalan kesepakatan. Pasal 78 ayat (10) memberikan wewenang kepada hakim untuk menolak pengakuan bersalah, baik karena keraguan atas kesukarelaan terdakwa maupun ketidakcukupan bukti, yang berimplikasi pada peralihan prosedur ke Acara Pemeriksaan Biasa. Di sinilah letak vacuum of norm yang berbahaya: undang-undang tidak secara eksplisit melarang Hakim Tunggal yang telah menolak pengakuan tersebut untuk kembali duduk memeriksa perkara pokok (baik sebagai hakim tunggal maupun anggota majelis).
Ketiadaan larangan eksplisit ini membuka celah terjadinya degradasi imparsialitas. Hakim Tunggal yang telah terpapar pada pengakuan dosa terdakwa, meskipun secara hukum pengakuan tersebut telah dianulir, tidak lagi berada dalam posisi tabula rasa saat memasuki sidang pemeriksaan biasa. Ia membawa serta beban pre-trial knowledge yang secara inheren merusak objektivitasnya.
Dalam doktrin hukum acara pidana yang ketat, situasi ini melanggar prinsip nemo judex in causa sua dalam tafsir yang lebih luas: seseorang tidak boleh mengadili perkara di mana ia telah membentuk opini awal (pre-judgment) terhadap substansi perkara tersebut.
Untuk memahami kedalaman bahaya ini, kita tidak dapat hanya bersandar pada logika hukum normatif semata, melainkan harus meminjam pisau analisis psikologi kognitif. Manusia, termasuk seorang hakim yang paling terpelajar sekalipun, bukanlah entitas mekanis yang mampu melakukan pemisahan memori secara sempurna.
Ketika seorang hakim mendengar terdakwa berkata, "Saya bersalah," informasi tersebut terpatri dalam kognisinya sebagai fakta inkriminatif yang paling kuat. Jika kemudian pengakuan itu ditarik kembali atau ditolak karena alasan teknis prosedural, hakim dihadapkan pada tantangan neurologis yang mustahil: menghapus jejak memori tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai ironic process theory, di mana upaya sadar untuk mengabaikan informasi justru memperkuat keberadaan informasi tersebut dalam alam bawah sadar.
Lebih jauh, bahaya laten yang mengintai adalah bekerjanya bias konfirmasi. Jika hakim yang sama memeriksa perkara pokok, ia cenderung secara tidak sadar mencari, menginterpretasi, dan memberikan bobot lebih pada bukti-bukti yang mendukung hipotesis awalnya, bahwa terdakwa sebenarnya bersalah namun gagal dalam prosedur plea. Bukti-bukti yang meringankan atau alibi terdakwa akan dipandang dengan skeptisisme berlebih, sementara bukti yang memberatkan akan diterima sebagai konfirmasi atas keyakinan sebelumnya.
Selain itu, terdapat risiko efek jangkar dalam penjatuhan pidana. Dalam proses negosiasi awal yang gagal, mungkin telah terlontar angka tuntutan atau tawaran hukuman. Angka ini, meskipun batal demi hukum, tetap tertanam sebagai titik referensi psikologis bagi hakim. Akibatnya, diskresi hakim dalam memutus perkara pokok menjadi terbelenggu oleh bayang-bayang negosiasi masa lalu, menihilkan kemerdekaan hakim dalam menggali keadilan berdasarkan fakta persidangan yang murni.
Kekhawatiran ini bukanlah paranoia tanpa dasar. Yurisdiksi global yang telah mapan, baik dalam tradisi Common Law maupun Civil Law, telah lama menyadari bahaya kontaminasi bias ini. Di Amerika Serikat, Federal Rules of Criminal Procedure secara tegas melarang partisipasi aktif hakim dalam negosiasi plea demi menjaga citra netralitas.
Sementara itu, di Jerman, yang sistem hukumnya memiliki genealogi dekat dengan Indonesia, prinsip incompatibility diterapkan secara ketat. Hakim yang telah menunjukkan indikasi pembentukan opini awal wajib didiskualifikasi dari persidangan utama.
Absennya mekanisme firewall yang tegas dalam Pasal 78 KUHAP 2025 menunjukkan bahwa legislator mungkin terlalu fokus pada aspek efisiensi prosedural, sehingga melupakan aspek psikologis penegakan hukum. Kita mengadopsi instrumen modernitas, namun alpa memasang katup pengaman yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan instrumen tersebut oleh kelemahan kognitif manusia.
Dalam situasi ketidakpastian ini, interpretasi hukum yang progresif dan sistematis mutlak diperlukan. Kita tidak boleh membaca Pasal 78 sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus diletakkan dalam satu tarikan napas dengan Pasal 271 dan 272 KUHAP 2025. Kedua pasal ini sejatinya menyediakan instrumen korektif untuk menetralisir racun bias kognitif yang dihasilkan oleh kegagalan Pasal 78.
Pasal 272 ayat (1) memberikan hak imperatif kepada terdakwa untuk mengajukan permohonan pergantian hakim apabila terdapat "alasan yang kuat mengenai objektivitas". Frasa ini harus ditafsirkan secara ekstensif. Pengetahuan hakim atas pengakuan bersalah yang batal demi hukum adalah bukti autentik hilangnya objektivitas. Oleh karena itu, pasal ini dapat dijadikan sebagai senjata utama litigasi untuk menolak hakim yang terkontaminasi bias pre-judgment. Ini bukan bentuk pembangkangan terhadap pengadilan, melainkan upaya menjaga kesucian proses peradilan itu sendiri.
Di sisi lain, Pasal 271 ayat (2) meletakkan beban etis di pundak korps hakim. Pasal ini mewajibkan hakim untuk mengundurkan diri jika memiliki potensi konflik kepentingan atau ketidakberpihakan. Dalam konteks ini, "kepentingan" tidak boleh direduksi hanya pada hubungan kekerabatan atau finansial semata. Kepentingan psikologis untuk membenarkan keyakinan awal bahwa terdakwa bersalah adalah bentuk konflik kepentingan yang paling halus namun mematikan. Oleh karenanya, pengunduran diri hakim yang telah memeriksa plea yang gagal bukanlah opsi, melainkan sebuah kewajiban moral dan yuridis.
Sebagai epilog, implementasi Pasal 78 UU Nomor 20 Tahun 2025 adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan jalan keluar dari kemacetan birokrasi peradilan; di sisi lain, ia berpotensi menjadi lorong gelap bagi matinya keadilan substantif jika tidak dikelola dengan presisi.
Oleh karena itu, diperlukan langkah taktis yang segera dan terukur. MA, sebagai benteng terakhir keadilan, diharapkan menerbitkan regulasi teknis yang melarang Hakim Tunggal pemeriksa plea untuk terlibat dalam pemeriksaan pokok perkara jika pengakuan ditolak. Mekanisme pemisahan berkas perkara dan rotasi majelis hakim seharusnya dilembagakan secara baku.
Hukum acara pidana bukan sekadar deretan aturan tentang cara memenjarakan orang, melainkan monumen perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara, termasuk kesewenang-wenangan yang lahir dari bias kognitif aparaturnya. Dengan menerapkan standar etika dan prosedur yang ketat melalui optimalisasi Pasal 271 dan 272, diharapkan KUHAP 2025 tidak hanya menjadi simbol modernisasi di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen penegak keadilan yang hidup, objektif, dan terpercaya. (ldr)
Baca Juga: Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia
Tulisan pendapat pribadi, dan tidak mewakili lembaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI