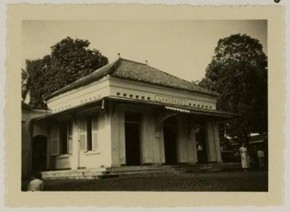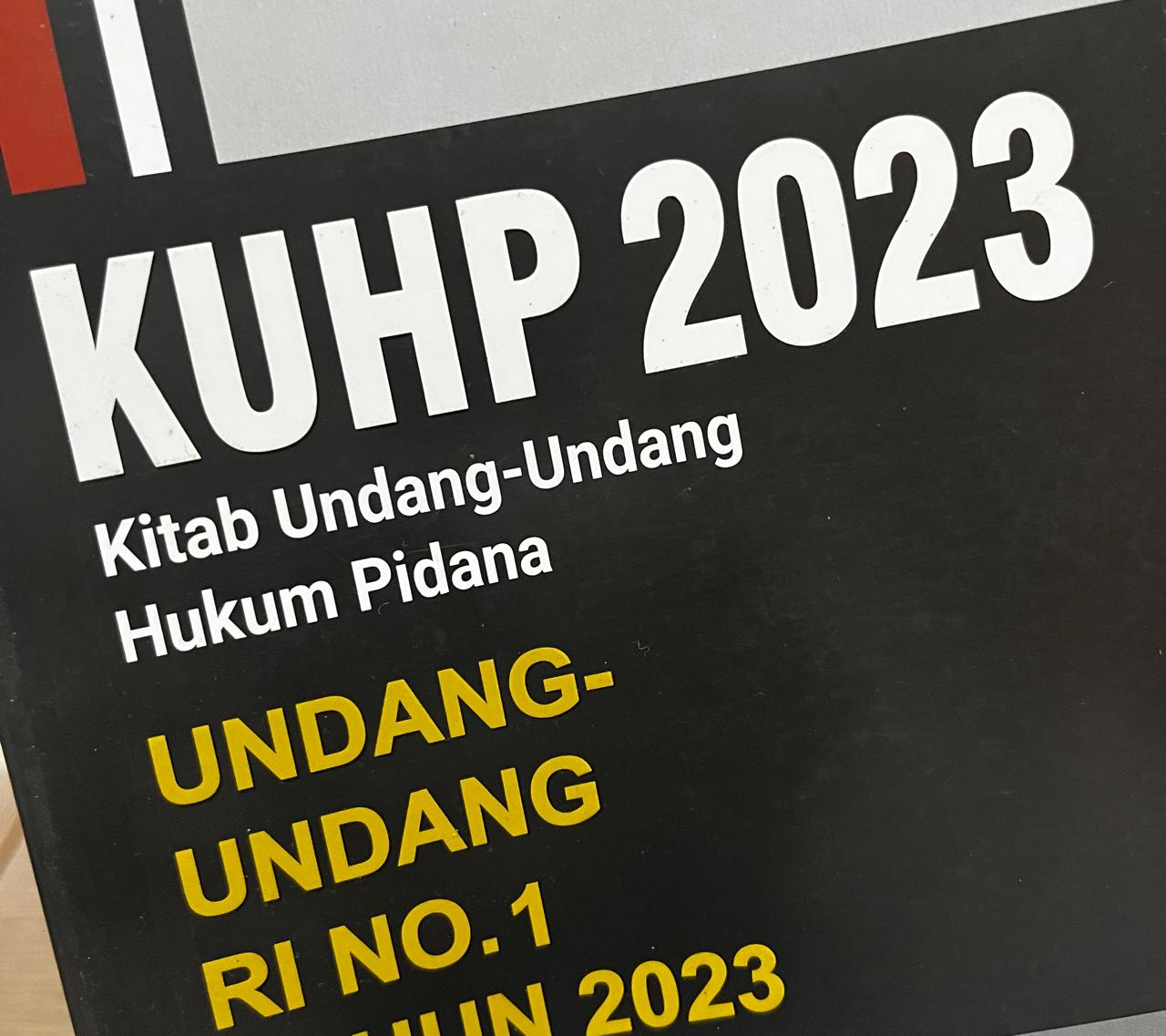Transformasi sistem hukum pidana Indonesia mencapai puncaknya dengan
pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP Baru), yang menandai berakhirnya era dominasi hukum kolonial Wetboek
van Strafrecht (WvS).
Perubahan
ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah upaya
sistematis untuk melakukan dekolonisasi hukum pidana dengan mengintegrasikan
nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan kesadaran hukum masyarakat yang selama
ini terpinggirkan oleh formalisme legalistik.
Salah satu manifestasi paling signifikan dari revolusi paradigma ini
adalah pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living
law) sebagai sumber hukum pidana materiel. Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru
menyatakan bahwa berlakunya asas legalitas formal tidak mengurangi berlakunya
hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut
dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP Baru.
Baca Juga: Interpretasi Pengadilan Atas Hak Tradisional Masyarakat Adat Timor Tengah Selatan
Hal ini menandai pergeseran fundamental dari asas legalitas formal yang
kaku, yang selama ini hanya mengakui undang-undang tertulis sebagai
satu-satunya dasar pemidanaan, menuju keseimbangan dengan legalitas materiel
yang menghargai norma-norma tidak tertulis yang eksis secara otonom di tengah
masyarakat.
Dialektika ini muncul karena adanya kebutuhan untuk menjembatani jurang (gap)
antara kepastian hukum yang bersifat legalistik dan rasa keadilan masyarakat
yang bersifat sosiologis. Pembuat undang-undang menyadari bahwa hukum
tertulis sering kali gagal menangkap dinamika keadilan lokal atau tertinggal
oleh perkembangan zaman.
Dengan mengakui living law, negara berupaya mencegah terjadinya
kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam situasi di mana suatu perbuatan
dianggap sangat tercela menurut standar moral dan adat setempat namun luput
dari rumusan delik dalam hukum positif.
Namun demikian, pengakuan ini membawa tantangan besar terkait bagaimana
menjaga elastisitas hukum adat agar tetap hidup dan dinamis, sembari memastikan
bahwa penerapannya tetap berada dalam bingkai asas legalitas yang memberikan
perlindungan bagi hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
Sebagai instrumen operasional untuk menjalankan mandat Pasal 2 ayat (3)
KUHP Baru, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025
tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (“PP
55/2025”). PP 55/2025 merupakan instrumen yang memberikan kejelasan prosedural
terhadap pengakuan living law itu sendiri.
Peraturan ini memposisikan negara sebagai fasilitator sekaligus pengawas
terhadap eksistensi hukum adat. Melalui PP ini, pemerintah menetapkan
bahwa pengakuan hukum adat tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus
melalui proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan dalam bentuk Peraturan
Daerah (Perda). Regulasi ini menjadi pedoman krusial bagi pemerintah daerah
dalam merumuskan Perda yang akan menjadi wadah formalisasi bagi tindak pidana
adat.
Berdasarkan Pasal 4 PP 55/2025, living law yang dapat diakui harus
memenuhi kriteria kumulatif yang ketat, yaitu: a) sesuai dengan nilai-nilai
dasar (Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang
diakui masyarakat bangsa-bangsa); serta b) diakui dan dilaksanakan oleh
masyarakat hukum adat setempat yang keberadaannya telah diakui dan ditetapkan
sesuai Permendagri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat. Kriteria ini berfungsi sebagai filter agar hukum adat
tetap selaras dengan cita-cita negara hukum modern.
Selain kriteria umum yang telah disinggung di atas, perbuatan tertentu
yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adat juga harus memenuhi syarat
kumulatif yang disebutkan dalam Pasal 5 PP 55/2025 yaitu: a) bersifat melawan
hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat; b) diancam
dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat; c) tidak diatur dalam KUHP Baru,
di mana hal ini merupakan prinsip subsidiaritas yang sangat penting. Jika suatu
perbuatan sudah diatur dalam KUHP Baru, maka ketentuan dalam KUHP Baru yang
harus dikedepankan, meskipun terdapat aturan adat yang mengatur hal serupa
(lihat Pasal 3 PP 55/2025); serta d) berlaku bagi setiap orang yang melakukan
tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut.
Pengaturan sanksi terkait penanganan dan penyelesaian tindak pidana adat juga
dibatasi secara tegas dalam Pasal 15 PP 55/2025. Pemenuhan kewajiban adat untuk
subjek hukum perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II
dalam KUHP Baru yaitu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan
untuk subjek hukum korporasi, pemenuhan kewajiban adatnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Perda setempat.
Tujuan utama dari pengakuan living law adalah untuk
memberikan ruang bagi keadilan restoratif yang berakar pada
tradisi. Namun, terdapat paradoks yang mendalam ketika hukum adat yang
sifatnya cair dan senantiasa beradaptasi dipaksakan masuk ke dalam instrumen
hukum tertulis seperti Perda.
Hukum adat memiliki elastisitas karena ia tumbuh dari kebiasaan dan
kesadaran hukum masyarakat yang dinamis. Begitu ia dikodifikasikan dalam Perda,
hukum tersebut menjadi statis dan kehilangan kemampuan untuk merespons
perubahan sosial secara cepat. Bagi aparat penegak hukum, keberadaan Perda
memang memberikan kepastian mengenai perbuatan apa yang dilarang, namun bagi
masyarakat adat, hal ini bisa berarti hilangnya "roh" hukum adat yang
fleksibel.
Untuk menjaga elastisitas ini, hakim sebagai gerbang terakhir keadilan
dituntut untuk tidak hanya menjadi "corong undang-undang" (la bouche
de la loi). Hakim tetap wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat melampaui apa yang sekadar
tertulis dalam Perda. Perda seharusnya dipandang sebagai "pintu
masuk" atau standar minimum, bukan sebagai batas akhir dari pencarian
keadilan substantif.
Pengakuan hukum adat sebagai pengecualian terhadap asas legalitas formal
melalui Pasal 2 KUHP Baru dan prosedur operasional dalam PP 55/2025 merupakan
upaya serius yang bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih
berkeadilan dan kontekstual.
Formalisasi melalui instrumen Perda merupakan keniscayaan untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam
sistem negara hukum modern. Namun, proses ini harus dikawal secara ketat agar
tidak berubah menjadi instrumen yang mematikan elastisitas dan sifat dinamis
hukum adat.
Baca Juga: Pembaharuan KUHP Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Keberadaan Hukum Pidana Adat
Penjagaan terhadap elastisitas tersebut terletak pada 3 (tiga) pilar
utama, yakni:
- Partisipasi
Bermakna (Meaningful Participation), menjamin bahwa masyarakat hukum
adat bukan sekadar objek, melainkan subjek aktif yang menentukan arah
formalisasi hukum mereka sendiri;
- Verifikasi
Konstitusional (Constitutional Verification), memastikan bahwa hukum
adat tidak melampaui batas-batas kemanusiaan, demokrasi, persatuan nasional,
dan nilai-nilai fundamental lainnya; serta
- Aktivisme
Yudisial (Judicial Activism), mendorong hakim untuk menjadi penjaga
nilai dan penggali rasa keadilan substantif, melampaui kekakuan teks Perda.
Dengan demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional tidak
boleh berarti asimilasi yang menghilangkan identitas unik tiap masyarakat.
Sebaliknya, hal ini harus dimaknai sebagai hibridisasi hukum yang menggabungkan
kepastian hukum negara dengan kearifan lokal masyarakat. Keberhasilan
implementasi PP 55/2025 pada akhirnya akan ditentukan oleh niat tulus semua
pemangku kepentingan untuk menempatkan hukum sebagai pelayan manusia, guna
mewujudkan kedamaian dan keseimbangan sosial yang sejati di seluruh bumi
Nusantara. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI