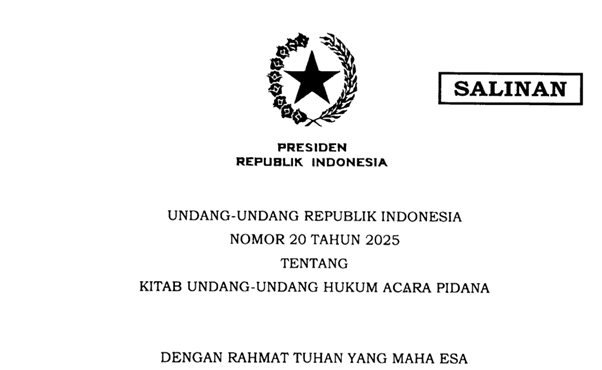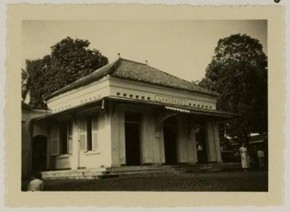Penahanan selalu dianggap lahir dari situasi mendesak. Negara bertindak pada fase ketika proses hukum belum mencapai kepastian, tetapi konsekuensinya sudah nyata bagi individu yang dikenai tindakan tersebut. Pada tahap inilah hukum acara pidana memperlihatkan wajah paling serius dari kekuasaan negara, kebebasan seseorang dapat dicabut sebelum kesalahan dipastikan melalui putusan pengadilan.
Dampaknya jarang
bersifat sementara. Penahanan kerap mengubah posisi sosial, relasi profesional,
dan bahkan arah pembelaan sejak awal perkara berjalan. Oleh karena itu,
perubahan norma penahanan tidak cukup dibaca sebagai pembaruan teknis,
melainkan harus dipahami sebagai penegasan sikap negara tentang batas
kewenangan yang layak dijalankan.
KUHAP baru membawa
perubahan penting pada titik ini. Jika Pasal 21 KUHAP lama bertumpu pada frasa
“keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”, Pasal 100 ayat (5) KUHAP baru memilih
pendekatan berbeda dengan merinci alasan penahanan ke dalam sejumlah perilaku
tertentu. Perubahan ini sering diasumsikan sebagai langkah menuju objektivitas.
Namun hukum acara tidak bekerja hanya melalui rumusan normatif. Pertanyaan yang
lebih mendasar adalah apakah perincian tersebut benar-benar membatasi
subjektivitas, atau justru memindahkannya ke bentuk yang lebih tersusun.
Baca Juga: Quo Vadis Penahanan Terdakwa Dalam Masa Transisi KUHAP Baru
Subjektivitas lama:
prediksi yang jarang diuji
Dalam rezim KUHAP
lama, penahanan diletakkan dalam kerangka penilaian ke depan. Aparat diminta
memperkirakan risiko yang mungkin muncul apabila tersangka tidak ditahan,
seperti potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi
tindak pidana. Penilaian semacam ini bersifat antisipatif dan tidak selalu
keliru. Namun persoalannya terletak pada fondasi penalarannya.
Kekhawatiran tidak
disyaratkan untuk hadir sebagai peristiwa konkret. Cukup hadir sebagai
kemungkinan. Akibatnya, batas antara penilaian profesional dan asumsi menjadi
kabur. Dalam praktik, frasa “menimbulkan kekhawatiran” sering tampil sebagai
alasan yang seragam dalam berbagai perkara, tanpa penjelasan individual
mengenai mengapa kekhawatiran itu relevan pada kasus tertentu.
Dalam situasi
seperti ini, penahanan berisiko bergeser dari langkah pengecualian menjadi
respons yang lazim dipilih. Bukan semata karena selalu diperlukan, tetapi
karena dianggap paling aman secara prosedural dan institusional (Packer, 1968).
Subjektivitas aparat tidak disaring melalui mekanisme pengujian yang ketat,
melainkan diterima sebagai bagian dari kebiasaan praktik.
Objektifikasi baru
dan pergeseran wajah subjektivitas
KUHAP baru mencoba
memutus pola tersebut. Alasan penahanan tidak lagi diletakkan pada apa yang
dikhawatirkan, melainkan pada apa yang dilakukan. Secara normatif, ini sejalan
dengan gagasan pembatasan kekuasaan negara melalui kriteria yang lebih terukur
dan dapat diuji (Ashworth, 2006).
Namun perincian
tidak identik dengan objektivitas. Banyak indikator dalam Pasal 100 ayat (5)
tetap membutuhkan penilaian. Memberikan informasi tidak sesuai fakta,
menghambat pemeriksaan, atau mempengaruhi saksi bukanlah peristiwa yang selalu
jelas batasnya. Ia menuntut tafsir, konteks, dan penilaian niat.
Pada titik ini,
subjektivitas tidak lenyap namun dapat dikatakan berganti rupa. Jika sebelumnya
aparat menebak apa yang mungkin terjadi, kini aparat menilai makna dari apa
yang telah terjadi. Subjektivitas berpindah dari wilayah prediksi ke wilayah
evaluasi.
Ilusi objektivitas
dan bahaya checklist normatif
Perincian alasan
penahanan dalam KUHAP baru menyimpan satu risiko yang tidak selalu disadari,
yaitu munculnya kesan seolah-olah keputusan penahanan telah sepenuhnya objektif
karena didasarkan pada daftar perilaku tertentu. Dalam praktik, daftar semacam
ini mudah diperlakukan sebagai daftar centang: cukup satu indikator dianggap
terpenuhi, maka penahanan dipandang sah.
Masalahnya bukan
pada keberadaan daftar itu sendiri, melainkan pada cara daftar tersebut
digunakan. Ketika penafsiran terhadap indikator dilakukan secara longgar,
penahanan kembali menjadi mudah dibenarkan. Bedanya, justifikasi tersebut kini
tampil lebih sistematis dan normatif.
Dari sudut pandang
penalaran keputusan, kondisi ini rentan terhadap kecenderungan mencari
pembenaran atas keputusan yang telah terbentuk sebelumnya. Ketika aparat sejak
awal merasa bahwa penahanan diperlukan, perilaku tersangka kemudian dibaca
untuk menguatkan kesimpulan tersebut, sebuah pola yang dalam psikologi kognitif
dikenal sebagai confirmation bias (Kahneman, 2011).
Risiko yang lebih
serius muncul ketika penggunaan hak justru ditafsirkan sebagai hambatan.
Perbedaan keterangan, sikap berhati-hati dalam pemeriksaan, atau pendampingan
penasihat hukum dapat dengan mudah dimaknai sebagai tindakan menghambat proses.
Padahal, dalam sistem peradilan yang menjunjung keadilan prosedural, hak
pembelaan bukanlah gangguan, melainkan bagian esensial dari proses yang adil
(Duff et al., 2007).
Praperadilan: dari
pengesahan ke pengujian
Di sinilah
praperadilan seharusnya mengambil peran yang lebih tegas. KUHAP baru secara
implisit menggeser praperadilan dari sekadar penguji administrasi menjadi
penguji rasionalitas penahanan. Hakim tidak cukup memeriksa apakah salah satu
huruf Pasal 100 ayat (5) disebutkan. Yang harus diuji adalah apakah alasan
tersebut berdiri di atas fakta konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.
Objektivitas hakim
tidak lahir dari sikap netral pasif, melainkan dari metode pengujian. Dalil
“menghambat pemeriksaan” harus diterjemahkan ke dalam perbuatan nyata, waktu
kejadian, dan dampaknya terhadap proses hukum. Penilaian harus bergerak dari
label ke peristiwa.
Selain itu, hubungan
kausal perlu diuji. Tidak setiap perilaku yang tidak menyenangkan aparat
benar-benar mengancam proses peradilan. Hakim perlu memisahkan antara risiko
nyata dan ketidaknyamanan prosedural. Di titik ini, penahanan diuji bukan hanya
sah atau tidak sah, tetapi perlu atau tidak perlu.
Uji proporsionalitas
menjadi elemen yang tidak bisa ditawar. Penahanan harus diposisikan sebagai
langkah terakhir. Jika tujuan dapat dicapai dengan mekanisme yang lebih ringan,
maka pencabutan kebebasan kehilangan justifikasinya. Hakim juga perlu sensitif terhadap
irisan antara alasan penahanan dan hak tersangka. Penggunaan hak tidak boleh
dengan mudah direduksi menjadi alasan penahanan.
Dengan kerangka tersebut,
penahanan menjadi ujian etika hukum acara pidana. KUHAP baru menuntut lebih
dari sekadar kepatuhan pada pasal tetapi juga menuntut disiplin berpikir.
Semakin rinci alasan penahanan dirumuskan, semakin besar tanggung jawab penegak
hukum, terutama hakim, untuk memastikan bahwa rincian itu tidak diperlakukan
secara mekanis.
Penutup
Perubahan dari “kekhawatiran”
ke “daftar perilaku” dalam KUHAP baru adalah langkah penting. Namun perubahan
bahasa tidak otomatis mengubah cara berpikir. Tanpa kesadaran akan risiko bias
subjektif, daftar alasan penahanan hanya akan menggantikan frasa lama tanpa
memperbaiki praktik.
Pertanyaan dalam
judul tulisan ini sengaja tidak dijawab secara tegas. Apakah subjektivitas
benar-benar hilang? Jawabannya tidak terletak pada teks undang-undang,
melainkan pada keberanian untuk menguji alasan penahanan secara kritis. Di
sanalah praperadilan menemukan maknanya, dan di sanalah martabat hukum acara
pidana dipertaruhkan. (np/snr/ldr)
Daftar bacaan
Ashworth, Andrew. Human
Rights, Serious Crime and Criminal Procedure. London: Sweet & Maxwell,
2006.
Kahneman, Daniel. Thinking,
Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
Baca Juga: Pembantaran (Stuiting): Permasalahan dan Solusi Praktis
Packer, Herbert L. The
Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press, 1968.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI